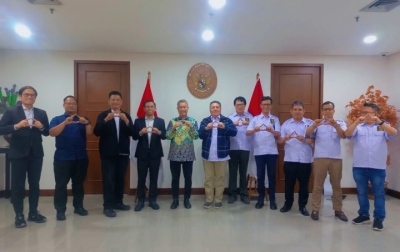Oleh: Roy Martin Simamora. Ada yang menarik pasca debat ketiga Cawapres tempo hari. Dari empat tema yang diangkat—pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya, satu tema yang menarik dibahas mengenai tema pendidikan. Tapi sayang, sebagai penonton, saya kecewa karena tema ini tidak terlalu serius dibicarakan ketimbang tema-tema yang lain. Tema pendidikan justru porsinya lebih sedikit.
Sebagai penonton dan peduli pendidikan, tema pendidikan seharusnya menjadi concern bersama oleh kedua cawapres. Bukankah sebuah bangsa besar karena dilihat dari keberhasilan mengelola sektor pendidikannya?
Tapi, panggang jauh dari api, debat malam itu tidak menyentuh akar persoalan. Tema pendidikan tidak tepat sasaran. Perdebatan malah membahas alokasi dana riset dan industri ketimbang membahas persoalan pelik pendidikan kita dari tingkat yang paling bawah.
Mekipun demikian, saya cukup mengapresiasi concern Cawapres 02 yang berinisiatif menghapus Ujian Nasional (UN) apabila seandainya diberikan mandat untuk memimpin bangsa ini. Pertanyaan besarnya: semudah itukah menghapus UN? Seandainya terpilih dan wacana menghapus UN terealisasi, maka “tools” apa yang akan hendak dipakai untuk mengukur kompetensi siswa ke depannya? Ini menjadi pertanyaan besar mengingat wacana menghapus UN sudah digaungkan oleh presiden-presiden sebelumnya, namun nyatanya sebatas wacana belaka. Tidak ada satupun presiden yang berani menghapus UN. Sampai sekarang UN berdasarkan tes tulis hingga UN tes komputer masih dilaksanakan.
Problem UN terus saja menjadi polemik. UN dinilai belum mampu mengatasi persoalan kualitas siswa. UN dinilai hanya mengedepankan asas kejujuran ketimbang menguji potensi peserta didik agar mampu berpikir kritis. Masalah lainnya, gap antara pendidikan di desa dan kota sungguh mengkhawatirkan. Pemerataan pendidikan belum dilakukan sepenuh hati. Terkesan setengah-setengah.
Belum lagi, pemerintah sudah membuat kebijakan baru: Ujian Nasional (UN) diganti dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Belum selesai masalah yang satu muncul lagi masalah baru. Padahal kita tahu, fasilitas di desa belum tentu memadai daripada di kota. Sekolah di desa mengalami kendala karena tidak memiliki akses internet. Boro-boro bicara akses internet cepat, sedangkan penyediaan komputer masih memprihatinkan. Dana BOS yang seharusnya peruntukan pengembangan akademik sekolah justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
Bersebab itu, pihak sekolah putar otak, caranya membawa siswa ke kabupaten yang menyediakan pelayanan akses internet cepat agar dapat ikut ujian. Tapi, apakah itu menyelesaikan masalah pendidikan? Tidak. Ini justru menambah beban sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Dan tentu saja, pemerintah masih belum bisa menyelesaikan persoalan itu.
Jika berkaca dari pelaksanaan UN, saya berpendapat sebaiknya UN digunakan sebagai pemetaan kualitas siswa dan sekolah diberbagai daerah, bukan untuk mengukur hasil belajar siswa semata. Disamping itu, UN tidak perlu dijadikan sebagai acuan atau “jalan” masuk Perguruan Tinggi (PT). Karena tidak ada jaminan, siswa yang masuk perguruan tinggi kualitasnya lebih baik dibandingkan siswa yang tidak.
Untuk mencapai skor tertinggi, siswa-siswa harus belajar, les privat dan bimbingan intensif. Hal ini membuat, para siswa berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Demikian kegiatan ini berulang-ulang tiap tahunnya. Bagi siswa yang penting adalah “lolos” UN tidak peduli dengan esensi pendidikan itu sendiri.
Melihat problem-problem pelaksaaan UN yang dijadikan sebagai acuan masuk perguruan tinggi (PT), yang mana banyak kecurangan seperti “pengkatrolan nilai” agar lolos ke perguruan tinggi yang diidamkan. Sekolah bermain curang demi meloloskan para siswanya ke perguruan tinggi. Tentu, ini menjadi nilai tambah sekolah agar meningkatkan rating. Sekolah berlomba-lomba mengejar “rating” meski dengan cara-cara yang tidak bijaksana. Karena itu, saya lebih setuju apabila program penelusuran minat dan bakat direalisasikan jika masuk ke Perguruan Tinggi (PT) bukan berdasar pada nilai UN semata.
Belajar dari Taiwan
Taiwan termasuk negara yang tidak terlalu memusingkan Ujian Nasional (UN). UN tidak menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan. Jika ditelisik, Taiwan sangat peduli dengan persoalan-persoalan pendidikan. Negara ini bahkan termasuk negara yang diperhitungkan dan dinilai terus-menerus membenahi sektor pendidikan. Berdasarkan peringkat Program for International Student Assessment (PISA) dari tahun ke tahun, Taiwan masuk lima besar secara berturut-turut. PISA ini memfokuskan pada tiga bidang ilmu: Matematika, Sains, Membaca.
Jadi, Taiwan tidak boleh dipandang sepele dalam hal membenahi persoalan pendidikan. Bagaimana dengan bangsa kita?
Bagi Taiwan, UN pernah jadi cerita buruk dan momok yang mengerikan. Banyak siswa yang depresi, stress karena beratnya UN, akhirnya tak sedikit yang bunuh diri. Karena itu, pemerintah Taiwan mengambil langkah cepat dan tepat untuk mencegah lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. UN tidak lagi dijadikan patokan untuk meluluskan siswa dan jalan masuk PT, terutama menembus PT terbaik di Taiwan.
Berdasarkan kisah-kisah yang dituturkan beberapa teman: adalah sebuah pride bagi siswa dan keluarga apabila anggota keluarganya mampu menembus PT terbaik di Taiwan. Jika tidak, nama baik menjadi taruhannya. Bayangkan, berapa banyak siswa yang akan mengubur harapan mereka masuk PT idaman karena tidak sanggup atau sulitnya tes Ujian Nasional? Jika skor buruk pada tes ujian, dapat dipastikan tidak akan masuk perguruan tinggi yang diminati. Menyikapi itu, Taiwan, dari tahun ke tahun terus memperbaiki kualitas pendidikannya agar lebih humanis.
Menariknya, para guru di Taiwan diharapkan agar berpartisipasi dalam merancang kurikulum dan membuat praktik pedagogis yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka. Dengan kata lain, administrator dan guru sekarang memainkan peran penting dalam mengembangkan kurikulum dan mempraktikkannya.
Jadi, pemerintah tidak melulu paling tahu problem siswa di sekolah. Pemerintah memberikan kebebasan bagi sekolah untuk mengembangkan akademik dan mutu pendidikan. Bagi Taiwan, kurikulum terbaik adalah antara guru dan siswa.
Begitu banyak sentimen negatif terhadap ujian nasional waktu itu, karena banyak siswa mengklaim ujian itu tidak adil karena tidak memungkinkan mereka untuk masuk universitas yang mereka inginkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka akan ditempatkan di perguruan tinggi berdasarkan skor yang mereka peroleh dalam ujian nasional. Jika skor rendah berpotensi masuk perguruan tinggi yang biasa-biasa saja. Bagi siswa yang memiliki skor tinggi ada kemungkinan bagi mereka masuk perguruan tinggi terbaik. Situasi inilah yang membuat banyak siswa ingin penghapusan ujian nasional karena merasa tidak adil sama sekali.
Sekolah menengah atas (SMA) mencakup kelas 10 hingga 12 di sekolah menengah akademik dan kejuruan seperti yang digambarkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa siswa dapat memilih untuk mendaftar pada sekolah alternatif, yang disebut program komprehensif, sekolah menengah berbasis khusus, atau perguruan tinggi junior.
Program komprehensif menawarkan kurikulum kejuruan dan akademik dan program berbasis spesialisasi menawarkan kurikulum inti yang menampilkan mata pelajaran atau jalur khusus untuk siswa dengan bakat khusus.
Siswa di sekolah menengah atas (SMA) akademik dan kejuruan tidak perlu lulus ujian komprehensif akhir untuk lulus, tetapi jika mereka ingin melanjutkan studi akademik di universitas, mereka harus mengikuti University Entrance Examinations (Ujian Masuk Universitas), yang mana memuat Tes Kemampuan Skolastik Umum (GSAT).
Tes ini menilai kompetensi mereka dalam bahasa Cina, bahasa inggris, matematika, dan ilmu alam dan sosial. Karena itu, penerimaan ke perguruan tinggi dan universitas didasarkan pada salah satu dari tiga metode berbeda: rekomendasi, aplikasi pribadi, atau ujian dan penempatan.
Dalam proses rekomendasi, siswa diterima di universitas tertentu berdasarkan hasil GSAT, kinerja SMA, dan referensi dari staf sekolah menengah. Jalur rekomendasi terbatas untuk beberapa kandidat yang berkinerja tinggi. Dalam proses aplikasi pribadi memungkinkan siswa untuk mendaftar ke lembaga yang ingin mereka hadiri berdasarkan hasil GSAT dan kinerja sekolah menengah mereka.
Dalam proses pemeriksaan dan penempatan dirancang untuk siswa yang gagal mendapatkan penerimaan berdasarkan metode yang disebutkan di atas. Siswa-siswa ini dapat mengikuti Tes Mata Pelajaran Tingkat Lanjut (AST), yang menilai kompetensi mereka dalam mata pelajaran khusus yang berkaitan dengan jurusan dan departemen di mana mereka ingin belajar. Berdasarkan hasil GSAT dan AST dan kinerja sekolah menengah mereka, siswa ditugaskan ke sebuah lembaga di daftar pilihan mereka.
Nah, hebatnya lagi, di semua sekolah di Taiwan, baik di pedesaan dan perkotaan mendapat pendidikan yang layak dan merata. Kebutuhan pendidikan disesuaikan dengan kultur yang berada di setiap daerah. Jadi, kurikulum tidak terlalu kaku untuk direalisasikan.
Sebagai contoh: sebuah sekolah dasar yang pernah saya kunjungi dan teliti di sekitar Taman Nasional Taroko, Hualien, Taiwan menyesuaikan konten pendidikan mereka dengan kebudayaan peradaban yang ada disitu. Sekolah itu mayoritas diisi oleh siswa yang berasal dari suku asli Taiwan. Yang mana suku ini sangat dekat dengan alam, baik berburu binatang, mengajari siswa agar dapat bertahan hidup, mengajari siswa berenang di sungai, mengajak anak melestarikan tarian tradisional, bermain musik tradisional, menggambar tumbuhan dan binatang, maupun mengajari anak cara membangun tempat tinggal di sekitar hutan. Maka, konten pendidikan yang diajarkan disesuaikan dengan person dan kebudayaan mereka, tidak melulu disamaratakan seperti yang dilakukan sekolah di perkotaan. Akhirnya, pendidikan yang ada di tiap daerah tercapai dengan baik.
Dengan demikian, wacana menghapus UN sepenuhnya bukanlah solusi yang tepat. Saya pikir, sebaiknya UN dijadikan (ingat) sebagai pemetaan kualitas pendidikan bukan sebagai acuan keberhasilan siswa dalam menjawab soal-soal. Disamping itu, pemerintah perlu terus berbenah diri. Konsep pendidikan mesti dipandang sebagai kebutuhan publik, mulai dari tingkat yang paling awal: sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sejatinya, esensi pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang berpikir, kreatif, humanis dan menghargai kehidupan, bukan menciptakan mereka menjadi “robot-robot” pendidikan yang selalu diatur demi kepuasan penguasa.***
Penulis Alumnus Hua-Shih College of Education, National Dong Hwa University, Taiwan.