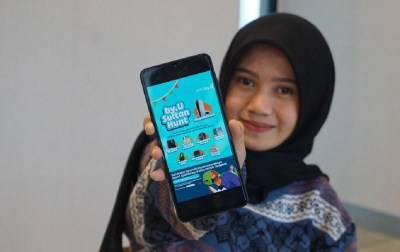Oleh: Roy Martin Simamora.
Sejarah telah mencatat, ada banyak contoh pemimpin yang hidup dengan syahwat berkuasa, diktator dan berakhir dengan kejatuhan. Adolf Hitler adalah salah satu dari sekian banyak pemimpin dunia—tidak berlebihan menyebutnya sebagai sang megalomaniak. Dalam tindak-tanduknya, kehidupan dan kepribadian Hitler tertuang jelas dalam catatan-catatan agitatif dan bukunya Mein Kampf (Perjuanganku). Jika dibaca, ada sesuatu keinginan untuk berkuasa kelewat batas, merasa superior dan akhirnya memicu holocaust (pemusnahan terhadap ras lain). Dalam buku itu, Hitler mengklaim bahwa Tuhan yang memilihnya untuk menjalankan misi tersebut. Karenanya, ia ingin Jerman menjadi “Lord of the Earth” di bumi (Tuan). Apakah tokoh diktator seperti Hitler atau kurang lebih sama masih hidup di zaman sekarang? Mungkin masih ada atau mungkin tidak ada lagi, meski beberapa gejala megalomania sudah mulai menjangkiti beberapa tokoh politik sekarang ini. Terbukti di antaranya menemui kejatuhan kekuasaan yang menyedihkan.
Sang Megalomaniak
Dua tahun silam, The Washington Post pernah sekali menurunkan sebuah opini bertajuk “This new report confirms that Trumps’s megalomania threatens our democracy,” yang ditulis oleh Greg Sargent. Surat kabar itu meneliti bagaimana, lebih dari setahun masa kepemimpinan Trump, terus menolak bukti bahwa Rusia mendukung pencalonannya sebagai presiden Amerika. Dalam tulisan itu, Megalomania Trump dianggap dapat mengancam demokrasi Amerika. Sargent, dalam tulisannya itu, melaporkan Trump dalam berbagai cara mendelegetimasi kebebasan pers; ketidakmampuan mengakui bahwa perilakunya mengarah langsung ke penyelidikan khusus terhadap Rusia dan mencoba menutupi penyelidikan tersebut dari publik. Hal inilah yang memicu banyak kemarahan publik Amerika. Tepat sebelum Trump dilantik sebagai Presiden, laporan itu mengatakan para penasehatnya mendesak Trump secara terbuka mengakui temuan intelijen AS bahwa Rusia berusaha menyabotase demokrasi Amerika. Sargent menyebut Trump “became agitated” atas laporan itu. Saya pikir, ada alasan mengapa Sargent menyebut Trump demikian. Trump kemudian mencerca intelijen AS karena tidak bisa dipercaya dan menganggap bahwa pencalonannya didorong oleh bantuan tim sukses selain strategi, pesan dan karismanya sendiri.
Sebelum menjadi Presiden Amerika, ia pernah mengeluarkan sebuah slogan “Make America Great Again.” Slogan yang digunakan selama kampanye presiden tiga tahun silam. Slogan yang banyak dibicarakan publik Amerika. Sebagian publik menilai ia meniru slogan kampanye mantan Presiden Amerika, Ronald Reagan “Let’s Make America Great Again” pada tahun 1980. Melalui slogan itu pula, Reagan sukses membawa dirinya menjadi presiden Amerika. Trump menyiratkan Amerika tidak pernah hebat. Ia sangat yakin Amerika akan menjadi bangsa yang besar dibawah kepemimpinannya kelak. Trump mengklaim dapat membuat Amerika menjadi bangsa yang besar dengan kebijakan-kebijakan yang akan direalisasikan seandainya terpilih. Beberapa orang bahkan menganggap itu hal yang konyol, utopis dan delusional. Sebagian orang juga berpendapat Amerika tidak pernah secara khusus “great.” Mereka justru mempertanyakan apa arti kata “great” tersebut.
Sebelum dan sesudah terpilih menjadi Presiden Amerika, Trump dikenal sebagai tokoh yang sarat kontroversial. Bahkan, ia jauh lebih kontroversial ketika sudah terpilih. Dikenal sebagai presiden kontroversial karena kerapkali melontarkan komentar pedas, sindiran, makian bahkan merembes ke penghinaan. Media Amerika bahkan mengkritik habis-habisan Trump karena sifat dan gaya kepemimpinannya tidak menggambarkan wajah Presiden Amerika. Media bahkan berusaha menganalisis secara kritis setiap twit Trump di media sosial. Media lebih fokus kepada kepribadian Trump yang narsistik setiap pidato dan hubris (sombong) ketimbang mengkritik kebijakan-kebijakan Trump pada Amerika. Dan, dengan melakukan itu, media massa Amerika telah merasa melahirkan mengalomaniak pertama Amerika presiden selebritas.
Imaji Megalomaniak
Imaji megalomania tidak hanya terjadi pada Trump. Bedanya, di Indonesia, gejala ini mewabah ke beberapa elit politik. Sebagai contoh: sebagian dari mereka memuji diri karena lahir dari darah tokoh pendiri bangsa. Atau, merasa “besar” dari partai yang didirikan oleh tokoh penting tertentu. Ada pula yang beramai-ramai menumpang tenar pada salah seorang tokoh untuk meraup keuntungan politik. Lengkap dengan atribut dan simbol-simbol ketokohan. Sebagian elit politik justru berupaya meniru pesona seorang presiden agar terlihat berwibawa dan karismatik. Tidak ada orisinalitas diri yang ditawarkan, tidak ada pertarungan gagasan yang pure (murni) dan kurang percaya diri. Kasus di atas adalah beberapa contoh yang sudah menjadi rahasia umum dalam konstelasi perpolitikan Indonesia.
Nostalgia terhadap era kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya juga sering ditonjolkan. Saya kira, ini bukan barang baru. Masih banyak orang menilai masa-masa kepemimpinan mereka (presiden sebelumnya) menggambarkan bahwa Indonesia sudah menjadi negara hebat. Saya kira, semua orang bebas menginterpretasikan kepemimpinan tiap-tiap presiden di masanya. Sah-sah saja. Boleh jadi mengkritik dan memberikan perspektif baru ihwal tatanan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, jangan berlebihan menyalahkan orang lain dan mendewakan orang lain atau memuji diri terlalu tinggi. Ada semacam delusional yang membelenggu kepala elit perihal kejayaan presiden-presiden sebelumnya. Delusional seperti anggapan kepemimpinan zaman sekarang tidak pernah sama sekali mengulang kembali kejayaan presiden sebelumnya dan mesti segera diganti - lengkap dengan tagar-tagar. Padahal, tiap presiden pernah besar di zamannya masing-masing. Ada yang dianggap buruk dan ada yang dianggap baik oleh sebagian orang. Tiap presiden memiliki porsi masing-masing: baik kekurangan dan kelemahan. Tiap presiden punya cara tersendiri dalam mengelola negara dan menjadikannya negara “besar” dalam kepala mereka. Tidak ada pemimpin yang sempurna 100 persen.
Tapi, seperti apa wajah negara “besar” itu? Cukupkah dengan gagasan belaka atau hanya angan-angan belaka dalam kepala? Atau, cukupkah dengan menjadi bangsa Indonesia masuk deretan ekonomi terbaik dunia, tetapi lupa mengurus rakyat? Cukupkah membuat negara lain terpesona dengan politik luar negeri, tetapi melupakan mencerdaskan anak-anak bangsa? Cukupkah membuat negara maju dalam teknologi informasi, tapi melupakan pemenuhan hak-hak warga negara di daerah-daerah tak tersentuh tangan pemerintah? Apakah dengan membangun infrastruktur secara langsung membuat bangsa kita menjadi “besar?” Lantas, apakah dengan mengganti presiden baru, kemudian membuat bangsa kita menjadi “besar” dalam sekejap mata? Apakah itu gambaran negara “besar” yang sedang kita impikan bersama? Delusi tentang negara besar masih sebatas “imaji” tidak akan serta merta membuat sebuah bangsa besar hanya dengan kata-kata. Dengan perbuatan saja muskil apalagi dengan kata-kata, itu sangat mustahil.
Tetapi, kemuskilan itu bisa terlewati bila bangsa Indonesia, terutama para pemimpin bangsa bersatu, bersungguh-sungguh bahu-membahu, bekerja mengelola negara dengan baik. Usah bermimpi terlalu tinggi. Sebab saya percaya dari kerja-kerja kecil melahirkan sesuatu yang besar. Dalam kepala saya, setiap pemimpin harus benar-benar sadar dan berkomitmen untuk tidak korupsi. Korupsi adalah monster; masalah besar bangsa kita. Korupsi yang membuat pengelolaan negara menjadi terhambat. Tapi, menghilangkan praktik korupsi tidak serta merta secepat kilat. Ia butuh proses yang panjang untuk mengedukasi tiap-tiap elemen bangsa agar tidak bermental korup. Tapi, kadang itu sangat egois. Tidak mudah mengatakan korupsi akan hilang jika mental para pemimpin dan rakyat tidak diperbaiki. Mengelola negara tidak seperti bermain sulap: Bim sala bim! Mesti ada sinergitas antar pemangku kebijakan.
Pemakluman terhadap Narasi Megalomaniak
Jika seseorang secara berapi-api merasa mampu melakukan sesuatu dengan sekejap mata atau mengelola negara menjadi negara “besar” dalam waktu yang singkat, barangkali ia telah terkena gejala megalomania. Impian negara “besar” dalam narasi kampanye kerapkali saya dengar. Ini adalah sound bite bagi siapapun. Sebagai contoh “negara akan hancur apabila dibawah kepemimpinan si A,” “Lebih baik pilih saya kalau tidak mau negara ini hancur,” “Saya lebih baik daripada si A,” “Negara ini akan bubar jika bukan saya yang memimpin.” Atau narasi baru semacam “Saya tidak kalah, saya memang.” Ini salah satu gejala buruk karena tidak merasa kalah dalam kompetisi dan merasa kebenaran hanya ada pada dirinya. Pada konteks ini publik seperti memberikan “pemakluman” dengan kedua narasi yang ditampilkan tadi. Narasi-narasi demikian boleh jadi menjerumus kepada megalomania akut. Seolah-olah, Ia adalah sosok kredibel dan berkompeten, yang mampu membawa kejayaan negeri. Sedangkan, kandidat yang lain tidak punya kompetensi apa-apa. Ciri dari megalomaniak semacam ini adalah Ia terlalu percaya diri, sombong dan tidak percaya pada orang lain.
Celakanya, megalomaniak akan merasa dirinya “istimewa” dan unik, yang dapat dipahami oleh orang (atau lembaga) istimewa atau berstatus tinggi. Membutuhkan kekaguman yang berlebihan, mengambil keuntungan dari orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri, kurang empati: tidak mau mengenali atau mengidentifikasikan perasaan dan kebutuhan orang lain, sering iri pada orang lain atau percaya bahwa orang lain iri padanya, menunjukkan perilaku atau sikap sombong dan angkuh.
Narasi megalomaniak akan berbahaya apalagi menggunakan narasi-narasi agitasi yang memancing persepsi rakyat. Bagi siapapun yang tidak belajar apa-apa mereka akan percaya dan semakin percaya. Mereka akan percaya bahwa negara ini memang akan hancur atau bubar. Pertanyaannya: bagaimana mungkin negara sebesar Indonesia bisa “besar” dalam waktu lima tahun berkuasa? Itu mustahil. Butuh estafet kepemimpinan berjenjang dan waktu yang sangat panjang untuk mewujudkan itu. Tapi dalam narasi politik, semua itu dapat atau pasti terjadi, terutama bagi politisi oportunis. Apapun mereka katakan—tidak peduli konten yang disampaikan baik atau tidak—asal semua kepentingannya berjalan mulus. Tidak lupa dengan mereka yang berhasrat terlalu tinggi dengan jargon bagus: membawa reformasi politik ke arah yang “lebih baik”. Karena itu, tidak dapat dihindari, setiap orang, saya, Anda serta politisi yang kita dengar dan tonton sudah terlahir dengan “tanda-tanda” itu. Tergantung separah apa megalomaniak seperti di atas kerap disuguhkan dihadapan publik.
Tanda-tanda megalomania yang paling sering kita saksikan, ketika menonton tayangan televisi, debat politik, bincang-bincang politik dan wawancara seorang tokoh politik oleh media massa tertentu. Mereka akan berbicara bahwa kandidatnya lebih baik dibandingkan kandidat lawan. Melontarkan narasi kebencian, narasi ketakutan, narasi politik identitas, kabar bohong dan hoax. Sebagaimana politisi yang megalomaniak, para pendukung (simpatisan) juga mengalami hal yang sama. Megalomania juga tidak menutup kemungkinan menyerang pendukung karena tidak memakai nalar sehat dalam menyerap semua informasi. Mana informasi yang harus diserap, mana informasi yang harus ditinggalkan. Merasa jika yang didukung lebih baik daripada yang tidak didukung.
Jadi jelas, megalomania adalah tipe delusional dari kesadaran diri dan perilaku kepribadian yang diekspresikan oleh tingkat ekstrem yang terlalu tinggi akan kepentingan, ketenaran, popularitas, kejayaan, kekuatan, kejeniusan, pengaruh politik, bahkan kemahakuasaan. Karakteristik kelainan ini adalah kemegahan ekstrem, ketidakpedulian terhadap kebenaran (post-truth), ketidakmampuan untuk menerima kritik (anti-kritik) atau melihat orang lain yang memicu dorongan untuk merendahkan entitas sosial (etnosentris) dan meremehkan semua orang yang tidak setuju. Megalomania juga gangguan mental ketika seseorang cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Dalam psikiatri, kondisi ini dianggap bukan penyakit independen tetapi merupakan gelaja kondisi patologis lain yang terkait kejiwaan.
Megalomania paling sering terjadi bersamaan dengan depresi, inferioritas yang kompleks, dan gangguan paranoid. Megalomaniak dalam politik akan tetap ada, hidup bertumbuh dan berkembang dalam demokrasi kita. Kelainan psikologis menjangkiti politisi dengan delusi keagungan dan obsesi terhadap kekuasaan. Megalomaniak akan berperilaku seolah-olah mereka yakin akan kekuatan dan kebesaran absolut politik mereka. Dengan begitu, sang megalomaniak akan berusaha mengklaim kebenaran absolut itu untuk menguatkan legitimasinya karena didorong oleh motif-motif ekonomi dan politik. ***
Penulis adalah Alumnus National Dong Hwa University, Taiwan.