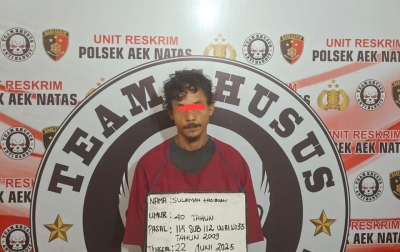Oleh : Anwar Saragih.
Linimasa media sosial kita saat ini sedang dihebohkan oleh pemberitaan ihwal merosotnya harga jual garam konsumsi di tingkat petambak yang jatuh ke posisi Rp400 per Kg, padahal normalnya harga garam konsumsi berada di kisaran Rp 750- Rp 800 per Kg (14/7/2019). Sementara pada pemberitaan yang lain, Kementerian Perindustrian secara rutin melakukan kebijakan impor dari luar negeri. Berbagai spekulasi kemudian bermunculan, utamanya berkaitan dengan rendahnya kualitas garam yang diproduksi oleh para petani garam di Indonesia.
Situasi seperti ini tentu anomali. Sebab, pasti ada yang salah dengan kita ketika Indonesia sebagai negara maritim tapi rutin mengimpor garam setiap tahunnya. Alasannya Indonesia memiliki garis pantai ke-2 (kedua) terpanjang di dunia, dengan panjang 99.093 kilometer seharusnya persoalan kebutuhan garam nasional bisa selalu terpenuhi tanpa ada hambatan. Namun, persoalan tata niaga garam rutin menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Seperti; kelangkaan, harga yang tinggi dan kualitas yang buruk hingga impor garam berjumlah besar terus terjadi. Dimana menurut data Kementrian Perindustrian tahun 2019 menyebutkan dari 3,9 juta ton garam untuk kebutuhan nasional, sebesar 2,7 juta ton harus di impor dari China dan Australia.
Industri manufaktur yang berhubungan dengan sustainbilitas produksi garam nasional menjadi faktor utama mengapa sampai saat ini pemerintah rutin mengimpor garam. Faktor lainnya berkaitan dengan proses produksi yang masih mengandalkan alat tradisional yang membutuhkan waktu 14-20 hari untuk proses pengeringan. Membuat para petani garam rentan mengalami gagal panen karena cuaca yang tidak menentu. Lebih lanjut, dalam proses pengeringan para petani garam masih mengandalkan sinar matahari, pengeruk kayu dan kincir angin.
Padahal Indonesia punya luasan lahan yang sangat besar. Dimana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan; luas lahan tambak garam di Indonesia adalah 26.024 hektar. Dengan asumsi 1 hektar lahan bisa menghasilkan rata-rata 1 ton maka potensi produksi garam yang bisa dihasilkan dalam skala nasional adalah 26 juta ton pertahunnya.
Artinya kita membutuhkan inovasi dalam meningkatkan produksi garam, dari aktivitas yang semula sifatnya tradisional ke arah yang lebih modern untuk mengatasi persoalan impor ini. Apalagi di era revolusi industri 4.0 telah berdampak pada disrupsi teknologi yang mengharuskan semua sektor industri termasuk industri garam harus berbenah mengikuti perkembangan zaman. Lebih lagi, di era ini segala aktivitas industri telah menggunakan big data, teknologi robotic, cloud computing (penyimpanan data di awan) dan internet of things (internet cepat) dalam proses industri dari hulu ke hilir. Konsep Teknologi Industri 4.0 di sektor industri garam tentu menjadi peluang besar sebagai roadmap (peta jalan) dalam sinergitas rencana, target dan capaian industri garam di Indonesia.
Data United States Geological Survey (USGS) tahun 2016 merilis negara-negara produsen garam terbesar di dunia. Dua negara Asia yaitu China dan India masuk dalam 10 (sepuluh) urutan teratas penghasil garam terbesar di dunia. Dimana negara China dengan garis pantai 14.500 kilometer berada di urutan pertama dengan jumlah produksinya sekitar 58 juta ton pertahunnya. Sementara India yang memiliki garis pantai 7.000 kilometer mampu memproduksi garam sebanyak 19 juta ton. Kedua negara tersebut memiliki strategi yang hampir sama dalam hal tata niaga garam dengan memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien. Utamanya dengan memperbaiki kualitas garam yang akan dipasarkan, produsen garam di negara tersebut memastikan kualitas garam yang bersih dan bebas dari kotoran.
Hui Wang, Xuegong Xu & Gaoru Zhu (2015) menulis jurnal yang berjudul ; Landscape Changes and a Salt Production Sustainable Approach in the State of Salt Pan Area Decreasing on the Coast of Tianjin, China” menyebutkan stategi negara China khususnya Kota Tianjin dalam meningkatkan produksi garam adalah merekonstruksi lahan-lahan pertanian garam di pesisir dengan menggunakan teknologi terbaru. Langkah utama adalah bagaimana menghasilkan garam dengan kualitas tinggi dengan Natrium Klorida (NaCL) yang kadarnya mencapai 96-99 persen dengan cara memanfaatkan pesisir laut, teknologi dan bahan kimia yang bisa memangkas waktu pengeringan menjadi 4-6 hari. Kemudian, Banumathi & Nadarajan (2015) menulis jurnal yang berjudul “Marketing Strategies And Practices With Reference To Salt Industries In Tamil Nadu India” menyebutkan strategi produksi dan pemasaran garam di India dilakukan menggunakan teknologi kimiawi untuk menghilangkan kotoran demi mendapatkan kemurnian NaCL sebesar 99,5 persen.
Artinya baik China dan India memiliki pola sama terkait produksi yang mengekstrasikan garam mereka ke laboratorium terlebih dahulu untuk dimodifikasi menjadi butiran halus sehingga menghasilkan kemurnia dan kadar NaCL yang tinggi. Sebab, persoalan utama dari garam yang dihasilkan oleh petani Indonesia adalah terkait kualitas. Pun 60% kebutuhan garam nasional diperuntukkan untuk industri dan sisanya 40% untuk kebutuhan konsumsi.
Teknologi Industri Garam 4.0
Pemerintah memiliki posisi sentral dalam mengatasi persoalan garam di Indonesia. Karena berdampak luas bagi tata niaga garam yang berkaitan dengan relasi produsen dan konsumen di pasar. Apalagi pemerintah memiliki kewenangan terkait kebijakan rekonstruksi, zonasi dan ekstensifikasi lahan pertanian garam yang berdampak langsung kepada petani garam, yang menjadi ujung tombak produksi garam dalam negeri.
Kesimpulannya, pemerintah harus membuat inovasi baru berbasis teknologi industri garam 4.0. Khususnya terkait program revitalisasi lahan yang steril, sistem terpadu dalam pengeringan dan perlindungan risiko bencana alam serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan penggunaan teknologi dalam hal prakiraan cuaca melalui aplikasi gadged (gawai).
Kerjasama antar pemangku kepentingan (stakeholder) terkait komoditas garam, seperti; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan harus dilakukan secara kemitraan. Terutama dalam hal penyajian data yang kerap berbeda antara instansi kementrian yang satu dan lainnya. Artinya kita masih memiliki pekerjaan rumah terkait big data tata niaga garam yang berdampak luas dari hulu ke hilir industrialisasi garam di Indonesia.
Disamping sinergitas antar kementrian tersebut, pemangku kepentingan lainya seperti; pemerintah daerah, pengusaha dan petani garam harus terlibat dan bekerjasama dalam konsep kemitraan. Khususnya mendorong pengusaha dan pelaku Informasi Teknologi (IT) berinvestasi dalam aplikasi teknologi garam 4.0 dengan membentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) garam yang terintegrasi untuk tujuan memenuhi kepastian usaha, infrastuktur pasar dan penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan kemurnian NaCL demi kualitas garam yang tinggi.
Harapannya jika konsep teknologi industri garam 4.0 yang berbasiskan kemitraan ini dilaksanakan, niscaya kedepannya bangsa Indonesia akan bisa swasembada garam. Tercapainya swasembada garam akan menjadi modal yang penting bagi Indonesia sebagai negara maritim menghadapi bonus demografi tahun 2030 dan Indonesia emas tahun 2045. ***
Penulis adalah dosen Ilmu Politik FISIP USU dan Peneliti di Lembaga Penelitian dan Pengembangan FISIP USU.