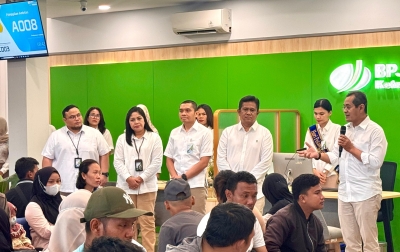Oleh: Jan Roi A Sinaga
PADA awal masa pemerintahan Jokowi-JK pada 2014 lalu, ada secercah harapan bagi bangsa Indonesia lewat slogan yang menggugah perasaan berbangsa saat itu, yakni Revolusi Mental. Kita semua yakin, bahwa salah satu penghambat kemajuan bangsa ini seperti negara-negara maju lainnya di dunia adalah masalah mental rakyat Indonesia.
Mental inferior, menganggap diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan negara lain. Kita langsung minder, dan beranggapan bahwa kita tidak mampu melakukan segala sesuatu yang negara lain telah lakukan. Imbasnya, kita kerap tertinggal selangkah bahkan lebih, dari negara lain perihal kemajuan dibidang teknologi dan pendidikan, misalnya. Sebagai perbandingan, negara kita lebih dahulu merdeka daripada India. Akan tetapi, India sudah berkembang pesat perihal teknologi dan pendidikan.
Program luar angkasa, teknologi informasi, teknologi sistem pertahanan negara, ditambah dengan banyaknya orang India yang telah diakui perusahaan besar dunia seperti Google, Apple, Microsoft dan lain sebagainya menduduki jabatan penting (CEO/COO). Apa yang membedakan kita dengan warga negara India? Masalah mental.
Mental demagogisch, salah satu warisan terbesar Belanda bagi bangsa Indonesia. Disebut warisan, karena sifat demagogisch yang ditinggalkan, sama persis seperti apa yang terjadi di Belanda, yakni suka mempermasalahkan hal sepele, dan mengabaikan pokok utama dari sebuah persoalan yang ada. Seperti yang dituliskan Tan Malaka dalam MADILOG, bahwa mental demagogisch cenderung mempermasalahkan sebuah persoalan, tapi tidak mencari solusi konkrit yang bermanfaat bagi kehidupan.
Sikap seperti inilah yang masih terus kita pelihara hingga kini, yang menjadi batu sandungan bagi bangsa Indonesia untuk terus mengejar ketertinggalannya dari negara berkembang lainnya, menuju era kemajuan. Sehingga, disaat Jokowi-JK diawal-awal pemerintahannya mencanangkan program revolusi Mental, ada secercah harapan bahwa Indonesia berada di gerbang kemajuan. Tetapi, hingga di penghujung periode pertama beliau sebagai Presiden, sudah sejauh manakah keberhasilan program Revolusi Mental yang didengung-dengungkan itu? Melihat situasi bangsa saat ini, tampaknya slogan Revolusi Mental masih sebatas Jargon semata. Belum ada dampak nyata, terutama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Tembok pemecah !
Seandainya pun Jokowi-JK telah benar-benar berupaya untuk merevolusi mental rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka, modern dan siap bersaing diera serba cepat ini, namun selama masih ada saja pihak oposisi yang menghalangi dan terus memelihara mental demagogisch dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka negara kita akan terus seperti ini.
Konflik sosial, Intoleransi, dan perdebatan panjang karena perbedaan pandangan politik, akan terus menjadi berita utama permasalahan negeri ini. Demi kepentingan politik, para elite yang seharusnya bisa menjadi harapan pemersatu bangsa, malah sibuk mencari cara bagaimana agar masyarakat berada pada dua kubu yang berseberangan, dikonfrontir, demi menjaga asa merebut puncak kekuasaan. Seolah-olah hal ini lumrah dalam negara dengan sistem demokrasi, meski pada kenyataannya (mereka) lupa memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Indonesia.
Masyarakat Indonesia yang belum mampu menjadi warga negara seutuhnya pun, akhirnya pasrah digiring kedalam pusaran politik para politisi 'kotor'. Dan kenyataan ini semakin jelas saat periode kepemimpinan Jokowi-JK dimulai, dan masih terus berlangsung hingga saat ini.
Bagi masyarakat yang tergabung dalam barisan oposisi, pemerintahan Jokowi-JK tidak ada benarnya, dan hanya menguntungkan bagi pihak Asing. Semua program pemerintah dianggap lalai, dan pemerintah langsung dicap gagal menjalankan tugasnya sebagai “nakhoda” bangsa ini. Tetapi, bukannya memberikan kritik yang membangun, kelompok ini kerap memberikan “nyinyiran” terhadap kinerja pemerintah. Nyinyir berbeda dengan kritik, karena ia berbasis kebencian, tanpa data dan fakta yang jelas. Tujuannya hanya satu, yakni memberikan cap “gagal” bagi pemerintah, dan mendesak Presiden Jokowi untuk segera mundur.
Apa saja diributkan dan dipermasalahkan, tetapi tidak pernah memberikan solusi yang baik atas sebuah permasalahan yang dikemukakan. Apa saja bisa dipolitisasi, mulai dari Agama hingga suku dan ras. Tujuannya jelas berusaha untuk memberi preseden buruk bagi pemerintahan yang sah.
Tidak ada bedanya dengan masyarakat yang bergabung dalam barisan pemerintah. Meski sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia mendukung pemerintahan yang sah, tetapi ada perbedaan bagi kelompok pro-pemeritahan di negara kita kali ini. Mereka lebih tepat disebut sebagai “die harder” Jokowi-JK, karena all out dalam memberikan pembelaan kepada Presiden atas setiap kebijakannya.
Pemerintahan Jokowi-JK sangat anti kritik bagi mereka, dan siapa saja yang memberikan kritikan atau nyinyiran, bukan lagi prosedur hukum yang berlaku, melainkan bully-an atau persekusi. Pernah satu ketika, CEO Bukalapak (salah satu aplikasi belanja Online di Indonesia) memposting sebuah data “usang” di akun twitternya perihal dana research and development yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain, termasuk Malaysia dan Singapura. Ahmad Zacky menulis harapan, agar “presiden baru” nanti, bisa meningkatkan anggaran R&D demi bersaing di era industri 4.0.
Melihat isi tweet tersebut, relawan Jokowi langsung marah dan mengamuk, menuduh Ahmad Zacky tidak tahu berterimakasih kepada Presiden Jokowi, yang mana beberapa waktu sebelumnya ikut meramaikan HUT Bukalapak, dan mempromosikan Bukalapak sebagai salah satu perusahaan unicorn berbasis aplikasi di Indonesia. Setelah itu, muncul seruan untuk meng-uninstall buka lapak dari gagdet para relawan Jokowi, dan memberi respon bintang satu di google play store
Jelas hal ini berdampak kepada citra Bukalapak sendiri sebagai perusahaan yang sedang bersaing dengan perusahaan serupa. Dengan pandangan negatif para masyarakat, bisa-bisa para investor yang awalnya ingin berinvestasi di Bukalapak, malah mengurungkan niatnya. Dan beberapa waktu lalu, tersiar kabar bahwa Bukalapak akhirnya memberhentikan sebahagian pegawainya. Melihat kenyataan ini, bagaimana perasaan pendukung Jokowi? Bahagia karena ini adalah sanksi atas sindirannya bagi Jokowi, sementara di luar sana ada puluhan bahkan ratusan orang yang mata pencahariannya terganggu?
Terbaru, giliran Tempo yang “diserang” para relawan Jokowi. Perihal tampilan cover majalah Tempo bergambar Presiden Jokowi, dengan bayangan sosok berhidung panjang, yang ditafsirkan sebahagian orang adalah Pinokio. Cover itu menjelaskan kritikan terhadap disahkannya RUU KPK oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah.
Imbasnya? Aplikasi Tempo di Google play store dan AppStore hanya mendapat bintang 1, dan mungkin akan bernasib sama dengan aplikasi Bukalapak yang akhirnya hilang dari Google play store. Saham Tempo pun terjun bebas, dan “diseberang” sana, beberapa buzzer dan relawan Jokowi seolah-olah berteriak bangsa sambil berkata, “siapa suruh kritik junjungan kami?”
Terlepas dari ada atau tidaknya keberpihakan Tempo sebagai sebuah media yang seharusnya netral, bukankah ada baiknya kita balas dengan kritikan disertai data yang tepat? Bukan malah menyerang secara psikis dan membuat sebuah perusahaan nasional, dimana banyak orang Indonesia menggantungkan hidupnya akhirnya menderita, hanya karena ulah sekelompok atau oknum tertentu.
Tidak ada dialektika yang dibangun. Argumen langsung dibantah dengan tindakan “anarkis”. Padahal, jika dicerna dengan pikiran terbuka, kritik dari Bukalapak dan Tempo, bisa dijadikan batu pijakan untuk memperkuat kedudukan Jokowi memimpin bangsa ini. Membalas sajian data, lebih baik dengan data, bukan dengan tindakan yang bisa merugikan semua orang, yang bahkan tidak ikut andil dalam sengketa pilihan politik ini.
Pun demikian dengan masyarakat dikubu oposisi, tidak pernah berhenti menggiring opini masyarakat untuk terus memandang negatif setiap kinerja pemerintahan. Disaat ada yang melawan, persekusi jadi andalan. Disaat dipaparkan data untuk menyanggah, bulying menjadi solusi. Sampai kapan kita akan terus bermusuhan seperti ini?
Jika tetap demikian, sama halnya kita sedang membangun kembali “tembok Berlin” di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sedang membangun jurang pemisah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita terlalu sibuk meributkan sesuatu yang seharusnya tidak menjadi masalah utama, dan melupakan masalah pokok bangsa ini yang seharusnya kita pecahkan bersama, yakni Intoleransi dan masuknya paham radikalisme yang siap merong-rong Pancasila dan keutuhan NKRI. Apa kabar Revolusi Mental yang dulu digembar-gemborkan oleh Jokowi-JK? Masihkah upaya itu akan terus berlanjut di periode kedua ini?
Kita semua menantikan realisasi dari revolusi mental ala Jokowi-Ma’aruf. Karena tidak ada artinya kita mengebut pembangunan infrastruktur, sembari berharap bisa bersaing diera 4.0 ini, jika Mental masyarakat Indonesia masih inferior dan demagogisch. Kita rindu Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Indonesia yang mana rakyatnya bisa menjadi warga negara, dan tudak ada pada dua kubu politik yang berseberangan. Menjadi warga negara, artinya ikut mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan kritikan yang membangun kepada pemerintahan. Dan yang terpenting dari itu semua, mendukung jalannya pemerintahan yang sah, bukan malah menjadi batu sandungan untuk kemajuan Indonesia. Itulah harapan kita semua. Semoga tercapai! ***
Penulis adalah, pemerhati Sosial, Pendidikan dan Budaya.