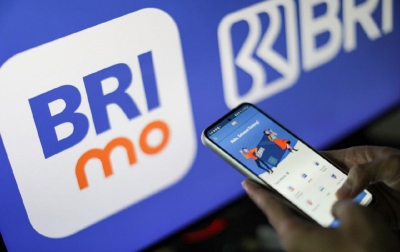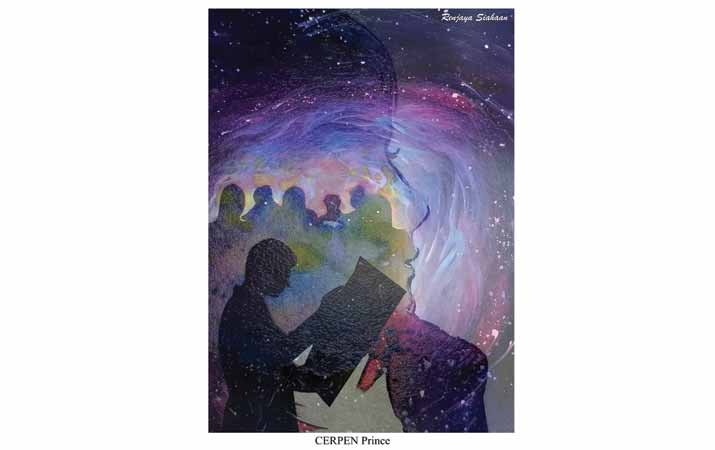
Oleh: T. Sansi Situmorang
Bebeb sudah menunggu di pintu kedatangan sewaktu aku tiba di sana. Kupeluk tubuhnya erat kemudian mencium pipinya. Dia malah menyosor bibirku. Bibir kami hanya bersentuhan sekilas. Aku tersenyum.
Seperti kesepakatan, kami langsung menuju Parapat. Semula niatku naik mobil travel yang berisi beberapa orang, tetapi Bebeb memutuskan menyewa mobil itu hanya membawa kami berdua.
Dalam perjalanan, Bebeb mengusulkan sebaiknya aku punya mobil. Dia bersedia menutupi kekurangannya. Bila aku gengsi menerima bantuannya, Bebeb bilang, “Uang itu sebagai pinjaman. Supaya kau tidak merasa memanfaatkanku.”
Aku menolak usulan Bebeb. Sepeda motor cukup untukku. Selain mampuku hanya itu, aku tidak butuh mobil. Sebenarnya, aku dan Bebeb bisa naik motor sampai ke Parapat. Lebih efisien karena bisa kami pergunakan selama berada di Parapat dan Samosir.
Bebeb menolak dengan berbagai alasan. Dia enggan naik motor untuk perjalanan jauh. Takut kecelakaan dan masuk angin. Aku mengerti kecemasannya.
Aku dan Bebeb menempel di kursi belakang. Kami, terutama Bebeb, sama sekali tidak menganggap sopir yang membawa kami. Kepala Bebeb bersandar di bahuku, sengaja wajahku kuhadapkan padanya. Hidungku menyentuh-nyentuh puncak kepalanya. Wangi rambut Bebeb mengantarku ke langit.
“Bagaimana kabar Jakarta?”
Bebeb bilang, Jakarta terasa sangat sepi tanpaku.
Kepala Bebeb kupindahkan ke pangkuanku. Sekarang, posisi Bebeb setengah berbaring. Aku tersenyum tipis ketika bertemu mata dengan sopir melalu spion dalam. Lelaki yang kuduga seusiaku itu tampak salah tingkah. Barangkali dalam hati dia bersumpah itu terakhir kali dia penasaran dengan kami.
Bebeb yang melarangku ke Jakarta. “Sebab aku mencintaimu. Tak mau kehilanganmu,” kata Bebeb dengan pasti.
Aku meliriki sopir. Kepalanya lurus ke depan. Kurasa sekarang telinga yang dia pasang benar-benar.
Aku setuju dengan Bebeb. Lebih aman memang seperti ini, Bebeb yang berkunjung ke Medan ketimbang aku ke Jakarta. Di Medan, hanya beberapa orang yang kenal Bebeb. Itu pun setelah kukenalkan. Tidak ada yang tahu masa lalu kami di sini. Di Jakarta, tidak terhitung yang mengenalku sekaligus mengenal Bebeb. Mereka tahu kami, latar belakang kami.
Sejak pindah ke Medan dua tahun lalu, tak sekalipun aku pulang ke Jakarta. Tidak terhitung jumlah Bebeb berkunjung ke mari. Bahkan pernah Bebeb tiba siang hari dan pulang sore harinya. Kami hanya sempat mampir di sebuah hotel tidak begitu jauh dari bandara.
Kedatangan Bebeb kali ini, termasuk luar biasa. Seminggu ini kami akan terus bersama-sama di sini. Ini akan menjadi waktu terpanjang kami setelah Jakarta kutinggalkan. Hartanto tahu Bebeb pergi ke Medan. Tidak seorang pun tahu sekarang aku menetap di Medan. Sebagai seorang pebisnis yang rutin melakukan perjalanan ke kota-kota di seluruh Indonesia, memang wajar Hartanto tidak curiga.
Dulu, Bebeb sudah berjanji di depan semua orang untuk melepaskan aku dari hati dan pikirannya. Janji itu yang dipegang Hartanto. Janji bukanlah takdir. Masih bisa dilanggar. Sayang sekali Hartanto tidak berpikir seperti itu.
Untung juga Hartanto tidak berpikir sampai ke situ. Bila iya, bisa jadi seumur hidupku tidak bisa bertemu Bebeb lagi. Aku yakin tidak bisa hidup tanpa Bebeb. Mungkin terdengar memualkan, tapi seperti itu adanya.
Aku sangat mencintai Bebeb. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, sewaktu pengambilan rapor di sekolah. Bebeb mengambil rapor Kimi. Untungnya aku lumayan dekat sama Kimi. Jadi tidak aneh bila kemudian aku sering ke rumah Kimi, tentu saja untuk melihat Bebeb.
Seperti sepotong magnet dengan lempengan besi, aku dan Bebeb nyaris tidak memiliki hambatan untuk merasa saling memiliki.
* * *
Usiaku baru empat belas tahun ketika ibuku meninggal. Usiaku belum lima belas tahun ketika ayah membawa istri baru ke rumah. Istri ayahku itulah yang merenggut keperjakaanku, di atas ranjang kamarku. Semula, hari-hari berjalan sangat menakutkan, terutama di saat ayah tidak berada di rumah. Perempuan itu bisa memaksaku di mana saja.
Sampai tiba sebuah titik, ketakutan itu hilang dari hatiku, namun bukan berarti kunikmati. Perbuatan laknat itu semacam kewajiban yang tidak berarti apa pun bagiku. Saat umurku tujuh belas tahun, ibu tiriku tewas kecelakaan di jalan raya. Aku pun merayakan kebebasanku.
Barangkali ibu tiriku melaknatku dari surga entah neraka. Seharusnya aku berduka atas kematiannya yang tragis. Aku tidak bisa menyukai perempuan-perempuan di sekelilingku. Kecuali Bebeb, dia cinta pertamaku.
* * *
Kami singgah di Pematang Siantar untuk makan. Pukul lima belas lewat tiga puluh. Tidak tepat dikata makan siang, tapi faktanya aku dan Bebeb belum makan siang. Setelah sopir tahu tujuan kami sebenarnya ke Tuk-tuk, dia menjelaskan kapal terakhir ke sana sekitar jam tujuh. Tentu masih ada waktu. Dari Pematang Siantar ke Parapat tidak sampai tiga jam.
Aku dan Bebeb masih duduk di belakang. Sopir tidak pernah lagi melirik-lirik melalui spion dalam. Mungkin dia tidak merasa aneh lagi melihat kemesraanku bersama Bebeb. Dulu aku malu mempertontonkan kemesraan di depan orang lain.
Sepuluh tahun bersama Bebeb agaknya berhasil memutuskan urat maluku perihal itu. Lagi pula kurasa, itulah satu bukti bila cintaku pada Bebeb benar-benar tulus. Tidak aku peduli pandangan orang lain, yang penting aku bahagia bersama Bebeb.
Sampai dua tahun lalu, kebahagian itu robek manakala Hartanto mengetahui hubungan kami. Tidak setitik debu rasa takut muncul di hatiku. Diam-diam aku bahagia terbongkarnya rahasia itu. Aku berharap Bebeb mengajakku lari, kemudian kami menikah.
Aku sakit hati manakala Bebeb tidak memilihku. Dia berjanji akan melupakanku bila diberi kesempatan. Hartanto memberi kesempatan itu. Aku pun meninggalkan Jakarta atas permintaan Bebeb dan belakangan Kimi.
Bebeb tidak berhak memintaku pergi jauh, tapi kurasa Kimi pantas mendapatkan yang dia inginkan. Selama ini Kimi sangat baik padaku. Dia tidak menghakimiku ketika hubunganku dengan Bebeb terbongkar. Padahal seharusnya, membunuhku pun Kimi pantas.
Entah kenapa malah Medan yang kupilih. Aku tidak memiliki saudara maupun kenalan di sini. Untungnya kota ini berbaik hati padaku, aku diterima bekerja di sebuah perusahaan bonafide dengan posisi tidak buruk. Di sini aku berusaha melupakan Bebeb dan segala kenangan kami. Semakin berjuang melupakan, semakin kuat Bebeb menggempur hati dan pikiranku.
Satu kesempatan, pertahananku bobol. Kuhubungi nomor Bebeb yang masih kuhapal. Ternyata, aku dan Bebeb sama-sama tersakiti dengan perpisahan kami. Esoknya, aku menjemput Bebeb di bandara. Kami menghabiskan dua hari yang sangat indah.
Begitulah. Aku dan Bebeb menjalin cinta lagi. Tanpa seorang pun yang tahu. Maksudku, tak seorang pun yang kami kenal tahu kami menjalin cinta lagi.
Sore yang hitam memayungi langit saat mobil melintasi Penatapan menuju Parapat. Biasanya, Danau Toba sangat indah ditatap dari sini. Sekarang, airnya yang biru tertutup asap putih kiriman dari provinsi tetangga.
Kutepuk pelan pipi Bebeb yang tertidur di pangkuanku.
“Hampir sampai.” Aku bergumam setelah matanya terbuka.
* * *
Empat malam kami habiskan di Tuk-tuk, Pulau Samosir. Kami tak ubah bagai bocah yang sedang mendapatkan mainan baru. Aku sendiri heran dengan gairahku, terutama gairah Bebeb. Sekejap pun Bebeb seolah enggan menjauh dariku. Barangkali, jika kupinta, Bebeb bersedia berdiri di sebelahku sembari memegang tangan kananku ketika aku buang hajat.
Keherananku terjawab sekarang, malam terakhir dari dua malam yang kami habiskan di Medan. Kami makan di kafe hotel tempat kami menginap. Bebeb bilang, sudah waktuku mencari perempuan lain. Perempuan yang pantas mendampingiku menghabiskan sisa hidup.
“Hanya Bebeb yang pantas mendampingiku menghabiskan sisa hidup. Tidak perempuan lain.”
Bebeb melanjutkan, “Dia bukan perempuan yang tepat untukku. Bila diibaratkan sebuah jalan, Bebeb hanya sebuah gang buntu. Sia-sia belaka menyusuri gang buntu sebab tidak menemukan apa pun pada ujungnya.”
“Bebeb matahariku. Bukan gang buntu.”
Bebeb tertawa kencang, tapi terdengar kering. Kemudian dia berkata, ini malam terakhir kami bersama. Ketika besok pagi menyapa, kami bukan lagi sepasang kekasih. Bebeb hanya masa laluku, demikian juga aku bagi Bebeb.
“Jangan berkata seperti itu. Hatiku sakit.” Aku tidak malu menangis di hadapan Bebeb, bahkan bila orang-orang di sekitar kami mengabadikan air mataku melalui ponsel mereka kemudian menyebarkannya ke dunia maya.
Aku sudah pernah kehilangan Bebeb, aku tidak mau mengalaminya sekali lagi. Aku tidak kuat. Semula Bebeb menghapus air mataku dengan kedua tangannya. Air mataku masih mengucur deras. Bebeb tampak kewalahan, Bebeb menghapus air mataku dengan lidahnya. Kemudian, aku dan Bebeb bertangis-tangisan.
“Bebeb, jangan pernah tinggalkan aku, ya.”
“Tidak, kita harus putus. Sebab aku akan pergi,” tegas Bebeb.
Diam-diam kulepas doa menuju langit. Semoga Tuhan membekukan waktu. Aku dan Bebeb saling berpelukan seperti ini sampai hari kiamat tiba.
Doaku tidak terkabul. Besoknya, saat terbangun, tidak ada Bebeb di sampingku. Nomor ponselnya tidak aktif, akun sosial medianya semua tidak dapat kulacak.
Aku merasa gila. Aku harus berbicara dengan Bebeb di Jakarta. Peduli setan Hartanto suaminya, Kimi anaknya, atau siapa pun itu.
* * *
Televisi masih menyala. Nama-nama penumpang pesawat beserta kru ditampilkan. Urutan 47 tertulis Miranda Sukesih (55 tahun). Itu nama Bebeb.
Diduga, tragedi ini diakibatkan kabut asap yang mengepung langit Kalimantan. Tidak ada korban selamat. Begitu kata pembaca berita.
Aku tidak tahu harus berbuat apa, selain memaki ketololanku. Seharusnya aku paham, pergi seperti inilah yang dimaksud Bebeb. Aku mengaku sangat mencintainya, tapi tak mampu menangkap tanda-tanda yang dia berikan waktu itu.
Bebeb, jangan pergi! Aku merasa berteriak sangat kencang, hingga leherku nyaris patah, anehnya telinga ku tidak menangkap suara apa pun.
Binjai, 31 Oktober 2015