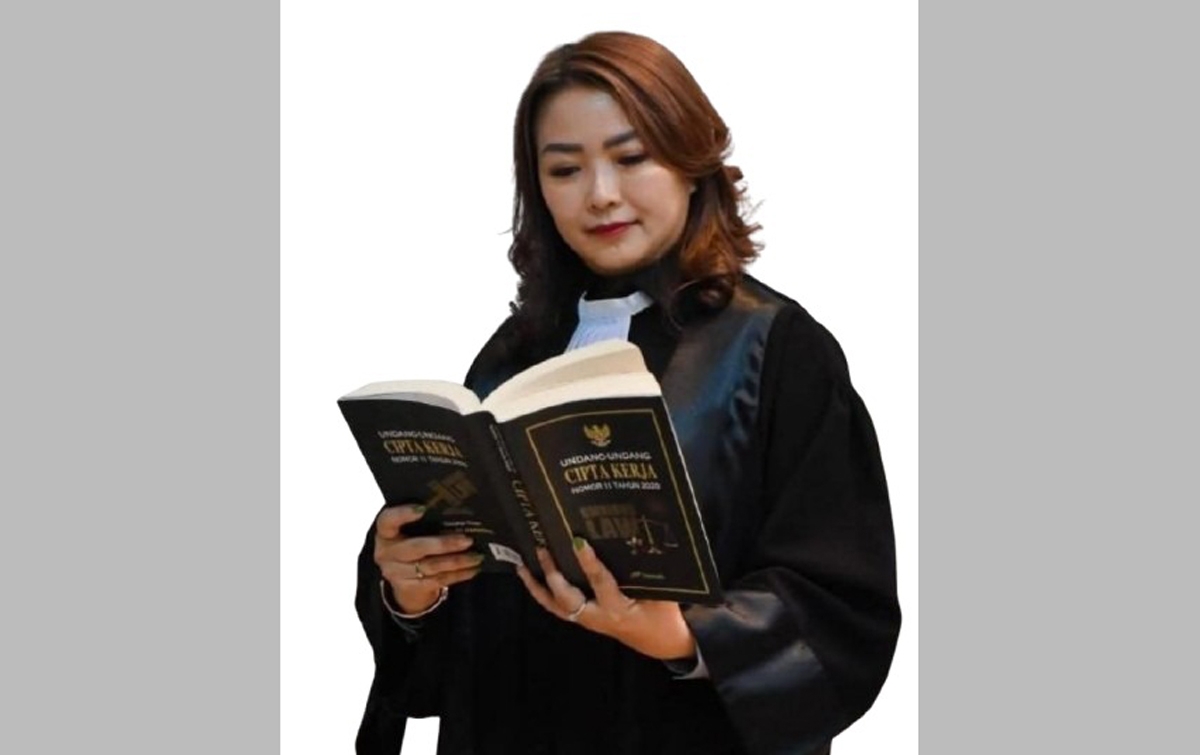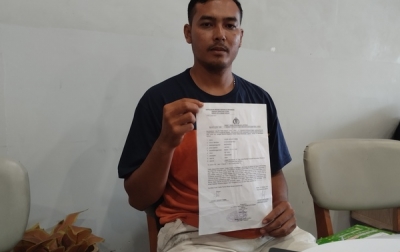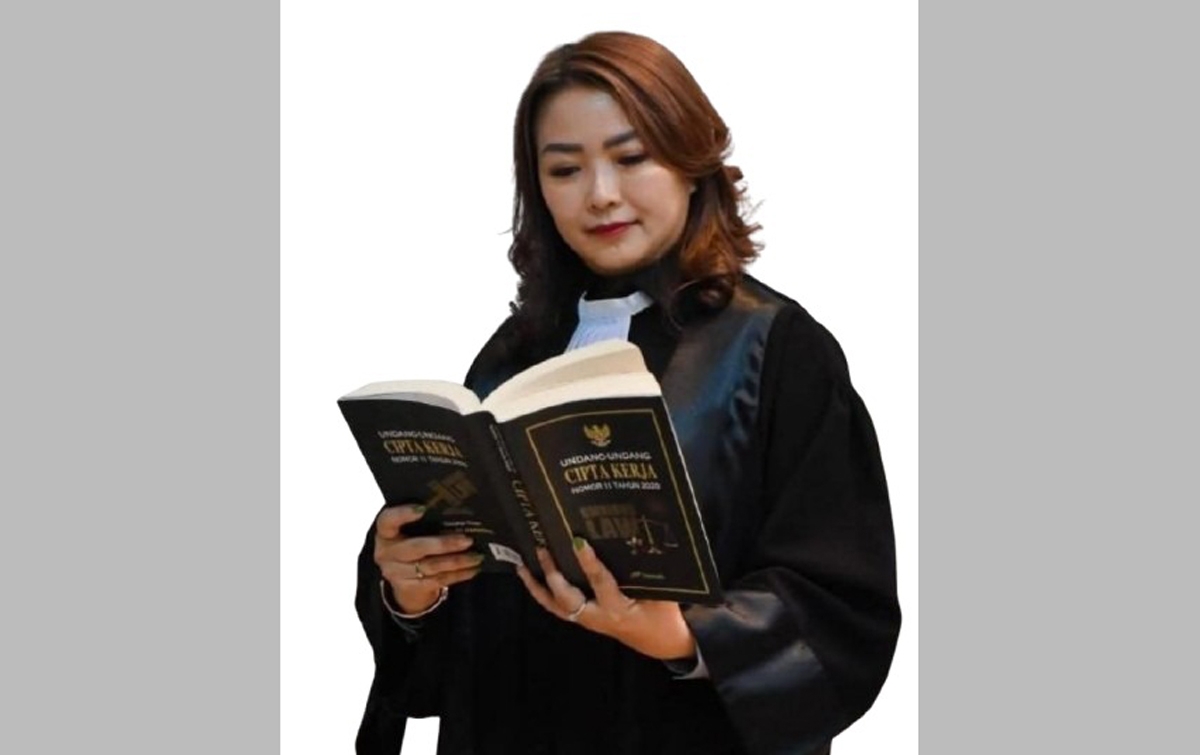
Oleh: Dr. Agustina, S.E., S.H., M.H., M.Psi.,M.Pd, dosen Universitas Satya Terra Bhinneka, pemerhati Psikologi dan Advokat (Analisadaily/Istimewa)
“Hukum dapat menjadi instrumen keadilan jika ia mengakui (nilai) kemanusiaan penuh dari korban, dan itu mencakup pemahaman terhadap kerugian psikologis” (Martha Minow, Ahli Hukum dari Amerika Serikat).
Pendapat ini menyoroti tentang pentingnya memperhatikan aspek psikologis korban tindak pidana terutama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari kalangan perempuan.
Sampai hari ini KDRT menjadi masalah serius yang menghantui banyak perempuan Indonesia. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) periode Januari-November 2023 terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 12% dibandingkan periode tahun 2022 yaitu 457.895 kasus. Dari data tersebut bentuk kekerasan yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual sebesar 34,8%, sisanya adalah kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi (
paudpedia.kemdikbud.go.id).
Di era modrenisasi seperti sekarang sudah tidak ada lagi pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap manusia diperlakukan secara sama (
equality) tanpa memandang jenis kelamin, suku dan golongan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, mualai dari politik, sosial-ekonomi, hingga dalam rumah tangga. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW 1979), menyatakan hak-hak perempuan mencakup hak dalam ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, serta hak dalam perkawinan dan keluarga.
Rendahnya tingkat pendidikan, adanya stigma, hingga menjalankan peran ganda, menjadi faktor penghambat bagi perempuan Indonesia untuk mandiri secara ekonomi dan mengambil keputusan dalam hidup. Meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, namun masih banyak perempuan mengalami kekerasan. Karena itu, perempuan harus memperoleh proteksi menyeluruh dari negara maupun masyarakat agar terhindar dari diskriminasi, kekerasan, pelanggaran hak dan berbagai bentuk prilaku yang merendahkan harkat-martabatnya.
Menanggapi fenomena ini, Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mendesak optimalisasi upaya pencegahan kekerasan perempuan, guna mewujudkan perlindungan secara menyeluruh bagi setiap warga negara. “Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia saat ini. Nilai-nilai perjuangan RA Kartini untuk membela hak-hak perempuan dan anti segala bentuk diskriminasi harus terus dihidupkan,” katanya (
metrotvnews.com)
Klasifikasi
Indonesia telah memiliki instrumen hukum perlindungan perempuan, terutama dalam kehidupan rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT merupakan aspek penting dalam upaya menghapuskan kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT, menegaskan perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum perempuan dalam Undang-Undang ini difokuskan pada proteksi kepada korban kekerasan domestik.
Kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Klasifikasi KDRT dalam undang-undang ini (Pasal 6-9) dibedakan menjadi, yaitu:
- Kekerasan fisik : perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- Kekerasan psikis: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang atau salah seorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran: tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan atau perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Sanksi pidana bagi pelaku KDRT diatur pada BAB IV UU PKDRT tentang Ketentuan Pidana (Pasal 44-Pasal 49) yaitu:
a. Kekerasan Fisik
- Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta jika kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka berat.
- Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat.
- Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan kematian korban.
- Jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri (atau sebaliknya) dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp5 juta
b. Kekerasan Psikis
- Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9 juta bagi pelaku kekerasan psikis.
- Jika kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri (atau sebaliknya) tanpa menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp3 juta
c. Kekerasan Seksual
- Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun untuk pelaku yang memaksakan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga.
- Jika kekerasan seksual mengakibatkan luka yang tidak bisa sembuh, gangguan daya pikir atau kejiwaan, gugur janin, atau tidak berfungsinya organ reproduksi, pelaku dapat dipidana penjara dari 5 hingga 20 tahun.
d. Penelantaran
- Pelaku penelantaran rumah tangga dapat dikenai pidana penjara maksimal selama 3 tahun atau denda maksimal sebesar Rp15 juta, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan ketergantungan ekonomi bagi anggota keluarga.
Luka yang Membekas
Perempuan seringkali digambarkan sebagai makhluk perasa karena sifat alami yang lebih sensitif dan emosional, sehingga perempuan cenderung mudah tersentuh hati, lebih peka dan ekspresif dalam menampilkan emosi (melalui air mata, senyuman, maupun tindakan langsung). Bagi perempuan korban KDRT oleh suaminya, akan sangat sulit baginya untuk menyembuhkan luka bathin (psikis) dibandingkan luka nyata akibat tindak kekerasan itu.
Ketika seseorang mengalami kekerasan fisik, luka dan lebam dapat dibuktikan melalui visum, namun bagaimana jika luka itu tak terlihat dan hanya terasa dalam batin? Bagaimana jika penderitaan itu berbentuk kata-kata yang meruntuhkan harga diri, emosional, membuat korban menjadi frustasi atau teror psikologis? Sayangnya, penerapan instrumen hukum kita belum cukup siap mendengar jeritan sunyi perempuan korban kekerasan. Kekerasan psikis dalam rumah tangga dianggap abstrak, sulit dibuktikan, dan kerap disepelekan. Padahal dampak merusaknya jauh lebih luas dibandingkan luka fisik, karena kekerasan psikis dapat menghancurkan kepribadian korban, memutus interaksi sosial, hingga menciptakan trauma mendalam.
Seperti contoh kasus korban KDRT yaitu perempuan berinisial TE (24) di Jakarta yang mengalami trauma psikis mendalam akibat kekerasan oleh suaminya sendiri di tahun 2024 lalu. Korban menjadi trauma, mengisolasi diri dalam kamar karena takut keluar rumah untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dikarenkan sang suami bukan hanya menganiaya fisik korban, melainkan juga mencaci maki dan melakukan tekanan psikis, hingga mengurung korban kamar mandi. Secara fisik, luka-luka akibat kekerasan itu telah pulih, namun secara psikis, trauma mendalam dan berkepanjangan itu masih menimbulkan bekas luka hingga sekarang.
Law enforcement saat ini masih sebatas menindak pelaku tanpa melakukan rehabilitasi mental secara total terhadap korban KDRT. Padahal Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang PDKRT dan turunan regulasi di bawahnya, menyediakan sarana perlindungan maupun pemulihan korban (rehabilitasi). Namun langkah ini jarang dilakukan secara tuntas dan hanya sebatas proses hukum saja. Setelah berkas dilimpahkan ke penuntutan dan pelaku di vonis oleh pengadilan, korban yang masih mengalami trauma harus berjuang sendiri untuk memulihkan diri. Sungguh ironi.
Hukum Holistik
“Hukum tanpa nurani hanyalah memperpanjang penderitaan bagi korban” (Satjipto Rahardjo).
Bahwa agar hukum dapat mencapai tujuan (keadilan, kepastian dan kemanfaatan), ia harus bekerja secara humanis. Artinya, hukum bukan sekadar sebagai instrumen yang kaku, melainkan juga merasa empati, bekerja dengan moral dan pendekatan hukum holistik. Pendekatan hukum holistik bukan hanya soal teks, tapi juga konteks. Hukum harus memahami relasi kuasa, dinamika emosi, dan struktur sosial, menempatkan manusia sebagai pusat bukan sekedar objek pasal. Dalam pendekatan Hukum Holistik, keadilan bukan lagi sekedar tindakan, tapi juga tentang dampak menyeluruh terhadap korban. Hukum Holistik mendorong pendekatan yang lebih manusiawi dan menyeluruh dalam membaca suatu kasus, termasuk mempertimbangkan kondisi psikologis korban sebagai bukti yang tak terbantahkan.
Sayangnya hukum kita saat ini masih terlalu menekankan pada bukti fisik konkret. Padahal pada kekerasan psikis, pelaku pandai menyembunyikan fakta, menjaga citra seolah tidak terjadi apa-apa. Karena itu, sudah waktunya untuk menodorng pembenahan hukum baik dari aspek materil maupun formil-nya, meningkatkan profesionalisme aparatur penegak hukum, membangun upaya protektif menyeluruh kepada saksi-korban KDRT tanpa diskriminatif, hingga meningkatkan pemahaman melalui edukasi masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum.
Pemerintah sebagai otoritas tertinggi harus hadir dan menunjukkan keberpihakanya kepada korban KDRT melalui tindakan nyata dalam berbagai kebijakan seperti menjamin terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat, memberikan akses pengaduan/laporan bagi korban dan menanganinya dengan baik, menyediakan layanan psikolog yang terjangkau, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan hingga sosialisasi untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti di masyarakat.
KDRT bukan hanya kekerasan fisik yang dapat terlihat jelas, kekerasan psikis yang tak kasat mata justru paling membekas dan memberi trauma berkepanjangan bagi korbannya. Ketika hukum masih gagap dan masyarakatnya apatis, maka korban KDRT akan semakin terpuruk, tersiksa, dan perlahan kehilangan dirinya. Hukum jangan hanya membela yang berdarah, tapi juga yang mengalami luka bathin. Hukum sejati tidak hanya melindungi tubuh, tetapi juga jiwa yang terluka.
Perempuan adalah sumber kehidupan, sumber peradaban dan kemajuan bangsa. Setiap perempuan harus berdikari dan tangguh menghadapi berbagai persoalan karena sebuah bangsa yang besar dapat tercermin dari sosok perempuan di dalamnya. Jika moral, keilmuan, dan perilaku perempuan itu baik, maka akan melahirkan generasi penerus yang baik pula. Namun jika perempuan di suatu negeri justru diangap remeh dan dipandang sebagai makhluk lemah, maka celakalah peradaban itu. Karena itu setiap perempuan harus mendapat perlakuan adil, memperoleh akses dan kesempatan yang sama dalam beragai hal, serta yang terpenting mendapatkan perlindungan atas tindakan maupun ancaman kekerasan. Bersama, mari kita jaga dan lindungi perempuan Indonesia demi keberlangsungan bangsa. Stop kekerasan terhadap perempuan !
*** Penulis adalah Dosen Universitas Satya Terra Bhinneka, Pemerhati Psikologi dan Advokat
(Adv)