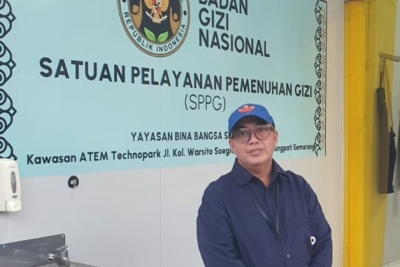Tuberkulosis (TBC), HIV, dan malaria masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, Indonesia menempati peringkat kedua dunia untuk jumlah kasus TBC, dengan estimasi lebih dari 1 juta orang sakit dan 125 ribu kematian pada 2023. HIV menempatkan Indonesia pada posisi ke-14 dunia dengan sekitar 570 ribu orang hidup dengan HIV (ODHIV) dan 28 ribu infeksi baru per tahun. Sementara malaria, meskipun tren nasional menurun, tetap menjadikan Indonesia peringkat kedua di Asia Tenggara setelah India dengan lebih dari 1 juta kasus per tahun.
Sorotan tajam jatuh pada Sumatera Utara (Sumut). Hingga pertengahan 2025, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) TBC baru mencapai 38%, jauh di bawah target nasional. Artinya, masih banyak masyarakat dengan gejala TBC yang belum mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan sesuai standar, padahal Sumut memiliki mobilitas penduduk yang tinggi sehingga risiko penularan lebih besar. Untuk HIV, estimasi kasus mencapai lebih dari 122 ribu ODHIV, namun hanya 39% yang konsisten mengakses terapi ARV. Kondisi ini memperlihatkan celah besar antara kebutuhan layanan dan cakupan yang tersedia. Malaria pun belum sepenuhnya hilang. Kasus indigenous masih ditemukan di kantong-kantong endemis seperti Batu Bara, Asahan, dan Nias Utara. Meski mayoritas kabupaten/kota di Sumut sudah menuju eliminasi, masih ada 10 daerah yang belum memenuhi syarat eliminasi karena penularan setempat tetap terjadi. Fakta ini menjadi pengingat bahwa malaria bukan sekadar “penyakit masa lalu,” melainkan ancaman yang masih menghantui sebagian masyarakat di pesisir dan pedalaman.
Potret gabungan TBC, HIV, dan Malaria di Sumut menggambarkan situasi darurat yang membutuhkan respons luar biasa. Tiga penyakit ini tidak hanya soal angka, tetapi menyangkut kualitas hidup jutaan orang. Jika penanganan TBC lambat, rantai penularan akan terus berlanjut. Jika ODHIV tidak segera dijangkau layanan komprehensif, generasi muda berisiko kehilangan masa depan. Jika malaria dibiarkan, kantong endemis bisa meluas dan menggerogoti produktivitas masyarakat.
Selain tingginya beban penyakit, upaya eliminasi di Sumut terhambat oleh berbagai faktor struktural. Pertama, stigma dan diskriminasi yang masih kuat, terutama pada TBC dan HIV, membuat banyak pasien enggan mencari layanan. Kedua, deteksi dini belum optimal, terbukti dari rendahnya notifikasi kasus di lapangan. Ketiga, akses layanan kesehatan tidak merata, terutama di daerah pedesaan, kepulauan, dan wilayah terpencil, sehingga sebagian masyarakat kesulitan memperoleh pengobatan tepat waktu. Keempat, kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas; banyak Puskesmas kekurangan tenaga farmasi maupun analis laboratorium, sementara turnover tenaga terlatih cukup tinggi sehingga kesinambungan program sering terganggu.Dengan kombinasi beban penyakit yang besar, capaian layanan yang rendah, serta tantangan struktural di lapangan, percepatan layanan kesehatan di Sumut bukan sekadar kebutuhan daerah, tetapi syarat mutlak bagi tercapainya target nasional eliminasi TBC, HIV, dan malaria pada 2030. Apa yang terjadi di Sumut akan menjadi penentu: apakah Indonesia mampu keluar dari jerat epidemi penyakit menular, atau justru tertinggal dalam memenuhi agenda kesehatan global.
Strategis Sumut
Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta kesehatan nasional. Dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa, provinsi ini merupakan salah satu daerah dengan populasi terbesar di Indonesia. Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi sekaligus kota terbesar ketiga di Indonesia, berfungsi sebagai hub kesehatan nasional. Banyak rumah sakit rujukan bertaraf nasional maupun regional berlokasi di Medan, seperti RSUP H. Adam Malik yang menjadi pusat rujukan utama di wilayah barat Indonesia. Kondisi ini menjadikan Sumut tidak hanya melayani kebutuhan kesehatan warganya sendiri, tetapi juga menjadi tujuan rujukan pasien dari provinsi sekitar seperti Aceh, Riau, dan Sumatera Barat.
Besarnya populasi Sumut otomatis berdampak pada tingginya beban kasus penyakit menular. Tingginya mobilitas penduduk antar kabupaten/kota, bahkan antarprovinsi dan lintas negara, semakin memperkuat posisi Sumut sebagai barometer capaian eliminasi penyakit menular di Indonesia. Bandara internasional Kualanamu dan pelabuhan Belawan menjadikan arus manusia dan barang keluar-masuk relatif tinggi, sehingga risiko penyebaran penyakit juga meningkat. Sumut bahkan berbatasan langsung dengan Malaysia melalui jalur laut, menjadikannya wilayah yang rawan bagi penyebaran lintas batas.
Selain faktor geografis, kondisi sosial-ekonomi Sumut juga turut menentukan dinamika penyakit menular. Sebagai salah satu pusat perdagangan dan industri di Sumatera, Medan dan sekitarnya menjadi magnet bagi pekerja migran dari berbagai daerah. Namun, di sisi lain, ketimpangan ekonomi dan keberadaan kantong-kantong pemukiman padat dengan sanitasi rendah menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penularan penyakit menular seperti TBC. Pada sisi HIV, keberadaan kelompok berisiko tinggi di kawasan perkotaan dan pelabuhan juga membuat Sumut masuk 10 besar provinsi dengan jumlah ODHIV terbanyak. Sedangkan untuk malaria, wilayah pedesaan dan kepulauan masih menghadapi risiko indigenous malaria, khususnya di kantong endemis seperti Nias Utara, Batu Bara, dan Asahan.
Dalam konteks eliminasi TBC, HIV, dan malaria menuju 2030, Sumut bisa dikatakan sebagai cermin keberhasilan atau kegagalan nasional. Dengan cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) TBC yang masih rendah (sekitar 38% pada 2025), Sumut memberi gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi Indonesia secara keseluruhan. Begitu pula dengan HIV, di mana lebih dari 122 ribu ODHIV hidup di Sumut, namun baru 39% yang terlayani dengan pengobatan ARV secara berkesinambungan. Angka ini jelas akan mempengaruhi pencapaian target nasional jika tidak segera dikejar.
Namun, posisi strategis ini bukan hanya tentang tantangan, melainkan juga tentang peluang. Jika Sumut berhasil mempercepat layanan kesehatan melalui deteksi dini, penguatan jejaring rujukan, dan penghapusan stigma, dampaknya akan sangat signifikan terhadap pencapaian nasional. Keberhasilan Sumut akan menjadi bukti bahwa percepatan layanan kesehatan di daerah dengan beban tinggi dan kompleksitas sosial-ekonomi dapat dicapai. Lebih jauh lagi, Sumut dapat menjadi role model bagi provinsi lain, khususnya di luar Jawa, dalam membangun sistem kesehatan yang responsif terhadap penyakit menular.
Pada akhirnya, posisi strategis Sumut dapat dirangkum dalam sebuah logika sederhana: jika Sumut bergerak cepat, Indonesia akan lebih cepat pula mendekati target eliminasi 2030. Sebaliknya, jika Sumut tertinggal, maka keberhasilan nasional pun akan terhambat. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, harus menempatkan Sumut sebagai prioritas dalam strategi eliminasi TBC, HIV, dan malaria. Keberhasilan di Sumut bukan sekadar kemenangan lokal, tetapi kemenangan bangsa.
Percepatan Layanan: Apa yang Dimaksud?
Percepatan layanan dalam konteks eliminasi TBC, HIV, dan malaria bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan sebuah strategi komprehensif untuk memastikan bahwa setiap individu yang berisiko atau sudah terinfeksi dapat segera terdeteksi, diobati, dan didukung dalam proses pemulihannya. Di Sumatera Utara, percepatan ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat capaian layanan yang masih jauh dari target nasional. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apa sebenarnya yang dimaksud dengan percepatan layanan itu?
Pertama, percepatan layanan berarti deteksi dini yang lebih luas dan menyeluruh. Tanpa deteksi, penyakit menular akan terus berada dalam “bayang-bayang” dan menyebar tanpa terkendali. Untuk TBC, skrining aktif harus diperluas pada populasi berisiko tinggi seperti keluarga kontak serumah pasien TBC, pekerja di lingkungan padat, maupun masyarakat di wilayah dengan angka insidensi tinggi. Optimalisasi sistem informasi seperti SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) harus benar-benar dijalankan untuk memastikan setiap kasus yang ditemukan tidak hilang dalam rantai pelayanan. Hal serupa berlaku pada HIV, di mana perluasan tes HIV menjadi kunci. Tes berbasis fasilitas kesehatan harus diperkuat dengan pendekatan berbasis komunitas, termasuk melalui mobile clinic atau layanan lapangan di daerah terpencil. Sistem informasi SIHA (Sistem Informasi HIV-AIDS) perlu dioptimalkan agar data kasus dapat dipantau secara real time, sehingga memudahkan intervensi lebih cepat.
Kedua, percepatan layanan juga berarti pengobatan tepat waktu. Tidak cukup hanya menemukan kasus, pasien harus segera masuk dalam perawatan. Pada TBC, targetnya adalah memastikan treatment enrollment baik untuk TBC sensitif obat (SO) maupun resistan obat (RO) dapat tercapai dengan cepat, sehingga mencegah putus obat dan resistensi lebih luas. Untuk HIV, percepatan layanan berarti memastikan ODHIV segera mendapatkan terapi ARV begitu terdiagnosis, tanpa menunggu kondisi tubuh melemah. Demikian pula pada malaria, penggunaan regimen standar yang konsisten harus diterapkan agar kasus tidak berkembang menjadi berat atau berulang. Prinsip “test and treat” menjadi roh percepatan, yakni diagnosis segera diikuti pengobatan tanpa menunda.
Ketiga, percepatan layanan membutuhkan pendekatan komunitas. Sumut memiliki kekuatan sosial yang luar biasa mulai dari kader kesehatan desa, tokoh agama, hingga organisasi pemuda seperti karang taruna. Mereka adalah jembatan antara sistem kesehatan dengan masyarakat. Edukasi berbasis rumah yang dilakukan kader, khutbah masjid yang mengangkat isu stigma HIV, atau kegiatan karang taruna yang menyosialisasikan pencegahan malaria dapat menjadi faktor kunci dalam mempercepat perubahan perilaku. Pendekatan komunitas inilah yang mampu menembus hambatan stigma, diskriminasi, dan ketidakpercayaan masyarakat pada layanan formal.
Keempat, percepatan layanan juga harus bertumpu pada inovasi digital. Pandemi COVID-19 sudah membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi katalis transformasi kesehatan. Untuk TBC, tersedia platform e-learning yang dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan secara cepat dan merata. Sistem pelacakan berbasis aplikasi juga dapat memperkuat investigasi kontak serta memastikan pasien tidak terputus dalam rantai layanan. Pada HIV, inovasi seperti layanan self-test membuka ruang privasi yang lebih luas bagi mereka yang takut stigma, sekaligus mempercepat deteksi. Integrasi data digital antara pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota akan membuat respon lebih gesit, akurat, dan efisien.
Dengan keempat pilar ini yaitu deteksi dini, pengobatan tepat waktu, pendekatan komunitas, dan inovasi digital maka percepatan layanan bukan lagi sekadar retorika, tetapi sebuah gerakan nyata yang bisa mempercepat langkah Sumatera Utara menuju eliminasi TBC, HIV, dan Malaria pada 2030. Intinya, percepatan layanan berarti memperpendek jarak antara “orang yang sakit” dengan “layanan yang menyembuhkan.” Semakin cepat jarak ini dipangkas, semakin besar peluang Indonesia, melalui Sumut, memenangkan perang melawan tiga penyakit menular mematikan ini.
Strategi Akselerasi di Sumut
Untuk mewujudkan target eliminasi TBC, HIV, dan Malaria pada tahun 2030, Sumatera Utara membutuhkan langkah akseleratif yang terencana dan berkesinambungan. Strategi percepatan tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan nasional, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk aksi nyata di tingkat lokal. Sumut, dengan kompleksitas sosial-ekonomi dan tingginya beban penyakit, memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan inovatif.
Langkah pertama adalah penguatan Puskesmas dan jejaring rumah sakit. Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer memiliki peran penting dalam penemuan kasus. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas, termasuk pelatihan untuk deteksi dini TBC, HIV, dan Malaria, harus menjadi prioritas. Selain itu, jejaring dengan rumah sakit rujukan perlu diperkuat agar pasien yang sudah terdiagnosis segera mendapatkan pengobatan tanpa hambatan birokrasi. Sistem rujukan berlapis, mulai dari Puskesmas hingga RSUP Adam Malik di Medan, harus berjalan cepat, transparan, dan responsif. Dengan begitu, tidak ada lagi pasien yang terjebak dalam antrean panjang atau kehilangan kesempatan mendapatkan terapi yang menyelamatkan nyawa.
Kedua, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci akselerasi. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Organisasi masyarakat sipil memiliki jaringan yang kuat hingga ke komunitas akar rumput, yang dapat menjangkau kelompok berisiko tinggi HIV atau populasi yang sulit diakses oleh layanan formal. Universitas, termasuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat di Sumut, dapat memberikan kontribusi melalui riset, inovasi teknologi kesehatan, serta program pengabdian masyarakat. Sementara sektor swasta dapat dilibatkan dalam penyediaan sumber daya, CSR kesehatan, hingga dukungan sistem informasi digital. Kolaborasi multipihak inilah yang akan mempercepat penemuan kasus, memperluas cakupan layanan, dan memperkuat ketahanan program kesehatan.
Ketiga, mobilisasi tokoh masyarakat untuk melawan stigma. Stigma masih menjadi hambatan besar dalam program TBC dan HIV di Sumut. Banyak pasien yang enggan memeriksakan diri karena takut dikucilkan. Tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas lokal memiliki pengaruh yang kuat untuk mengubah persepsi masyarakat. Melalui khutbah, kegiatan keagamaan, atau pertemuan adat, pesan-pesan positif tentang pentingnya pemeriksaan dini, kepatuhan minum obat, dan dukungan terhadap pasien dapat disampaikan. Dengan cara ini, stigma dapat dikikis, dan masyarakat lebih terbuka menerima bahwa penyakit bukan aib, melainkan kondisi medis yang bisa diobati.
Keempat, implementasi program Quick Win lokal perlu segera dijalankan untuk menghasilkan dampak nyata dalam waktu singkat. Misalnya, pembentukan “Desa Siaga TBC”, di mana seluruh perangkat desa, kader kesehatan, dan masyarakat dilibatkan dalam menemukan kasus TBC, memastikan pengobatan berjalan, serta melakukan pemantauan secara rutin. Untuk HIV, pembentukan klinik ramah komunitas dapat menjadi jawaban. Klinik ini menyediakan layanan VCT (Voluntary Counseling and Testing) dan pengobatan ARV dengan suasana yang inklusif, menghormati kerahasiaan pasien, serta melibatkan komunitas terdampak sebagai pendamping. Di wilayah malaria, quick win bisa berupa distribusi kelambu berinsektisida massal dan surveilans aktif di kantong endemis.
Strategi akselerasi ini, jika dijalankan secara simultan, akan mempercepat Sumut menutup celah antara beban penyakit yang tinggi dengan capaian layanan yang masih rendah. Lebih dari itu, akselerasi bukan hanya soal memenuhi target angka, tetapi tentang menyelamatkan nyawa, mengembalikan harapan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sumut memiliki modal sosial, infrastruktur kesehatan, dan energi kolektif yang cukup untuk bergerak lebih cepat. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, keberanian berinovasi, dan komitmen kolaborasi.
Pada akhirnya, keberhasilan strategi akselerasi di Sumut akan menjadi tolok ukur nasional. Jika Sumut mampu menunjukkan percepatan signifikan, maka provinsi lain dengan tantangan serupa akan lebih mudah mengikuti. Sebaliknya, jika Sumut tertinggal, capaian nasional pun akan terganggu. Karena itu, akselerasi di Sumut bukan sekadar agenda daerah, tetapi bagian dari strategi besar Indonesia untuk mengakhiri TBC, HIV, dan malaria pada 2030.
Seruan dan Harapan
Percepatan layanan kesehatan di Sumatera Utara tidak boleh dipandang sebatas pencapaian target angka. Di balik persentase dan grafik capaian, ada nyawa manusia yang dipertaruhkan. Setiap kasus TBC yang terlambat ditemukan bisa berarti penularan kepada beberapa orang lain. Setiap orang dengan HIV yang tidak segera mengakses ARV berisiko mengalami komplikasi serius dan kehilangan harapan hidup. Setiap kasus malaria yang dibiarkan bisa berkembang menjadi wabah di kantong-kantong endemis. Karena itu, percepatan layanan sesungguhnya adalah upaya menyelamatkan nyawa sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini adalah investasi kemanusiaan yang nilainya jauh melampaui angka di tabel laporan.
Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menjadi teladan percepatan layanan kesehatan berbasis komunitas dan inovasi. Dengan populasi besar, infrastruktur kesehatan yang relatif lengkap, serta modal sosial yang kuat, Sumut dapat menjadi laboratorium nyata bagaimana strategi eliminasi penyakit menular dijalankan secara efektif. Kekuatan komunitas, baik melalui kader desa, tokoh agama, maupun organisasi pemuda, bisa menjadi ujung tombak dalam menghapus stigma, mendorong deteksi dini, dan memastikan kepatuhan berobat. Sementara itu, inovasi digital harus dioptimalkan untuk mempercepat alur layanan, mulai dari pencatatan kasus dalam sistem informasi hingga layanan self-test yang memberi ruang aman bagi masyarakat yang takut stigma.
Harapan ini tidak akan terwujud tanpa gotong royong. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, universitas, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, hingga media massa harus berdiri di barisan yang sama. Eliminasi TBC, HIV, dan malaria bukan pekerjaan satu institusi, tetapi kerja kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan gotong royong, tantangan besar bisa diurai menjadi langkah-langkah kecil yang nyata. Dengan gotong royong pula, mimpi eliminasi 2030 dapat berubah menjadi kenyataan. Kita harus ingat, Sumut bukan hanya satu provinsi di antara 38 provinsi lainnya. Sumut adalah barometer. Jika Sumut berhasil mempercepat layanan, maka Indonesia akan lebih cepat pula mendekati target eliminasi 2030. Sebaliknya, jika Sumut tertinggal, maka capaian nasional pun akan terganggu. Oleh karena itu, tanggung jawab mempercepat layanan di Sumut tidak hanya berada di pundak pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi kepedulian nasional.
Seruan ini harus sampai ke setiap sudut desa, ke setiap Puskesmas, hingga ke ruang-ruang keluarga: bahwa TBC, HIV, dan Malaria bisa dikalahkan jika kita bergerak bersama. Bahwa penyakit menular bukan aib, melainkan tantangan kesehatan yang bisa diatasi dengan ilmu, layanan, dan solidaritas. Bahwa target 2030 bukan sekadar slogan internasional, melainkan janji untuk melindungi generasi yang akan datang.
Penutup
Di tengah besarnya tantangan kesehatan, Sumatera Utara tidak boleh berhenti bergerak. Beban kasus TBC, HIV, dan Malaria yang masih tinggi menunjukkan bahwa kerja keras harus terus ditingkatkan. Namun, di balik angka-angka itu, tersimpan peluang besar untuk membuktikan bahwa Sumut bisa menjadi motor perubahan nasional. Dengan populasi yang besar, posisi strategis sebagai hub kesehatan, serta kekuatan komunitas yang tersebar hingga ke pelosok desa, Sumut memiliki semua modal untuk melakukan percepatan layanan. Pernyataan tegas harus kita gaungkan bersama: “Sumut bergerak, Indonesia lebih kuat melawan TBC, HIV, dan Malaria.” Kalimat ini bukan sekadar slogan, tetapi semangat perjuangan yang harus menjadi nafas setiap langkah. Gerakan percepatan layanan kesehatan di Sumut adalah refleksi tekad kolektif bangsa, bahwa tidak ada satupun warga yang boleh tertinggal dari akses kesehatan yang layak.
Namun, perjuangan ini tidak bisa ditanggung satu pihak saja. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyiapkan kebijakan, regulasi, dan anggaran. Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan yang harus dibekali dengan kapasitas dan dukungan agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Komunitas, mulai dari kader kesehatan, tokoh agama, hingga organisasi pemuda, adalah jembatan penting yang mampu menggerakkan masyarakat dan mematahkan stigma. Sementara itu, masyarakat luas tidak boleh pasif; kesadaran untuk melakukan pemeriksaan dini, mendukung anggota keluarga yang sakit, dan memutus rantai penularan adalah bentuk kontribusi nyata yang tak ternilai.
Kolaborasi lintas sektor pun mutlak diperlukan. Universitas dapat berkontribusi melalui riset dan inovasi, organisasi masyarakat sipil melalui advokasi dan pendampingan, sedangkan sektor swasta dapat terlibat lewat dukungan sumber daya dan program tanggung jawab sosial. Media massa, dengan kekuatannya membentuk opini publik, juga harus menjadi mitra strategis untuk menyebarkan informasi yang benar dan mengikis stigma yang masih membelenggu. Hanya dengan kebersamaan, target eliminasi TBC, HIV, dan malaria pada 2030 bisa tercapai. Gotong royong adalah kunci. Setiap langkah kecil, mulai dari edukasi rumah tangga hingga inovasi berbasis teknologi, jika dilakukan serentak, akan membentuk gelombang besar perubahan.
Penutup ini adalah seruan, sekaligus undangan: mari kita buktikan bahwa Sumut mampu menjadi teladan. Mari bergerak bersama, bukan hanya untuk memenuhi target angka, tetapi untuk menyelamatkan nyawa, mengembalikan harapan, dan memperkuat Indonesia dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Insya Allah