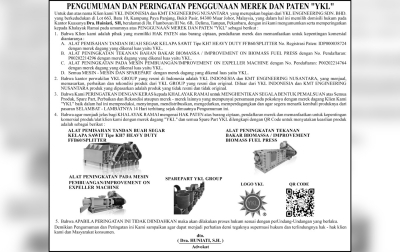Menggali Nilai Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Masa Depan Berkelanjutan (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Potensi non kayu dari hutan dinilai belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal nilainya juga tinggi dan bisa dilakukan tanpa harus mengeksploitasi alam bahkan justru turut dalam melestarikannya.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Berkelanjutan yang diselenggarakan Green Justice Indonesia (GJI) bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara pada Senin (15/9/2025) yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten.
Direktur GJI, Panut Hadisiswoyo mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang diskusi lintas pihak untuk menggali potensi hasil hutan bukan kayu yang dinilai belum dikelola secara optimal, sekaligus mendorong strategi perlindungan hutan berkelanjutan.
Menurutnya, hutan tidak hanya bernilai dari kayu, tetapi juga menyimpan potensi besar dari hasil hutan bukan kayu. Potensi itu mencakup sumber pangan, obat-obatan, hingga bahan kosmetik yang bisa dikelola tanpa merusak ekosistem.
Menurutnya, jika pemanfaatannya hanya pada eksploitasi kayu demi keuntungan sesaat, ada konsekuensinya besar yakni deforestasi, perubahan iklim, dan bencana. Padahal, hutan menyimpan potensi luar biasa dari sisi non-kayu. "Misalnya getah damar, kemenyan, obat-obatan, dan sumber pangan. Semua itu bisa dikelola lestari,” katanya.
Dia berharap seminar ini dapat mendorong perhatian publik dan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan industri ekstraktif dalam pengelolaan hutan. Sumatera Utara memiliki kawasan hutan seluas 3 juta hektare. Dalam pemanfaatannya menurutnya masih harus dioptimalkan.
“Apakah pemanfaatannya optimal? Apakah kita hanya fokus pada pemanfaatan ekstraktif, eksplotatif gitu ya? Nah, bagaimana dengan nilai-nilai kandungan hutan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan yang bisa melebihi nilai dari kayu, bisa melebihi nilai-nilai dari ekstraktif lainnya,” katanya.
Menurutnya, ada opsi pemanfaatan hutan yang secara lestari, yang tidak merusak ekosistem namun tidak dioptimalkan. “Sebenarnya itu sih yang menggagas kenapa GJI melaksanakan acara ini mengingat memang penting narasi-narasi ini diangkat kembali,” katanya.
Dicontohkannya, berbagai potensi hutan yang dapat dikelola secara berkelanjutan, salah satunya getah kemenyan yang kini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat.
Masyarakat selama ini telah mengelola HHBK dan menjaga keutuhan ekosistem hutan, namun banyak yang belum mendapatkan pengakuan hukum, baik sebagai hutan desa maupun hutan adat.
Panut menambahkan, Presiden dan Wakil Presiden bahkan sudah menyinggung soal kemenyan. Namun, pengelolaan HHBK sering kali masih terbentur akses dan legalitas bagi masyarakat adat maupun desa hutan. “Masyarakat sebenarnya sudah mengelola hutan secara turun-temurun, menjaga ekosistem, dan menggantungkan hidup dari HHBK. Tapi banyak yang belum mendapat pengakuan resmi,” jelasnya.
Selain kemenyan, lanjut Panut, tenun ulos dengan pewarna alami dari hutan yang bisa bernilai sepuluh kali lipat dibanding pewarna sintetis. Demikian pula jamur hutan, eco-print, hingga berbagai produk turunan HHBK lain yang bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.
Sayangnya, kata Panut, pemerintah masih lebih memilih industri instan yang cepat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). “Padahal masyarakat juga butuh kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya melihat sumber daya alam dikeruk habis-habisan,” tegasnya.
Ia menyebut regulasi sebenarnya sudah ada, salah satunya lewat skema perhutanan sosial dengan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) ataupun Rencana Usaha Perhutanan Sosial (RUPS) yang mencakup pengelolaan HHBK. Panut menilai, skema ini bisa menjadi jalan keluar untuk mendorong industri HHBK naik kelas dan memberi manfaat nyata.
“Kalau dikelola dengan baik, HHBK bisa jadi strategi pengelolaan hutan yang lestari sekaligus sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat,” katanya.
Pengelolaan HHBK dan Kemandirian Petani
Direktur Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LESOS) yang berkantor di Jawa Timur, Purnomo menjelaskan panjang-lebar perjalanan lembaganya sejak awal 1990-an bergerak di bidang lingkungan hingga fokus pada penguatan ekonomi masyarakat tepi hutan melalui produk-produk organik dan hasil hutan non-kayu.
Dikatakannya, LESOS berdiri sebagai bagian dari upaya di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman, sebuah desa kecil di lereng Gunung Penanggungan (1.653 mdpl), yang sudah lama dikenal secara internasional karena komitmennya pada lingkungan. Sejak 2006, lembaga ini mulai mendorong produk organik, baik hasil budidaya maupun hasil hutan.
“Dari hasil hutan ini cukup menarik sebenarnya, karena bisa memperkuat masyarakat tepi hutan secara ekonomi. Tapi di sana banyak problem yang dihadapi,” ujarnya.
Ada yang Mengkhawatirkan
Dijelaskan Purnomo, sudah terjadi penurunan daya dukung lahan yang diduga akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat, karena keterbatasan keterampilan, sering merambah lebih jauh ke dalam hutan lindung, bahkan hingga ke puncak Gunung Kerinci.
“Alhamdulillah ada potensi pengelolaan hutan non kayu, misalnya kopi. Itu bisa menghentikan perambahan. Tapi di sisi lain, penggunaan racun kimia yang berlebihan merusak tanah dan menimbulkan banyak penyakit tanaman,” jelasnya.
Menurut Purnomo dampaknya begitu jelas, seperti tanah longsor, banjir di daerah yang sebelumnya tidak pernah tergenang, serta erosi yang menggerus nutrisi lahan. Purnomo mencontohkan daerah Sumbawa yang dulunya tidak pernah banjir, namun berubah setelah ada program pemerintah yang memaksa pembukaan lahan secara besar-besaran.
Keterbatasan Akses
Selain kerusakan lingkungan, problem utama yang dihadapi masyarakat tepi hutan adalah keterbatasan akses: dari permodalan, pasar, hingga informasi. Meski kini jaringan internet dan televisi sudah menjangkau desa-desa, informasi spesifik mengenai komoditas bernilai ekonomi masih sulit didapatkan oleh petani.
“Masyarakat sebenarnya punya peluang besar. Misalnya tanaman untuk kosmetik atau medis, itu nilainya tinggi. Tapi mereka minim informasi. Akhirnya banyak yang lebih memilih menanam sayur cepat panen, walau sebenarnya sering rugi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola tanam monokultur yang kerap didorong program pemerintah juga berisiko. Menurutnya, stabilitas lingkungan menuntut keberagaman tanaman: kopi, kakao, alpukat, hingga pohon kayu untuk kebutuhan jangka panjang. “Petani tidak hanya butuh makan atau kopi saja. Mereka juga butuh kayu untuk membangun rumah. Jadi harus ada kombinasi,” tegasnya.
Faktor Ketergantungan
Purnomo juga menyoroti mahalnya biaya produksi akibat benih, pupuk, dan pestisida yang kini menjadi komoditas dagang besar. Petani semakin jarang membuat benih sendiri, dan kasus kriminalisasi kepala desa di Aceh yang mengembangkan benih padi lokal menjadi peringatan.
“Bayangkan, kalau lima perusahaan benih jagung berhenti menjual, dalam tiga bulan ketahanan pangan kita bisa runtuh. Itu bahaya besar,” ucapnya. Karena itu, ia mendorong agar benih lokal bisa dikembangkan oleh masyarakat sendiri, dengan dukungan perguruan tinggi maupun dinas terkait.
Di tengah persoalan itu, Purnomo menekankan banyak komoditas hasil hutan yang punya nilai tinggi namun belum digarap maksimal. Ia mencontohkan sukun yang kini diolah menjadi tepung bebas gluten dan laris di pasar Amerika. Begitu juga alpukat yang diminati karena tren kesehatan, serta minyak sirih yang bernilai ratusan ribu rupiah per kilogram.
“Kalau di hutan ada kayu, bisa juga ditanam rambatan seperti kemukus, merica, atau vanili. Jadi satu pohon bisa menghasilkan banyak. Pertanian modern seharusnya seperti itu: nanam satu, dapat banyak,” katanya.
Konsep ini berbeda dengan pertanian konvensional yang hanya mengandalkan satu komoditas. Dengan pola multikultur, petani bisa memperoleh pendapatan dari berbagai sumber sekaligus, sekaligus menjaga ekosistem hutan.
Menurutnya, masyarakat hutan selama ini terjebak dalam budidaya semata, tanpa keterampilan hilirisasi. Produk kopi misalnya, hanya dijual dalam bentuk biji hijau dengan harga Rp140 ribu per kilogram. Padahal setelah dipanggang, nilainya bisa naik lebih dari dua kali lipat.
“Kalau masyarakat hanya menjual hasil mentah, mereka tidak pernah dapat nilai tambah. Padahal dari green bean ke roasted, nilainya bisa 100 persen lebih tinggi. Itu yang harus dinikmati petani,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi model perdagangan yang tidak transparan. Menurutnya, petani seharusnya tahu harga jual akhir produk mereka, bukan hanya harga di tingkat tengkulak. Skema seperti fair trade dan organik diharapkan bisa menjembatani hal tersebut.
Purnomo mengingatkan agar setiap program pendampingan tidak sekadar melibatkan masyarakat sebatas tenaga kerja atau formalitas musyawarah. Mereka harus benar-benar menjadi bagian dari kepemilikan usaha, baik dalam bentuk koperasi maupun perusahaan.
“Kalau bikin perusahaan, masukkan masyarakat jadi pemilik. Kalau koperasi, mereka harus jadi anggota. Jangan sampai kita yang datang ke desa malah jadi juragan baru. Sudah waktunya masyarakat diberikan kepercayaan penuh,” katanya.
Sementara itu, akademisi Universitas Sumatera Utara Dr. Iwan Risnasari, S.Hut., M.Si., menjelaskan, masyarakat selama ini masih terjebak pada pandangan bahwa hutan hanya bernilai dari kayu. Padahal, di balik itu terdapat banyak sumber daya lain yang bernilai ekonomi tinggi.
“Tantangannya degradasi hutan, deforestasi. Sebenarnya kenapa muncul degradasi, deforestasi? Mungkin karena mindset masyarakat kita bahwa hasil hutan yang penting itu kayu. Padahal kalau kita lihat hasil hutan selain dari kayu ternyata tidak kalah banyak nilai ekonominya,” ujarnya.
Dikatakannya, pemanfaatan zat pewarna alami dari berbagai tumbuhan, termasuk mangrove dan tanaman khas daerah. Di Nusa Tenggara, misalnya, masyarakat masih mengolah akar mengkudu sebagai pewarna merah tanpa campuran kimia. Namun, tingginya permintaan seringkali mendorong eksploitasi berlebihan hingga dikhawatirkan tanaman tersebut punah.
“Sehingga ada kekhawatiran, ini nanti lama-lama punah. Mungkin bisa jadi karena kurang sosialisasi bahwa harus ada budidaya,” jelasnya.
Di Sumatera Utara, potensi pewarna alami juga melimpah. Kayu tinggi, secang, mahoni hingga limbah kayu merbau terbukti menghasilkan pigmen warna. Bahkan, riset kecil yang dilakukannya menunjukkan serbuk kayu merbau bekas panglong laku terjual hingga puluhan kilogram hanya dalam dua hari.
“Artinya kan potensial ya, selama kita tahu apa potensinya. Selama ini mungkin kita tidak tahu apa saja potensi yang ada di sekitar kita,” katanya.
Selain pewarna alami, komoditas lain seperti madu, rotan, dan resin jernang juga menjanjikan. Namun, data dan pemetaan potensi HHBK di Indonesia masih minim. Padahal, di pasar global, jernang telah lama dipakai sebagai bahan pewarna keramik maupun farmasi.
Dijelaskannya, pengembangan HHBK tidak cukup berhenti pada pelatihan masyarakat. Tantangan besar justru terletak pada pemasaran dan keberlanjutan usaha. “Seringkali kendalanya itu di situ. Mereka diberi keterampilan, sumber dayanya ada di samping rumah mereka. Tapi setelah jadi, dibawa ke mana? Ngejualnya ke mana?” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi lintas pihak, mulai dari universitas, pemerintah, hingga sektor swasta. Pendampingan berkelanjutan, terutama dalam aspek digital marketing, pengemasan produk, hingga akses pameran dinilai penting agar produk masyarakat bisa menembus pasar.
“Kalau kelompoknya itu aktif, giat, bahkan akhirnya mereka bisa ikut pameran kemana-mana, bisa juga menjadi narasumber kemana-mana, kita kan senang. Artinya transfer ilmu yang kita lakukan itu berdampak,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menggali kearifan lokal. Beberapa komunitas adat di Sumatera Utara, misalnya, telah lama menggunakan kulit kayu Sikam dan Balaka untuk kuliner maupun pewarna. Potensi ini bisa dikembangkan ke industri tekstil, tenun, dan batik alami yang kini banyak diminati pasar luar negeri.
“Optimalisasi HHBK bukan hanya soal ekonomi, tapi juga untuk kelestarian hutan. Karena ketika masyarakat mengetahui ada nilai ekonomi dari cabang, daun, atau serbuk kayu, mereka bisa memanfaatkannya tanpa merusak. Kuncinya adalah sinergi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi USU, Liana Dwi Sri Hastuti yang sudah bertahun-tahun meneliti tentang jamur. Dikatakannya jamur memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan, obat-obatan, hingga kosmetik. Menurutnya, keanekaragaman jamur di Indonesia sangat tinggi karena statusnya sebagai salah satu negara mega biodiversitas.
“Jamur sangat potensial sebagai pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Mereka bisa dikembangkan di bidang pertanian, kesehatan, bahkan menjadi solusi untuk krisis pangan, terutama bagi anak-anak yang mengalami stunting karena kekurangan protein,” jelasnya.
Jamur, lanjut Liana, memiliki keunggulan dibandingkan sumber protein hewani seperti ayam atau daging sapi, karena efek sampingnya rendah bagi kesehatan. Namun, meski permintaan jamur di Sumatera Utara tinggi, produksi lokal masih jauh dari mencukupi. “Permintaan jamur sangat besar, tetapi budidaya di Sumatera Utara masih rendah. Padahal banyak spesies jamur yang belum diteliti dan bisa dimanfaatkan,” tambahnya.
Beberapa jenis jamur bahkan bernilai ekonomi tinggi di pasar internasional, seperti jamur susu harimau yang bisa mencapai harga Rp1 juta per kilogram dan jamur travel yang harganya menembus Rp4 juta per kilogram. Namun, menurut Liana, sebagian besar permintaan justru datang dari luar negeri karena kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia akan potensi jamur.
Selain bernilai ekonomi, jamur juga berkhasiat bagi kesehatan. Beberapa spesies diketahui dapat membantu mengatasi penyakit kanker, jantung, hingga diabetes. Sayangnya, penelitian di Indonesia masih minim karena keterbatasan musim, biaya, serta sarana pendukung. “Jamur biasanya muncul pada musim hujan dan petir, itu pun terbatas. Penelitian dan riset masih sangat sedikit,” ungkapnya.
Untuk itu, Liana mendorong pemerintah agar lebih serius mendukung pengembangan jamur, termasuk memberikan bantuan kepada petani. Ia mencontohkan pengalaman membina komunitas petani jamur di Medan yang mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp20 juta per bulan, meski dengan fasilitas terbatas.
Menurutnya, teknologi budidaya jamur sebenarnya tidak mahal jika dilakukan dengan inovasi sederhana. Misalnya, penggunaan kulkas bekas untuk mengatur suhu atau alat kelembapan rakitan sendiri. “Rekayasa iklim untuk budidaya jamur bisa dilakukan secara sederhana, bahkan dengan peralatan rumah tangga yang dimodifikasi. Jadi ini sangat mungkin dikembangkan sebagai industri rumahan,” terangnya.
Liana menutup paparannya dengan ajakan agar riset dan pemberdayaan masyarakat di bidang jamur diperkuat. “Potensinya luar biasa, baik untuk pangan, kesehatan, maupun ekonomi. Sayangnya kita masih jauh tertinggal dalam pengembangan. Ini saatnya pemerintah dan akademisi bersama-sama mendorong pengelolaan jamur secara serius,” tegasnya.
Memperkaya diskusi, dalam sesi kedua, Onrizal juga mengemukakan hasil risetnya. Akademisi USU itu menjelaskan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dinilai mampu menjadi alternatif sumber penghidupan masyarakat sekaligus strategi menjaga kelestarian hutan.
Jika dikelola dengan baik, lanjutnya, HHBK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak ekosistem hutan. “Kalau berhasil, ini akan menjadi alternatif pencarian penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan begitu, hutan tetap lestari, sementara nilai ekonominya juga mendukung kesejahteraan,” jelasnya.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan, terutama terkait jaminan kualitas dan keamanan produk HHBK, khususnya yang berbentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. “Untuk itu dibutuhkan riset mendalam agar produk dari hutan benar-benar aman dan bermanfaat bagi manusia,” tambahnya.
Lebih jauh, Onrizal menekankan potensi ekosistem mangrove sebagai contoh nyata pemanfaatan HHBK yang berkelanjutan. Mangrove tidak hanya berfungsi menjaga garis pantai dan menjadi habitat biota laut, tetapi juga bernilai ekonomis tinggi. “Kalau mangrovenya baik, makanan tersedia sempurna dan keanekaragaman hayati meningkat. Tapi kalau rusak, populasinya akan punah,” tegasnya.
Masyarakat pesisir, lanjut Onrizal, dapat mengembangkan berbagai produk turunan mangrove, mulai dari sirup, dodol, minuman fermentasi nira nipah, hingga pemanfaatan untuk ekowisata. Ia mencontohkan kawasan Nagalawan yang berkembang dengan homestay, kedai kopi berbasis produk mangrove, dan ekoprint. “Dengan pengelolaan yang tepat, lahan terbatas pun bisa mendatangkan nilai ekonomi hingga miliaran rupiah,” katanya.
Onrizal menutup paparannya dengan menegaskan bahwa pengelolaan HHBK, termasuk mangrove, harus memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Ia juga menekankan pentingnya riset, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. “Keberhasilan pengelolaan mangrove bisa menjadi alternatif nyata bagi masyarakat dibandingkan ketergantungan pada industri ekstraktif seperti tambang atau perkebunan monokultur,” ujarnya.
Kepala Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Tampan Sitompul dalam seminar itu menjelaskan perjuangan menjaga kemenyan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan kelestarian hutan adat.
Menurutnya, harga kemenyan selama ini sering dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak jelas. Kondisi itu merugikan petani.
“Harga dari haminjon ini terkesan buruk akibat mafia-mafia yang tidak kita tahu dari mana. Itulah yang membuat posisi petani kemenyan lemah,” ujar Tampan.
Ia menilai kehadiran inisiatif hilirisasi kemenyan yang sempat dibicarakan hingga ke level Wakil Presiden memberi peluang baru. Dengan adanya pengolahan menjadi minyak esensial atau produk turunan, masyarakat adat dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar.
“Di Singapura sekarang sudah ada mesin pengolah bahan baku menjadi minyak ekstrak. Kalau itu memungkinkan, kami bisa menjualnya sebagai minyak, bukan sekadar bahan mentah,” jelasnya.
Ia menambahkan, sudah ada pula rencana industri yang bisa mengolah kemenyan menjadi parfum dan produk bernilai tinggi lain. Bagi masyarakat Simardangiang, keberadaan pabrik pengolahan kemenyan di kawasan mereka akan berdampak positif. “Kalau produksi lebih dekat ke kampung, otomatis harga akan meningkat. Itu harapan kami,” tegasnya.
Komitmen Menjaga Hutan
Tampan menegaskan, profesi petani kemenyan tidak bisa digantikan begitu saja. Proses menoreh pohon kemenyan membutuhkan keahlian khusus dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terbiasa menjaga serta melestarikan hutan.
“Tidak semua orang bisa menyadap pohon kemenyan. Harus orang yang sudah melihat, menumbuhkan, menjaga, dan melestarikannya. Kalau petani kemenyan keluar, otomatis produksi hilang,” katanya.
Karena itu, ia menolak pandangan bahwa masyarakat harus meninggalkan kemenyan demi komoditas lain. Masyarakat adat, lanjutnya, justru berkomitmen untuk terus menanam kemenyan baru tanpa merusak hutan. “Kami tetap menumbuhkan kemenyan. Bukan mengganti hutan dengan tanaman lain, tapi menjaga agar tetap jadi hutan hasil hutan bukan kayu,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, di Desa Simardangiang terdapat tiga jenis pohon kemenyan: Haminjon Towa, Haminjon Durame, dan Haminjon Bulu. Masing-masing memiliki karakteristik pertumbuhan dan nilai ekonomi berbeda. “Haminjon Towa itu paling mahal, getahnya putih dan aromanya beda. Tapi baru bisa disadap tujuh sampai sepuluh tahun setelah ditanam,” katanya.
Sementara Durame bisa dipanen dalam lima sampai tujuh tahun, dan Bulu lebih cepat lagi, sekitar empat sampai tujuh tahun. Namun, meski lebih lama, Towa tetap dipertahankan karena kualitas getahnya unggul dan bisa berproduksi ratusan tahun. “Ada pohon kemenyan umur 150 tahun lebih, sampai sekarang masih berproduksi,” ungkapnya.
Merawat Kearifan Lokal
Penyadap kemenyan, kata Tampan, bukan sekadar soal teknis melukai batang pohon. Pohon dianggap punya “waktu” sendiri untuk mengeluarkan getah. Jika disadap pada waktu yang salah, getah tidak keluar, bahkan pohon bisa menutup lukanya sendiri.
“Kalau dikerjakan sesuai selera pohon, dia akan mengeluarkan banyak getah. Tapi kalau dipaksa, tidak akan berhasil. Pohon kemenyan ini unik, dia hidup bergampingan dengan manusia dan hutan sekitarnya,” terangnya.
Proses menyadap juga membutuhkan tenaga ekstra. Untuk satu pohon, dibutuhkan waktu setengah jam, sehingga dalam sehari seorang petani hanya bisa menggarap enam pohon. “Berbeda dengan karet, kalau kemenyan hasilnya terbatas. Karena itu harus dikumpulkan sedikit demi sedikit,” jelasnya.
Tampan menegaskan bahwa masyarakat adat Simardangiang tidak akan menebang pohon kemenyan, bahkan ketika pohon sudah tidak produktif.
“Di kampung kami sangat dilarang menebang pohon kemenyan. Bahkan sebesar-besarnya, pohon itu tidak boleh ditebang. Biarlah dia mati dengan sendirinya,” katanya.
Dari Sopir Truk Kini Praktisi Kopi
Praktisi kopi asal Marancar, Tapanuli Selatan, Abdul Wahid Harahap, berbagi pengalamannya dalam mengembangkan usaha kopi berkonsep konservasi. Dalam sebuah seminar hasil hutan bukan kayu (HHBK), ia menekankan bahwa kopi bukan sekadar komoditas, melainkan juga jalan menuju kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.
“Kami para petani justru lebih menjaga hutan daripada yang sering dianggap orang. Kami tidak pakai pestisida kimia, tidak merusak hutan. Limbah rumah tangga kami olah jadi pupuk. Konsepnya sederhana: bertani sambil menjaga alam,” ungkap Wahid.
Sejak 2008, Wahid mengelola Tyyana Kopi, sebuah usaha yang kini dikenal luas hingga mancanegara. Kopi Arabika dari Marancar disebutnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena ditanam secara ramah lingkungan. Ia bahkan pernah menerima penghargaan dari Kementerian Kehutanan atas komitmennya mengembangkan kopi dengan konsep konservasi.
Lebih jauh, Wahid menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk melanjutkan perjuangan menjaga hutan sekaligus mengolah hasilnya secara bijak. “Kami ini sudah hampir pensiun. Tangannya sekarang di adik-adik mahasiswa. Jangan terlena isu-isu, tapi punya komitmen membangun desa, mengolah hutan jadi sumber ekonomi,” pesannya.
Usaha kopinya juga unik karena mengusung konsep sosial. Di kafenya, pengunjung bisa “minum kopi sepuasnya, bayar seikhlasnya”. Menurut Wahid, konsep ini lahir dari keprihatinan bahwa para petani sering tidak bisa menikmati kopi terbaik yang mereka hasilkan sendiri.
Meski usahanya kini berkembang menjadi agrowisata dengan kafe, kolam, hingga pengolahan kopi di lahan sendiri, Wahid menegaskan perjalanan itu tidak mudah. Delapan tahun pertama ia membangun usaha nyaris tanpa modal, hanya bertahan berkat ketekunan dan dukungan keluarga. “Saya mulai dari nol. Pernah delapan tahun membuka usaha tanpa sekalipun memberi uang belanja ke istri. Tapi justru di situ kami ditempa,” kisahnya.
Wahid berharap pemerintah dan lembaga-lembaga pendamping seperti NGO lebih serius mendukung petani kopi dan pelaku HHBK. Menurutnya, kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah sangat penting agar kopi dan hasil hutan bukan kayu lainnya bisa menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan.
“Kalau diukur dari sisi ekonomi, kopi tidak kalah nilainya dengan profesi lain. Bedanya, kami menjaga hutan, bukan merusaknya. Harapan saya, ke depan semakin banyak mahasiswa dan generasi muda yang mau turun ke lapangan, jadi pelaku, bukan sekadar penonton,” katanya.
(REL/RZD)