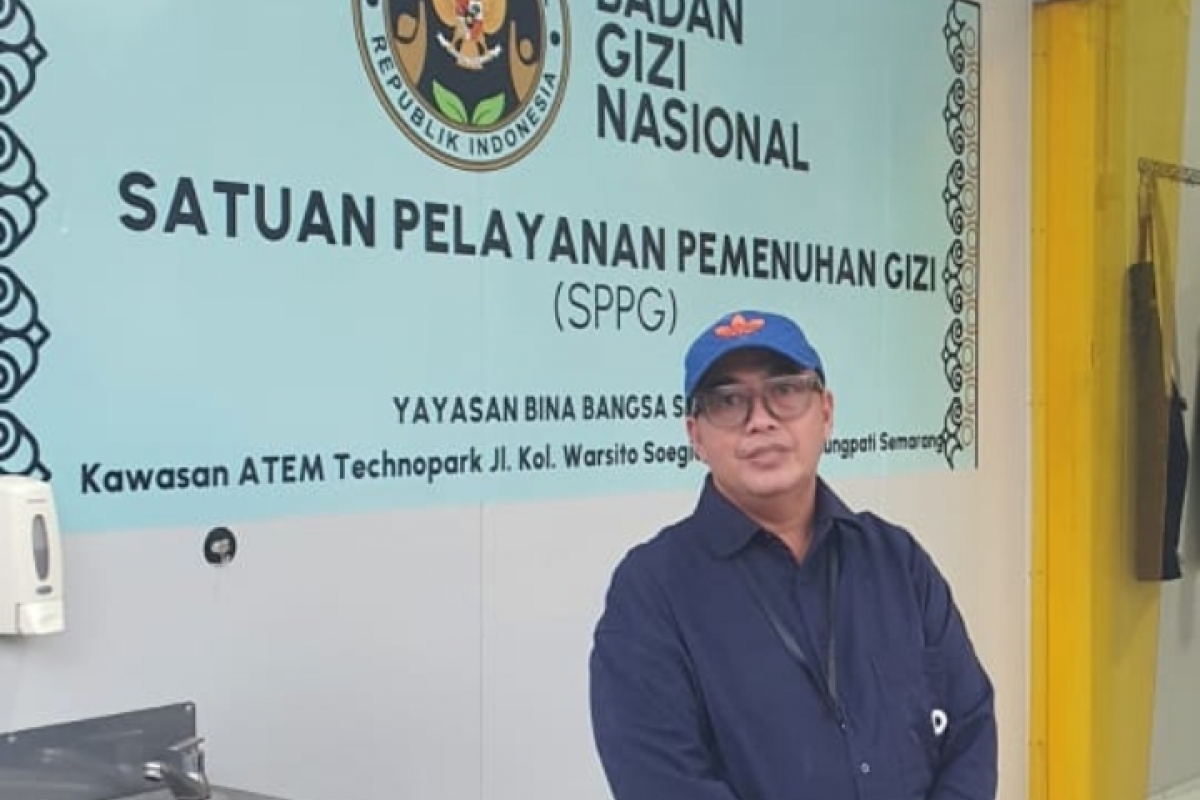
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menempati posisi penting dalam agenda pembangunan nasional. Program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendasar bangsa: memastikan anak-anak Indonesia, terutama mereka yang bersekolah dan berasal dari kelompok rentan, mendapatkan akses gizi yang layak. Dengan target menjangkau jutaan penerima manfaat, MBG dipandang sebagai salah satu strategi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan prevalensi stunting, sekaligus membangun fondasi kesehatan generasi mendatang.
Namun, dalam euforia menyambut program besar ini, kita tidak boleh melupakan satu dimensi penting yang menentukan keberhasilan yaitu keamanan pangan. Sebagus apa pun kandungan gizi yang disiapkan, apabila bahan pangan yang dipakai tidak aman, justru akan menimbulkan masalah baru. Kasus keracunan makanan massal di sekolah, pesantren, hingga kegiatan sosial kerap menghiasi pemberitaan. Jika kejadian serupa menimpa program sebesar MBG, dampaknya bukan hanya pada kesehatan anak-anak, tetapi juga pada citra dan keberlanjutan kebijakan nasional ini.
Risiko yang mengintai cukup beragam. Pertama, potensi terjadinya keracunan massal akibat kesalahan penyimpanan, distribusi, atau pengolahan makanan. Dalam skala kecil, kasus seperti ini mungkin bisa segera diatasi. Namun dalam skala nasional dengan jutaan penerima manfaat, efek domino bisa sangat besar: dari beban rumah sakit, keresahan publik, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Kedua, ada risiko penyebaran penyakit zoonosis.
Indonesia masih menghadapi ancaman penyakit menular yang bersumber dari hewan, seperti flu burung atau rabies. Jika bahan pangan hewani untuk MBG tidak diawasi secara ketat, penyakit-penyakit ini dapat masuk ke rantai konsumsi manusia. Di sinilah pentingnya penerapan pendekatan One Health, yang menempatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Ketiga, kualitas gizi itu sendiri bisa menurun jika bahan pangan tercemar.
Kontaminasi logam berat di sayuran, residu pestisida di buah, atau mikroplastik dalam hasil laut, semuanya bisa memengaruhi manfaat gizi yang ingin dicapai. Bukannya memperbaiki status kesehatan anak, pangan yang tercemar justru bisa memperburuk kondisi mereka dalam jangka panjang.
Realitas Lapangan di SumutHasil audiensi di Sumatera Utara memberi gambaran nyata tentang tantangan implementasi MBG. Saat ini baru tersedia 225 dapur dari target 1.742 dapur, sementara penerima manfaat baru sekitar 752 ribu dari target 4,2 juta orang. Kesenjangan besar ini menunjukkan betapa pentingnya percepatan pembangunan fasilitas SPPG agar distribusi makanan benar-benar terjamin.
Selain itu, aspek kualitas pangan juga menjadi perhatian serius. Makanan yang disediakan harus rendah risiko penularan penyakit dan bebas praktik koruptif. Namun di lapangan, kualitas sering menurun, bahkan ada masalah bau organik dan keterbatasan pengendalian hama. Karena itu, pest control serta perizinan operasional dapur menjadi kunci, disertai peningkatan kapasitas penjamah makanan agar higienitas terjaga.
Pertanyaan kunci kemudian muncul: Bagaimana memastikan MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan sehat?Jawabannya tidak bisa sederhana. Dibutuhkan tata kelola pangan yang terpadu, yang menghubungkan aspek regulasi, pengawasan, edukasi, hingga partisipasi masyarakat. Regulasi dan standar memang penting, tetapi implementasi di lapangan jauh lebih menentukan. Pengawasan tidak boleh berhenti di pabrik atau gudang, melainkan harus menelusuri rantai pasok dari petani dan peternak hingga ke meja makan di sekolah. Selain itu, perlu ada keterlibatan banyak pihak.
Pemerintah pusat, daerah, sekolah, koperasi, UMKM penyedia pangan, hingga orang tua murid, semua harus berada dalam ekosistem yang sama: ekosistem yang sadar bahwa pangan yang bergizi belum tentu aman, dan pangan yang aman akan selalu menjadi syarat utama untuk mencapai gizi yang optimal.
Konteks Global dan Pembelajaran dari China
Dalam konteks global, keamanan pangan semakin ditempatkan sebagai isu strategis yang menyangkut kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan bahkan kepercayaan politik. Dunia sudah menyaksikan bagaimana insiden keracunan massal, wabah zoonosis, hingga kontaminasi pangan bisa mengguncang kepercayaan publik, menimbulkan kerugian ekonomi miliaran dolar, dan mengganggu perdagangan internasional.
Oleh karena itu, banyak negara kini membangun tata kelola pangan yang tidak hanya mengutamakan gizi, tetapi juga menekankan aspek keamanan, keterlacakan, dan ketahanan sistemik. Salah satu negara yang sering dijadikan rujukan adalah China. Setelah menghadapi serangkaian skandal pangan pada awal 2000-an, pemerintah China melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pengawasan pangan. Hasilnya adalah penerapan kerangka yang dikenal dengan nama “Four Strictests”: standar paling ketat, pengawasan paling ketat, sanksi paling berat, dan akuntabilitas paling serius. Empat prinsip ini menjadi pondasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.
“Standar paling ketat” diterjemahkan dalam bentuk harmonisasi regulasi nasional yang menyatukan lebih dari seribu standar keamanan pangan, sebagian besar selaras dengan Codex Alimentarius internasional. Hal ini memastikan bahwa pangan yang beredar di pasar domestik maupun ekspor tunduk pada aturan yang jelas dan konsisten. “Pengawasan paling ketat” dijalankan melalui inspeksi acak, pemantauan laboratorium, serta penerapan sistem keterlacakan digital.
“Sanksi paling berat” memberi efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar aturan, mulai dari denda besar hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, “akuntabilitas paling serius” menegaskan bahwa tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga pejabat regulator dapat dimintai pertanggungjawaban bila terjadi insiden.
Selain itu, China mengembangkan konsep “Three-dimensional integration”, yang menggabungkan kolaborasi lintas sektor, tata kelola bersama masyarakat, dan inovasi teknologi. Kolaborasi lintas sektor membuat kementerian pertanian, kesehatan, perdagangan, dan lingkungan bekerja dalam satu kerangka yang terpadu. Tata kelola bersama masyarakat memberi ruang bagi industri, sekolah, koperasi, hingga konsumen untuk ikut mengawasi dan melaporkan risiko. Inovasi teknologi melengkapi keduanya, melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), blockchain untuk keterlacakan rantai pasok, hingga whole-genome sequencing yang mempercepat deteksi sumber wabah penyakit bawaan pangan.
Hasil dari kombinasi kebijakan tersebut cukup mencolok. Tingkat kelulusan sampel pangan (food sample pass rate) meningkat secara konsisten dalam satu dekade terakhir. Lebih dari itu, hampir tidak ada lagi insiden sistemik besar yang merusak kepercayaan publik. Sistem keterlacakan pangan berbasis teknologi membuat penarikan produk (recall) bisa dilakukan lebih cepat, lebih spesifik, dan lebih transparan.
Pesan penting dari pengalaman China adalah bahwa One Health telah menjadi fondasi utama tata kelola pangan modern. Dengan menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, China memastikan bahwa keamanan pangan tidak hanya dinilai dari sisi gizi atau kebersihan produk akhir, tetapi dari seluruh ekosistem yang memengaruhi pangan.
Konsep ini memperlihatkan bahwa pangan aman adalah hasil dari sinergi lintas sektor mulai dari peternakan dan pertanian, kesehatan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan. Bagi Indonesia, pengalaman ini memberi pembelajaran berharga. Jika program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) ingin berhasil, tidak cukup hanya menyiapkan menu gizi. Harus ada kerangka tata kelola keamanan pangan yang ketat, terintegrasi, dan berbasis One Health. Tanpa itu, risiko keracunan massal, zoonosis, dan pencemaran lingkungan bisa mengancam tujuan mulia program tersebut.
Kondisi Indonesia Saat Ini
Indonesia sebenarnya memiliki kerangka regulasi yang cukup kuat dalam bidang keamanan pangan. Sejumlah perangkat hukum telah tersedia, mulai dari Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, standar nasional melalui SNI, hingga berbagai peraturan teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Pertanian. Namun, kekuatan regulasi ini masih menghadapi persoalan mendasar: sistemnya masih terfragmentasi. Setiap kementerian dan lembaga berjalan dengan kewenangan sendiri-sendiri, tanpa ada mekanisme koordinasi terpadu yang memastikan semua kebijakan bergerak ke arah yang sama.
Fragmentasi ini membuat pengawasan pangan lebih dominan di hilir, sementara pengawasan di hulu mulai dari budidaya pertanian, peternakan, hingga distribusi bahan pangan mentah masih relatif lemah. Akibatnya, potensi masalah keamanan pangan seringkali baru terdeteksi saat produk sudah beredar di pasar atau bahkan sudah dikonsumsi. Padahal, pencegahan di hulu jauh lebih efektif dan murah dibandingkan tindakan korektif di hilir.
Kelemahan ini tercermin dari berbagai kasus keracunan makanan di sekolah dan pesantren yang berulang setiap tahun. Banyak kejadian menunjukkan bagaimana pengelolaan makanan dalam skala besar, seperti katering sekolah atau konsumsi massal di pesantren, belum siap menghadapi risiko keamanan pangan. Mulai dari bahan baku yang tidak segar, proses pengolahan yang tidak higienis, penyimpanan tanpa rantai dingin, hingga distribusi yang tidak memenuhi standar. Kasus-kasus ini seharusnya menjadi peringatan bahwa sistem pengawasan kita belum cukup tangguh untuk program sebesar Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan melibatkan jutaan penerima manfaat.
Selain itu, tantangan lain yang tak kalah besar adalah rendahnya literasi pangan masyarakat, termasuk pelaku UMKM pangan yang akan menjadi bagian penting dari rantai pasok MBG. Banyak produsen kecil belum memahami prinsip dasar keamanan pangan seperti hazard analysis, praktik higiene yang baik, atau pentingnya keterlacakan produk.
Padahal, UMKM dan usaha kecil rumah tangga mendominasi rantai pasok pangan domestik. Tanpa pembinaan yang serius, mereka akan tetap menjadi titik rawan dalam upaya menjamin pangan yang aman.
Di sisi lain, sistem traceability atau keterlacakan pangan di Indonesia juga masih terbatas. Memang ada upaya pada komoditas ekspor seperti perikanan atau hortikultura, di mana standar internasional mengharuskan pencatatan rantai pasok. Namun untuk pasar domestik, keterlacakan pangan hampir belum berjalan. Akibatnya, ketika terjadi kasus keracunan, otoritas sering kesulitan menelusuri asal-usul bahan pangan yang bermasalah.
Situasi ini sangat berbeda dengan negara-negara yang sudah menggunakan teknologi digital, seperti QR code atau blockchain, untuk memastikan pangan dapat ditarik kembali (recall) dengan cepat dan tepat sasaran. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap transisi: regulasi sudah ada, tetapi implementasi belum maksimal. Tantangan terbesar bukan pada kurangnya aturan, melainkan pada lemahnya integrasi, koordinasi, dan pengawasan di lapangan. Jika tidak segera dibenahi, kelemahan ini dapat menjadi batu sandungan besar bagi keberhasilan MBG. Program yang bertujuan mulia meningkatkan gizi anak bangsa bisa terancam oleh masalah keamanan pangan yang sebenarnya dapat dicegah.
Pentingnya Tata Kelola Terpadu untuk MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda pemenuhan gizi, melainkan juga momentum emas untuk memperbaiki tata kelola keamanan pangan nasional. Jika hanya dipandang sebagai kegiatan distribusi makanan, maka MBG berisiko terjebak dalam rutinitas tanpa meninggalkan warisan kelembagaan yang kuat. Sebaliknya, jika program ini dijadikan pintu masuk untuk reformasi sistem pangan, Indonesia berpeluang besar membangun fondasi yang lebih kokoh dalam menjamin pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah integrasi lintas kementerian dan lembaga.
Selama ini, urusan pangan masih berjalan parsial: Kementerian Pertanian mengatur produksi, BPOM mengawasi peredaran dan produk olahan, Kementerian Kesehatan menangani risiko kesehatan masyarakat, sementara Kemendikbud dan Dinas Pendidikan bertanggung jawab pada aspek implementasi di sekolah. Fragmentasi ini harus diakhiri. MBG memerlukan sebuah mekanisme koordinasi terpadu, semacam task force nasional, yang menyatukan seluruh kementerian dan pemerintah daerah dalam satu garis kebijakan. Dengan integrasi, kebijakan tidak lagi tumpang tindih, dan pengawasan bisa berjalan konsisten dari hulu ke hilir.
Kedua, dibutuhkan co-governance dengan masyarakat. Pemerintah tidak mungkin mengawal MBG seorang diri. Sekolah sebagai titik distribusi, koperasi pangan yang menjadi penyedia, UMKM yang memproduksi makanan, hingga orang tua yang mendampingi anak, semua harus dilibatkan. Partisipasi masyarakat akan menciptakan budaya pengawasan bersama, di mana keamanan pangan bukan hanya urusan regulator, tetapi juga kesadaran kolektif.
Misalnya, koperasi sekolah atau koperasi merah putih di desa bisa diberdayakan untuk menjadi pusat distribusi bahan pangan segar yang terjamin kualitasnya, sementara orang tua bisa dilibatkan dalam forum evaluasi menu dan keamanan pangan.
Ketiga, inovasi digital harus menjadi pilar penting. Penggunaan QR code untuk keterlacakan bahan pangan bisa dimulai dari pemasok hingga kantin sekolah, sehingga setiap kasus bisa ditelusuri dengan cepat bila ada masalah. Aplikasi pelaporan risiko berbasis ponsel juga dapat dibuat, sehingga guru atau orang tua bisa langsung melaporkan gejala keracunan atau kecurigaan terhadap kualitas makanan. Selain itu, perlu didorong pembentukan laboratorium cepat di daerah yang mampu melakukan uji sederhana terhadap sampel pangan.
Teknologi digital akan menjadikan pengawasan lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Terakhir, penerapan pendekatan One Health merupakan syarat mutlak. MBG tidak boleh hanya dipandang dari sudut gizi anak, tetapi juga dari keterkaitannya dengan hewan dan lingkungan. Pencegahan zoonosis seperti flu burung sangat penting karena banyak bahan pangan berasal dari ternak dan produk hewani. Pengendalian resistensi antimikroba (AMR) juga harus diperhatikan, mengingat penggunaan antibiotik di peternakan dapat meninggalkan residu pada makanan yang dikonsumsi. Lebih jauh, menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran air, tanah, dan udara akan memastikan bahwa pangan yang dihasilkan tetap aman dan berkualitas.Dengan tata kelola terpadu, MBG dapat menjadi model reformasi sistem pangan nasional.
Program ini tidak hanya memberi makan jutaan anak sekolah, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan Indonesia agar lebih tangguh, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, MBG bisa dikenang bukan sekadar sebagai program gizi, melainkan sebagai tonggak lahirnya tata kelola pangan terpadu yang berpihak pada kesehatan generasi bangsa.
Sebagai Penutup, Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi besar bagi masa depan bangsa. Namun keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari distribusi makanan bergizi semata, melainkan juga dari jaminan bahwa pangan tersebut aman, higienis, dan bebas risiko kesehatan. Dengan tata kelola yang terpadu, pengawasan ketat, partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip One Health, MBG dapat menjadi contoh reformasi pangan nasional. Pada akhirnya, MBG bukan hanya tentang memberi makan, tetapi tentang memastikan generasi Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh.




















