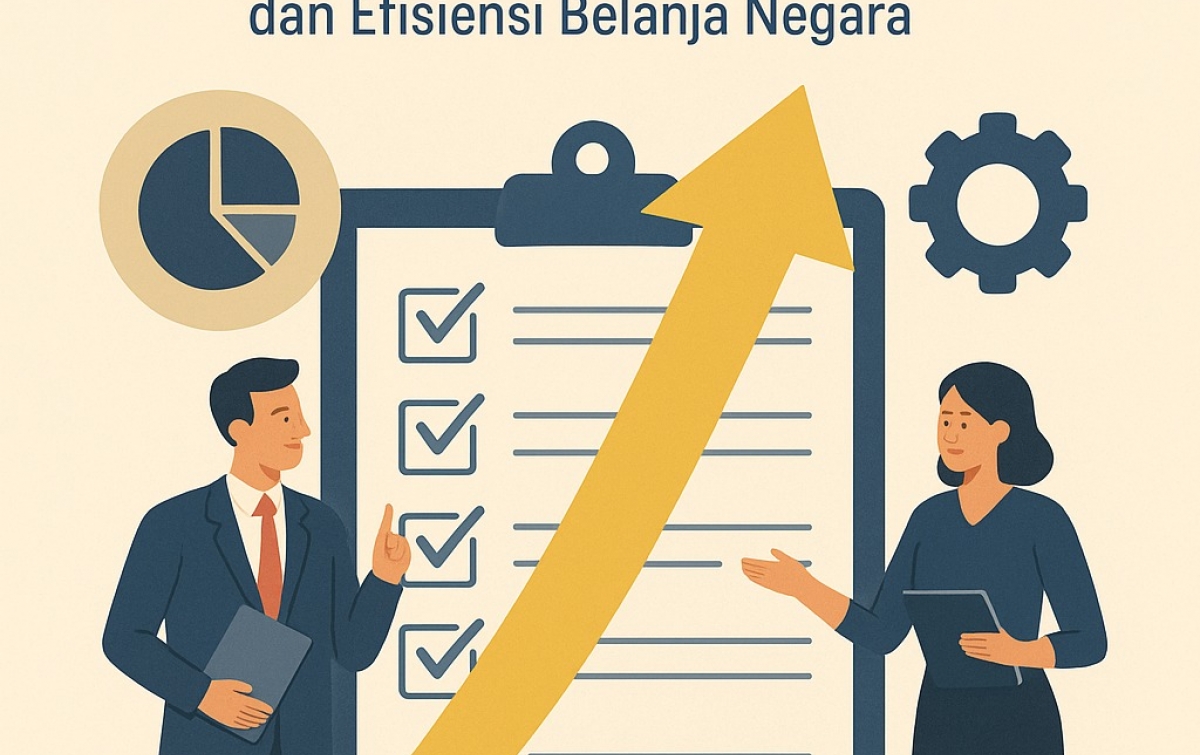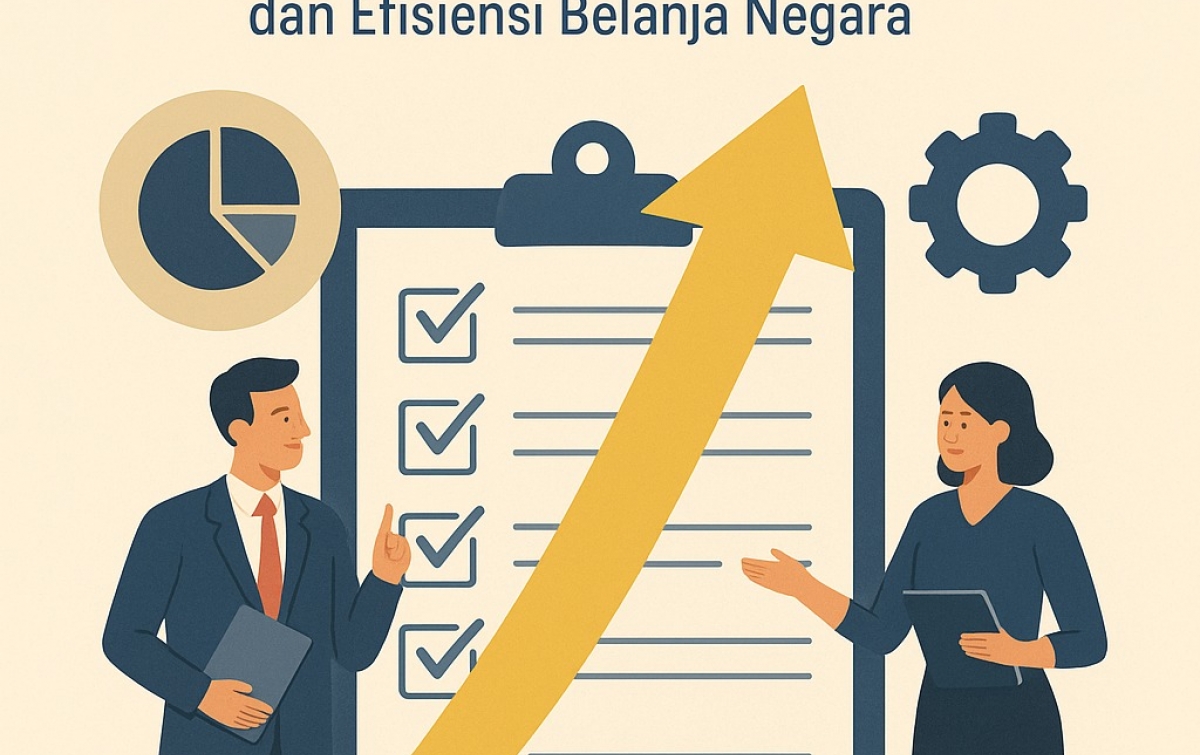
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Analisa/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Di tengah semakin ketatnya ruang fiskal dan tuntutan masyarakat atas kualitas belanja negara, pemerintah terus berupaya menghadirkan instrumen yang mampu memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara tepat, efisien, dan akuntabel.
Salah satu instrumen tersebut adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Bagi sebagian masyarakat, istilah IKPA mungkin terdengar teknis dan birokratis. Namun, sesungguhnya IKPA menyimpan makna penting. IKPA adalah cermin kedisiplinan satuan kerja pemerintah dalam mengelola anggaran, serta alat ukur yang menentukan seberapa berkualitas uang rakyat dibelanjakan.
Rsegulasi sebagai Fondasi
Posisi IKPA semakin kuat dengan terbitnya Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA. Aturan ini menegaskan bahwa IKPA bukan hanya sekadar angka administrasi, melainkan alat manajemen yang memandu satuan kerja agar lebih disiplin dalam perencanaan, lebih tertib dalam pelaksanaan, serta lebih transparan dalam pertanggungjawaban. Selain itu, PMK 107 Tahun 2024, yang merevisi PMK 62/2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, menekankan pentingnya keterpaduan. Perencanaan anggaran tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus tercermin nyata dalam kualitas belanja. Dalam konteks inilah IKPA hadir sebagai jembatan antara dokumen anggaran dengan hasil pembangunan.
Delapan Cermin Kedisiplinan Anggaran
Dengan delapan cermin tersebut, IKPA mengajarkan bahwa kualitas belanja bukan hanya soal berapa besar anggaran yang diserap, tetapi bagaimana prosesnya dijalankan secara disiplin dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Delapan Indikator yang Menjadi Tolak Ukur IKPA dibangun atas indikator yang secara bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang disiplin anggaran.
Pertama, revisi DIPA. Indikator ini mengukur seberapa sering dan signifikan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) mengalami perubahan. Semakin sering direvisi, semakin tampak bahwa perencanaan tidak stabil. Revisi memang terkadang diperlukan, tetapi jika berlebihan, hal itu mencerminkan lemahnya proyeksi kebutuhan di awal tahun.
Kedua, Deviasi Halaman III DIPA. Indikator ini menilai kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi. Deviasi yang tinggi bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan lemahnya kemampuan satker memperkirakan arus kas. Jika tidak terkendali, hal ini bisa mengganggu manajemen kas negara secara keseluruhan.
Ketiga, penyerapan anggaran. Indikator ini masih menjadi perhatian publik. Selama ini, belanja negara kerap menumpuk di ujung tahun anggaran. IKPA mendorong satker untuk menjaga ritme penyerapan yang merata sepanjang tahun, sehingga program pemerintah dapat lebih cepat memberi manfaat kepada masyarakat.
Keempat, belanja kontraktual. Pemerintah mengukur berapa besar belanja kontrak barang dan jasa yang terealisasi tepat waktu. Semakin cepat kontrak ditandatangani, semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
Kelima, penyelesaian tagihan. Indikator ini melihat kecepatan satker dalam memproses tagihan pembayaran. Ketepatan waktu sangat penting, bukan hanya untuk menjaga reputasi pemerintah, tetapi juga untuk memastikan penyedia barang dan jasa tidak dirugikan.
Keenam, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Walaupun jumlahnya relatif kecil, pengelolaan dana kas ini menjadi cermin kedisiplinan administrasi. Jika satker lalai, potensi penyalahgunaan dan moral hazard bisa muncul.
Ketujuh, dispensasi SPM. Indikator ini mencerminkan seberapa sering satker meminta pengecualian dalam penerbitan Surat Perintah Membayar. Semakin sering dispensasi diajukan, semakin besar indikasi adanya hambatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dan kedelapan, capaian output. Ini adalah indikator yang paling substantif: apakah belanja yang telah dikeluarkan benar-benar menghasilkan keluaran yang bermanfaat? Dengan kata lain, IKPA tidak hanya mengukur kepatuhan prosedur, tetapi juga efektivitas hasil.
Dari Angka Menjadi Akuntabilitas
Selama bertahun-tahun, penilaian kinerja anggaran di Indonesia kerap dianggap sebatas angka-angka administratif, berapa persen realisasi, seberapa cepat penyerapan, atau seberapa banyak revisi dilakukan. Paradigma ini memunculkan kritik bahwa pengelolaan APBN cenderung berorientasi pada compliance (kepatuhan prosedural) ketimbang pada accountability (pertanggungjawaban substantif).
Kehadiran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengubah lanskap tersebut. Delapan indikator yang digunakan tidak hanya merekam data finansial, melainkan juga menyingkap kualitas tata kelola fiskal. Misalnya, indikator Revisi DIPA bukan sekadar angka berapa kali dokumen anggaran diubah, tetapi mencerminkan apakah perencanaan awal sudah matang atau masih lemah. Begitu pula dengan Penyelesaian Tagihan, yang tidak hanya menunjukkan kecepatan proses administratif, tetapi juga kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha.
Dengan demikian, angka-angka IKPA memiliki dimensi ganda, di satu sisi, bersifat kuantitatif yang dapat diukur secara objektif di sisi lain, bersifat kualitatif yang menyingkap perilaku organisasi, efisiensi birokrasi, dan konsistensi perencanaan. Inilah yang dimaksud bahwa IKPA mampu membawa pemerintah “dari angka menuju akuntabilitas.”
Lebih jauh, PMK 107 Tahun 2024 menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak lagi sekadar dilaporkan pada akhir tahun, melainkan dibangun sejak awal perencanaan, dikawal saat pelaksanaan, dan diaudit saat pelaporan. Setiap indikator IKPA berfungsi sebagai check-point akuntabilitas yang memastikan bahwa belanja negara bukan sekadar terserap, tetapi benar-benar memberikan manfaat.
Dalam perspektif akademik, pendekatan ini selaras dengan konsep New Public Management (NPM) yang menekankan orientasi hasil (result oriented government). Negara modern tidak cukup hanya menunjukkan berapa banyak uang yang dihabiskan, melainkan harus membuktikan apa hasil dari setiap rupiah yang dibelanjakan. IKPA, melalui indikator Capaian Output, menjadi instrumen penghubung langsung antara realisasi anggaran dengan outcome pembangunan.
Implikasi praktisnya sangat signifikan. Ketika angka IKPA dipublikasikan dan dibandingkan antar-satuan kerja, ia menciptakan insentif kompetitif bagi lembaga untuk memperbaiki kinerja. Dengan demikian, akuntabilitas tidak lagi hanya menjadi jargon birokrasi, melainkan nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Singkatnya, IKPA menggeser makna angka anggaran dari sekadar laporan akuntansi menjadi cermin akuntabilitas negara. IKPA menuntut agar setiap rupiah APBN tidak hanya tercatat dalam laporan, tetapi juga hadir dalam bentuk layanan publik yang dirasakan rakyat.
Menjaga Efisiensi Belanja Negara
Kelebihan lain dari IKPA adalah kemampuannya menjaga dan mengawasi efisiensi belanja negara. Ambil contoh indikator deviasi rencana penarikan dana. Jika rencana tidak sesuai realisasi, maka arus kas negara bisa terganggu. Begitu juga dengan keterlambatan penandatanganan kontrak. Semakin lama kontrak ditandatangani, semakin terlambat pula manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Dengan menilai hal-hal detail ini, IKPA mencegah anggaran terbuang percuma akibat perencanaan yang lemah atau eksekusi yang lambat. Anggaran yang dikelola secara efisien tidak hanya menjaga kesehatan fiskal negara, tetapi juga memastikan hasil pembangunan hadir tepat waktu.
Efisiensi belanja negara bukan hanya soal mengurangi pengeluaran atau menekan biaya, tetapi lebih pada mengoptimalkan penggunaan setiap rupiah APBN agar menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam literatur administrasi publik, efisiensi dipahami sebagai perbandingan antara input (sumber daya) dengan output (hasil kerja)—semakin besar hasil yang diperoleh dengan biaya yang sama, semakin efisien suatu organisasi publik.
Menjadikan IKPA Sebagai Budaya, Bukan Sekadar Nilai
Ke depan, IKPA harus dipahami bukan hanya oleh pengelola anggaran di satuan kerja, tetapi juga oleh pimpinan instansi, pengambil kebijakan, bahkan masyarakat. IKPA harus menjadi budaya baru birokrasi dalam mengelola anggaran: disiplin sejak perencanaan, tertib dalam pelaksanaan, cepat dalam pertanggungjawaban, dan fokus pada hasil.
Dengan dukungan regulasi yang kuat melalui, IKPA berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan belanja negara yang lebih berkualitas. Pada akhirnya, indikator ini akan memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar dikelola secara transparan, efisien, dan menghasilkan manfaat nyata.
Karena itu, ketika kita berbicara tentang APBN, sejatinya kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa. Dan melalui IKPA, masa depan itu sedang diarahkan agar lebih akuntabel, lebih efisien, dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Berita kiriman dari: Tulus Halomoan Marbun, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara