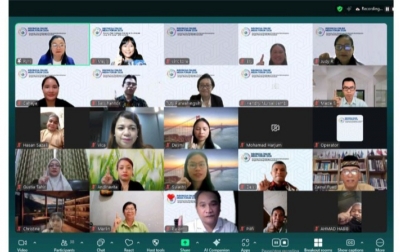Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Air yang turun, luka yang tertinggal. Pagi yang seharusnya biasa di Sumatera berubah menjadi lembar sejarah pahit. Lumpur menutupi rumah, jembatan beterbangan seperti lidi, dan ratusan keluarga masih mencari nama yang tak kunjung kembali.
Di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), air surut hanya meninggalkan satu hal, yakni sunyi yang penuh kemarahan. Di balik sunyi itu, ada angka-angka yang bicara jauh lebih keras dari pidato konferensi pers, yakni 712 ribuan jiwa meninggal, 3,2 juta lebih warga terdampak, tiga provinsi lumpuh, infrastruktur nasional rusak parah.
"Di bahasa hukum PP 21/2008, semua ini seharusnya punya satu kalimat “ini bencana nasional.” Namun sampai detik ini, status itu belum keluar. Di sinilah kisah ini mulai berubah dari sekadar bencana alam menjadi kisah 20 tahun peringatan yang tak diindahkan," tegas Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Selasa (9/12).
Menurut Iskandar, LHP BPK sejak 2005 berkali-kali menulis kalimat yang mirip, yakni hutan gundul, izin amburadul, DAS rusak, dan sistem peringatan dini tak sinkron. Selama 20 tahun pula, BPK mencatat pola yang sama:
1. Izin sawit dan tambang di hulu DAS diterbitkan tanpa analisis risiko banjir-dasar,
2. Kerusakan hutan hujan Sumatera meningkat 500–600 ribu hektare per lima tahun,
3. Peralatan early warning tidak dirawat,
4. Koordinasi antarprovinsi rapuh, karena tiap daerah lebih sibuk membuka lahan daripada menjaga bukit.
Negara melalui BPK sudah menyampaikan temuan. KLHK menjawab formal. Daerah beralasan fiskal tidak cukup!
Sementara itu, ujarnya, setiap musim hujan, masyarakat hanya mendengar peringatan yang sama: “curah tinggi, waspada.” Realitanya, Sumatera sedang menunggu tanggalnya sendiri. Dan 2025 adalah tanggal itu.
Dikatakannya, 10 tahun terakhir BMKG telah mengintegrasikan radar cuaca, satelit Himawari, dan INAWRN. Tetapi banyak daerah, terutama Aceh hingga Sumut, tidak punya sirene dan pengeras suara di desa-desa rawan longsor. Peringatan berhenti di layar smartphone, padahal warga rentan tidak punya internet.
BNPB sebenarnya memiliki pedoman evakuasi dan peta rawan. Namun 30% peta rawan banjir-longsor kabupaten tidak diperbarui sejak 2014. Itu temuan BPK 2015–2023. Dan ketika bencana datang, BMKG sudah memberi sinyal, tetapi mesin kebijakan tak bergerak. Terlihat teknologi berlari, tapi birokrasi berjalan kaki!
Kepemimpinan diuji
Iskandar Sitorus menyebut, respons Presiden Prabowo menarik untuk dicermati. Presiden hadir cepat di lapangan, memberi instruksi langsung, dan memobilisasi TNI dalam 24 jam. Namun hal kontras tampak di bawahnya:
1. Ada pembantu presiden yang telat bergerak, masih menunggu “data kumulatif”,
2. Ada kepala lembaga yang mengeluarkan pernyataan kontroversial seolah menyederhanakan skala bencana,
3. Ada kementerian teknis yang sibuk saling menyalahkan soal penggundulan DAS.
Sementara presiden turun langsung, sebagian pembantunya masih memakai kacamata lama, yakni yang penting rapi di laporan, bukan cepat di masyarakat. Ini celah kepemimpinan yang sangat terlihat publik!
Secara regulasi, syarat Bencana Nasional sudah terpenuhi jauh melewati ambang batas, karena:
- Korban meninggal > 100 orang, ini sudah terpenuhi 7–8 kali lipat,
- Pengungsi > 100.000, itu terpenuhi 32 kali lipat,
- Lintas provinsi, sudah terpenuhi,
- Kerugian > Rp1 triliun, malah sudah terpenuhi berlapis-lapis.
Namun ada satu bacaan politis–strategis yang mungkin tumbuh di benak Presiden Prabowo, ia tampaknya memilih “menunda”, sembari mengumpulkan basis hukum kuat, karena status Bencana Nasional akan membuka gerbang penyidikan multi-pintu terhadap:
1. Korporasi sawit, tambang, dan HTI,
2. Pemerintah daerah penerbit izin,
3. Kementerian/lembaga yang mengabaikan rekomendasi BPK,
4. Oknum aparatur yang menutup mata atas peringatan kerusakan DAS.
"Jika status “nasional” ditetapkan terlalu dini, korporasi bisa bersembunyi di balik dalih “bencana alam murni”. Bisnis perasuransian akan berperilaku menjadi tidak adil! Namun jika ditetapkan setelah bukti siap, hasilnya lebih mematikan, itu secara hukum," tegasnya.
Dalam dunia hukum lingkungan, ini disebut “strategic enforcement timing.” Dan presiden tampaknya sedang menerapkannya! Inilah saatnya pemerintah menggunakan senjata lengkap peraturan.
Saat ini, begitu status Bencana Nasional diputuskan, pemerintah bisa menjalankan mekanisme multi-door:
1. Polri menyidik pidana lingkungan sesuai pasal 98–99 UU 32/2009 jo pasal 109–113 terkait pencemaran dan perusakan,
2. Kejaksaan Agung menggugat perdata pemulihan lingkungan sesuai pasal 90 UU 32/2009 (strict liability) dengan gugatan ganti rugi Rp triliunan,
3. KPK menyidik korupsi perizinan dan TPPU sesuai pasal 12 UU Tipikor serta Pasal 3 dan 5 TPPU maupun alur fee perizinan sawit/tambang,
4. BPK membuktikan audit 20 tahun sesuai Pasal 8 UU BPK yang menyatakan LHP adalah alat bukti sah,
5. KLHK lakukan penegakan administratif berupa pencabutan izin, denda pemulihan dan pemakzulan perusahaan operator.
Dengan kombinasi ini, penyidikan bukan hanya mungkin, tapi wajib secara hukum.
"Apa yang harus dilakukan sekarang? Presiden Prabowo memiliki peluang emas untuk mencatat sejarah:
1. Sudah saatnya menetapkan Bencana Nasional. Ini bukan sekadar label. Ini penegasan bahwa negara berdiri bersama korban.
2. Bentuk Satgas Penegakan Hukum Bencana Sumatera beranggotakan: Polri, KPK, Kejaksaan, BPK, KLHK, PUPR, BIN, BNPB.
3. Gunakan data warga sebagai bukti awal berupa foto, citra drone, video longsor dan banjir bandang adalah petunjuk permulaan (KUHAP pasal 1).
4. Jejak 20 tahun audit harus jadi pijakan. Bencana ini bukan tiba-tiba. Ada jejak administrasi, jejak izin, dan jejak politisnya," jabar Iskandar.
Namun untuk diketahui, katanya, di depan Presiden hari ini ada dua pilihan:
1. Menangani bencana sebagai rutinitas administrasi, atau,
2. Menggunakan bencana ini sebagai momentum membersihkan Sumatera dari 20 tahun kejahatan lingkungan.
Jika memilih yang kedua, dan semua tanda menunjukkan itu yang sedang dipertimbangkan, maka penundaan status “nasional” bukan kelemahan, melainkan strategi!
Karena untuk sekali ini, negara tidak boleh lagi hanya memadamkan api. Negara harus memutus siapa yang menyalakan apinya!
Bencana Sumatera adalah tragedi, tetapi sekaligus juga peluang memperbaiki sejarah. Dan sejarah sedang menunggu apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah itu.
(HEN/RZD)