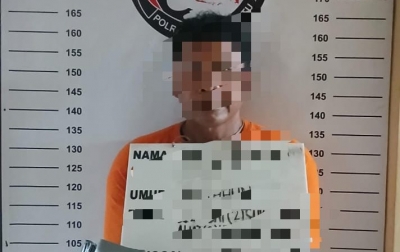Oleh: Dian Purba
Medan mendahului huru hara Mei 1998. Ratusan anak muda melewatkan akhir pekan mereka berdemonstrasi di kampus Universitas HKBP Nommensen (UHN) tanggal 2 Mei. Demonstrasi ini adalah gabungan dari beberapa kampus: UHN, UMSU, IKIP Medan, UISU, ITM, Amik Kesatria, UNIKA, UDA, USI XII. Tak ada tanda-tanda aksi ini akan berakhir ricuh sebelum semakin lama mereka berdemonstrasi semakin mereka tahu aksi mereka berusaha dibubarkan aparat keamanan. Massa yang awalnya menonton saja kemudian bergabung dengan mereka. Terjadilah barisan arak-arakan kemarahan. Mereka kemudian bentrok dengan petugas keamanan. Lalu aksi menjalar ke sekitar kampus. Mereka mengambil batu dan melempari kaca showroom mobil Timor di dekat kampus. Mereka juga mengamuk di KFC. Hotel Angkasa juga tak luput dari amukan. Mereka mendobrak pintu showroom itu dan menyeret satu mobil Mazda ke luar untuk kemudian dibakar setelah mobil itu digulingkan. Rumah-rumah dan perkantoran di Jalan Sutomo juga jadi sasaran amuk massa.
Dua hari kemudian, menjelang siang, giliran IKIP Medan berdemonstrasi di depan kampus mereka. Paling tidak sekitar 500 orang berlompat-lompat bernyanyi riang diiringi asap dari ban-ban bekas yang mereka bakar. Mereka berpawai. Polisi melihat itu berpotensi menimbulkan kerusuhan. Polisi kemudian menghentikan mereka. Kontak fisik pun terjadi. Batu-batu dan bom molotov dihadiahkan ke polisi. Kemudian mereka dihadang masuk ke dalam kampus. Tentu saja para mahasiswa itu tak mudah dihalau seperti domba digiring masuk kandang. Mereka tetap bernyanyi bergelora sembari menunjukkan diri tak sudi dipaksa masuk kampus. Kedua belah pihak memutuskan bernegosiasi. Tawaran mahasiswa: biarkan kami berdemonstrasi tanpa perlu ada aparat di sekitar mereka. Sementara polisi: berdemonstrasilah di dalam kampus saja. Negosiasi itu demikian alot sehingga kesepakatan bersama disetujui: mahasiswa berdemonstrasi di dalam kampus sementara polisi berjaga di luar kampus.
Menjelang malam, mahasiswa merasa situasi sudah kondusif sehingga beberapa dari mereka memutuskan keluar dari kampus. Rupa-rupanya polisi menghadang mereka di gerbang. Polisi membentak mereka dengan kata-kata kasar. Juga kata-kata cabul. Mereka disuruh berjalan berjingkrak beriringan sambil memegang bahu masing-masing. Kemudian, SN, salah seorang dari mahasiswa yang keluar itu, diremas payudaranya setelah kerudungnya direnggut paksa hingga terlepas. Dia juga dipeluk. Sebelum diremas, si polisi itu membuka resleting celananya dan menunjukkan kemaluannya ke SN dan teman-temannya seperti seakan-akan hendak melakukan pemerkosaan. Perlakuan bejat itu membuat SN pingsan. Kejadian itu pula yang menggugurkan kesepakatan kedua belah pihak.
Warga yang melihat aksi bejat itu geram. Segera terbentuk sekutu antara mereka dan mahasiswa. Malam itu juga mereka mendatangi pos polisi di Jalan Pancing. Mereka berusaha mencari polisi itu. Isu pelecehan seksual itu beredar begitu cepat sehingga warga semakin ramai ikut bergabung. Yang dicari tidak tersua. Mereka kemudian menghancurkan pos polisi tersebut. Mereka mengobrak-abriknya. Bahkan mereka membakar mobil truk dan sepeda motor yang terparkir di depan pos. Aksi itu berhenti setelah kota gelap gulita karena listrik sengaja dimatikan.
Inilah awal kerusuhan Mei di Medan. Hari-hari setelah itu adalah hari-hari amuk massa, hari-hari penjarahan, hari-hari kerusuhan. Yang cukup menarik, penjarahan dan kerusuhan terjadi di pinggiran kota. Di sekitar kampus IKIP Medan sendiri hampir semua jalan di sana terjadi perusakan toko-toko diiringi penjarahan. Aksara Plasa dirusak dan dijarah isinya. Di Pasar Tembung terjadi penjarahan toko-toko warga Tionghoa. Sebelum dijarah mereka dipaksa ke luar. Mereka tidak menyerang toko yang di depan gedung bertuliskan “Milik Pribumi”, yang memasang sajadah di depan toko, dan juga yang memasang bendera merah putih.
Di Simpang Limun di Jalan Sisingamangaraja juga terjadi kerusuhan. Kerumunan massa menumpuk ban dan kayu di jalan sebagai barikade. Mereka kemudian membakar barikade itu. Lalu mereka menjebol satu toko pakan, menjarah segala isinya, lalu menyiksa pemiliknya. Mereka juga merusak dan menjarah Medan Supermarket. Demikian juga di daerah Belawan. Di Titi Papan terjadi perusakan dan penjarahan dua buah toko. Mereka juga merusak dua unit kendaraan roda empat. Kita juga mesti mencatat peristiwa tanggal 8 Mei di Jalan Yos Sudarso, Simpang Sicanang, dan Kampung Kurnia P. Sicanang. Di pagi hari ratusan orang mengamuk dan mengharu biru kampung tempat pemukiman warga Tionghoa. Mereka menghujani kampung itu dengan batu. Di Martubung, Ali Herban, warga keturunan Tionghoa, mesti merelakan peternakan ayamnya habis dilahap si jago merah.
Tim gabungan pencari fakta yang dibentuk pemerintah menyelidiki kerusuhan Mei itu menulis, “Selain dipicu pelecehan seksual, seminggu sebelum terjadi kerusuhan di beberapa tempat seperti Kodya Medan, Kabupaten Simalungun dan Tebing Tinggi sudah disebarkan isu-isu akan munculnya kerusuhan. Bersama dengan itu teror baik melalui telepon, maupun orangnya didatangi langsung oleh beberapa pemuda yang bertampang preman. Beberapa informasi juga menyebutkan bahwa sebelum kejadian di Medan itu, beberapa toko sudah ditandai dengan cat pilok pada malam harinya. Toko-toko yang ada tandanya inilah yang kemudian dijarah dan dirusak massa saat kerusuhan.”
TGPF juga menyimpulkan, “Pola-pola kerusuhan yang terjadi di Medan dan sekitarnya ini tampaknya dapat dipakai sebagai suatu gambaran awal untuk melihat pola-pola kerusuhan di tempat lainnya. Jemma Purdey mengamini kesimpulan itu. Dalam penelitiannya tentang kekerasan anti-Tionghoa di Solo dan Medan, dia menampik pendapat yang mengatakan bahwa kekerasan si Solo dan Medan adalah peristiwa kekerasan yang bersifat lokal. Purdey menulis aksi kekerasan (terhadap Tionghoa) di Medan dan Solo tidak bisa dipisahkan dari aksi kekerasan-kekerasan serupa di kota lain di Indonesia. Purdey tiba di kesimpulan itu karena dia melihat ada satu persamaan di semua aksi kekerasan itu: aksi-aksi kekerasan itu tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah, dalam hal ini militer dan polisi.
Temuan Purdey segaris dengan temuan TGPF. Tim ini mengatakan terdapat orang-orang berbadan kekar dan tegap yang tidak canggung atau takut melakukan aksinya, yang tampak sudah sangat terlatih dengan gerakannya yang cepat dan sepertinya mengomando massa, yang anehnya mereka memegang senjata laras panjang M-16 dan pistol FN-45. Untuk kasus Medan, sesuai dengan temuan TGPF, kita harus menambahkan satu aktor lagi sebagai penggerak kerusuhan: pemuda setempat yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat sebagai preman.
Pertanyaan ini kemudian ingin saya ajukan: kenapa aksi penjarahan dan kerusuhan tidak terjadi di pusat kota Medan? Dengan melihat pola kerusuhan di beberapa tempat di Medan, saya berasumsi, para provokator tidak menemui aksi demonstrasi di pusat kota karena nyaris hampir tidak ada perguruan tinggi di sana. Para provokator itu membutuhkan aksi mahasiswa untuk memicu kerusuhan. Kita boleh menyebut Universitas Methodist Indonesia, kampus terbesar yang berada di pusat kota. Robert Tobing, rektor Universitas Methodist Indonesia saat itu mengatakan demonstrasi terjadi di kampus itu. Namun aksi itu tidak melebar karena rektor mengeluarkan kebijakan: bila demonstrasi berlangsung rusuh maka siapa pun yang ikut berdemonstrasi akan dipecat.
Pertanyaan yang masih tersisa: Siapakah mereka yang mengecat toko-toko di malam hari itu yang di keesokan harinya massa sudah sangat terbantu menemukan sasaran amukan? Dan tentu saja yang paling utama: bagaimana negara mempertanggungjawabkan tindakan aparatnya, yang oleh TGPF disebut provokator, kepada para korban dan seperti apa pertanggungjawaban kepada martabat manusia dan juga kepada perjalanan sejarah Indonesia? ***
Penulis, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada