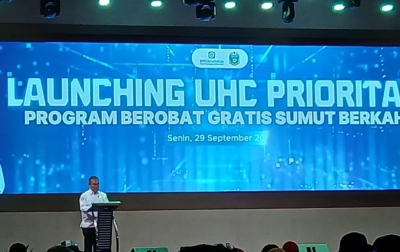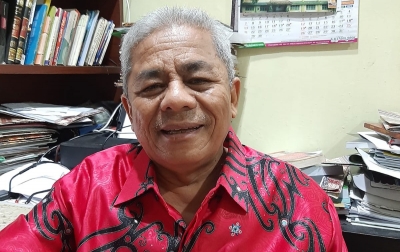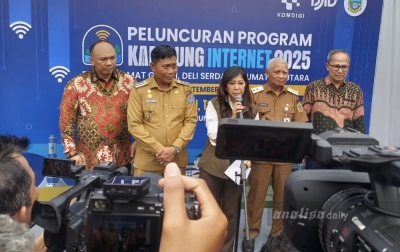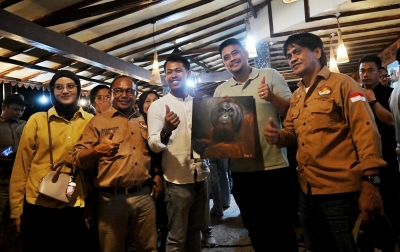Oleh: Korrie Layun Rampan. Penulis mengenal nama Marah Rusli pada usia 11 tahun, saat baru duduk di bangku kelas I SMP. Ketika itu penulis baru pindah dari ibu kota kecamatan ke ibu kota provinsi, untuk melanjutkan sekolah, karena waktu itu SMP hanya ada di ibu kota provinsi. Jarak antara ibu kota kecamatan ke ibu kota provinsi sekitar 525 kilomter perjalanan sungai.
Sepulang sekolah penulis blusukan ke pasar untuk mencari beras dan ikan asin. Karena tinggal sendiri di rumah kosong, harus mampu memasak sendiri, termasuk memasak lauk-pauknya. Karena baru beberapa kali masuk ke pasar itu, penulis tersesat di sebuah lorong. Ternyata di ujung lorong itu terdapat sebuah kios penyewaan buku.
Penulis melihat-lihat buku-buku yang dipajang. Ada satu buku yang menarik. Sampulnya tebal, ilustrasi sampulnya sangat kuno, tapi memikat. Ukuran bukunya lebar dengan huruf-huruf yang besar. Di sampul itu tertulis judulnya Sitti Nurbaya (dengan t dua huruf), entah cetakan yang keberapa. Penulis bertanya ingin membeli.
“Buku itu disewakan,” kata pemilik kios sewaan itu.
“Kamu punya kartu sewaan di sini?” tanyanya.
“Belum,” kataku.
“Kamu anak baru?” tanyanya.
“Sepertinya aku melihat kamu murid kelas I di SMP. Aku kelas II,” katanya menerangkan. Aku membenarkan.
“Karena kamu adik kelasku, bisa saja aku jual buku Sitti Nurbaya itu,” katanya sambil menyebutkan besaran harganya.
Aku pulang ke rumah kosong tanpa beras dan ikan asin, tapi dengan mengepit buku novel Sitti Nurbaya.
Hatiku terlonjak-lonjak gembira. Maklum selama empat tahun di SD di kecamatan, tak ada bacaan (jarak ibu kota kecamatan dengan ibu kota provinsi lebih 500 km). Meskipun lulus dengan nilai tertinggi dari SD, masuk SMP di kota seperti rusa masuk kampung. Terasa tololnya luar biasa. Apalagi halnya dengan bacaan fiksi.
Siapakah Marah Rusli?
Sastrawan ini lahir di Padang, Sumatera Barat, 7 Agustus 1889. Lulus sebagai dokter hewan pada usia 26 tahun. Pada usia 32 tahun terbit novelnya Siti Nurbaya. Mungkin pengaruh novel Charles Dickens Gadis yang Malang yang diterjemahkannya (atau pengaruh novel lainnya). Novel Siti Nurbaya menunjukkan bentuk sastra novel yang sesungguhnya, sebagaimana novel-novel yang terbit di Barat. Dia telah meninggalkan bentuk sastra tradisional bersifat istana sentris. Bersama dengan novelis Merari Siregar (yang menulis novel Azab dan Sengsara), Marah Rusli memperlihatkan sastra novel baru yang tidak lagi menggunakan tokoh dewa-dewi, para pangeran, dan putri raja. Siti Nurbaya menggunakan latar dan tokoh yang realis, cerita tidak lagi berakhir sebagai sebuah dongeng.
Siti Nurbaya memperlihatkan beberapa hal penting menjadi ciri sebagai novel besar. Pertama berhubungan dengan persoalan adat. Marah Rusli menentang adat kawin paksa. Dia berbeda dari novelis sezamannya seperti Nur Sutan Iskandar, A. Datuk Pamuntjak NS, Aman Datuk Madjoindo dan lain-lain yang masih memberi toleransi terhadap kawin paksa. Marah Rusli justru menggunakan haknya sebagai penentu nasib sendiri, bukan hanya di dalam novel, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Dia menikah saat sebelum lulus sebagai dokter hewan. Membawa istrinya pulang ke kampung. Sebagai turunan bangsawan, Marah Rusli dianggap telah melanggar adat.
Di dalam Siti Nurbaya terdapat pemikiran niaga yang justru dalam fiksi-fiksi selanjutnya kurang mendapat garapan serius. Dalam novel ini persoalan konglomerasi yang dilandasi pemikiran entrepreneur diberi ruang yang luas. Meskipun corak niaga itu masih tradisional, namun ide-ide dalam bidang perdagangan memberi arti penting di dalam kehadiran novel ini.
Siti Nurbaya memperlihatkan ide-ide kemerdekaan dengan menampilkan sikap dan sifat kepahlawanan. Sebagai tokoh antagonis, Datuk Meringgih menyimpan unggun cita-cita merdeka dengan jiwa kewirawanan yang mengepulkan api perlawanan.
Dalam novel ini unsur kerja ditekankan sebagai sumber keberhasilan hidup. Itu sebabnya penulis menentang kaum ningrat yang hanya berjudi dan menyambung ayam -memelihara klangenan-. Di samping itu, kaum muda harus diberi peran berdikari dan menantang, termasuk dalam hal pemilihan jodoh.
Dalam novel lainnya, La Hami (1952) Marah Rusli mengajukan pemikiran tentang masa lampau yang tak pernah mati. Masa lampau adalah dataran perjalanan. Dijalani di masa kini dan kemudiannya ditelusuri di masa depan. Dalam hal memaknai sejarah, masa lampau adalah wujud pelajaran penting untuk tidak terjatuh ke dalam ke salahan yang sama di masa depan.
Novel lainnya, Anak dan Kemenakan (1956), membicarakan akar adat dan budaya Minang yang menekankan kedudukan anak sebagai tanggung jawab paman. Sang Ayah tidak bertanggung jawab terhadap anak sendiri. Dia bertanggung jawab terhadap kemenakan. Itu sebabnya orang jemputan tidak perlu khawatir akan keselamatan dan keberhasilan anaknya, meskipun dia memiliki anak dalam jumlah yang banyak. Unsur kedudukkan anak dan kemanakan ini merupakan tema utama novel ini, membuat persoalan adat menjadi sangat jelas.
Karya terakhir Marah Rusli, Memang Jodoh (2013). Karya ini selesai ditulis tahun 1961, tujuh tahun sebelum ia meninggal dunia, dan penerbitannya baru terjadi 91 tahun kemudian setelah penerbitan Siti Nurbaya. Karya ini merupakan fenomena tersendiri bagi Marah Rusli sebagai novelis awal dalam sastra Indonesia. Ternyata Marah Ruli merupakan sastrawan bernapas panjang dengan penggelontoran ide-ide besar. Dalam catatan Dr. J. S. Badudu, Marah Rusli mengalami konflik keluarga, karena dipaksa menikah lagi, meskipun dia sudah beristri. Konflik adat inilah yang menjadikan dirinya sebagai sastrawan, karena dia yakin melalui tulisan ide-ide perlawanannya dapat lebih mudah tersebar dan para pembacanya akan lebih gampang memahami sikapnya.
Memang Jodoh memperlihatkan pertalian dan persambungan pemikiran Marah Rusli dalam bentuk dan tema. Secara tematik, Memang Jodoh menunjukkan pentingnya adat budaya di dalam kehidupan manusia. Akan tetapi tujuan adat adalah menjadikan masyarakatnya maslahat, seingga mampu melahirkan kemaslahatan di dalam kehidupan.
Secara tematik, Marah Rusli lebih tegas dibandingkan Abdul Muis maupun Hamka. Abdul Muis dalam Salah Asuhan memutuskan hubungan Hanafi dengan Corrie dalam bentuk perceraian. Hamka dalam Tenggelamnya Kapal van der Wijck mematikan tokohnya agar tidak terjadi perkawinan antara Hayati dengan Zainuddin.
Dalam wujud yang demikian, kedua novelis ini masih ragu-ragu dan takut untuk melawan adat. Ada ketidaktegasan dalam hal perlawanan mereka, sehingga tokoh-tokoh ini dibiarkan menjalani hidup (dan bahkan mati) di dalam kekalahan mereka untuk membangun cinta di dalam perkawinan. Dalam hubungan ini, Nur Sutan Iskandar lebih tegas, karena dia secara konsekuen berpihak kepada adat dan tradisi seperti yang ditulisnya dalam novel Salah Pilih.
Sebagaimana dikatakan Sapardi Djoko Damono, novel semiautobiografi Memang Jodoh, sangat penting untuk memahami berbagai isu sosial. Menjadi latar karya sastrawan Angkatan Balai Pustaka, berasal dari etnik Minangkabau di Sumatera Barat. Novel-novel Wisran Hadi, Darman Moenir, Gus TF Sakai yang ditulis di zaman kini membutuhkan pintu masuk untuk dapat memahaminya secara lebih mendalam, holistik dan komprehensif.
Dalam hubungan penerbitan, Memang Jodoh baru dapat dibaca peminat sastra, hampir seabad setelah penerbitan Siti Nurbaya. Penulis teringat, banyak sastrawan kita yang sudah tiada dengan meninggalkan karya-karya yang belum diterbitkan, di antaranya sastrawan Djumri Obeng dan Harijadi S. Hartowardojo.
Djumri meninggalkan beberapa naskah cerpen, novelet dan novel. Beberapa naskah noveletnya pernah dimuat Majalah Sarinah -waktu itu penulis ini menjadi redakturnya- dengan menggunakan beberapa nama samaran. Karya-karya itu tetap terpendam di majalah itu, hingga dewasa ini. Harijadi meninggalkan naskah novel Gelombang di Jakarta. Menurut Ajip Rosidi naskah tersebut hanya tinggal editing kecil, tetapi kapankah novel Gelombang di Jakarta itu muncul seperti Memang Jodoh?