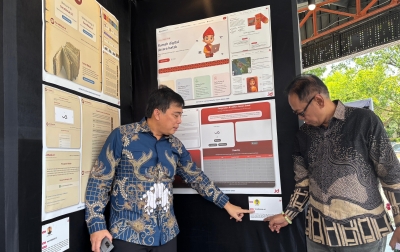Oleh: J Anto
SEJAK 1980-an ruang ekspresi Ronggeng Deli makin menyempit, digerus arus pembangunan yang abai terhadap hak hidup kesenian rakyat. Ronggeng Deli pun bak mati suri. Kalaupun ada pentas, mereka tak ubahnya seperti pentas klangenan. Sejumlah seniman ronggeng tanah Deli dan budayawan diaspora di Jakarta sejak 2015 berupaya melakukan revitalisasi. Akankah Ronggeng Deli hidup kembali menjadi kesenian rakyat Melayu?
Tahun 70-an air Sungai Deli yang mengalir di sebelah Jalan Raden Saleh Medan dekat gedung Walikota Medan masih terlihat cukup jernih. Ke sanalah jelang sore, Sukarnoto, remaja usia 13 tahun bersama remaja sepantarannya menceburkan tubuh ke sungai itu. Sembari bercanda ria, mereka berenang dan bermain-main air. Rumah Sukarnoto memang tak jauh dari Sungai Deli.
Bersama orangtuanya, ia tinggal di Asrama PT KAI Jalan Jawa. Ayah Sukarnoto, seorang pegawai Jawatan Kereta Api Indonesia Medan.
Saat duduk di bantaran sungai untuk mengeringkan badan, tak jauh dari situ, sepasang mata Sukarnoto melihat beberapa perempuan dan laki-laki tengah menari dan saling melontarkan pantun. Seperti tersihir, ia lalu mendekat dan menonton para penari dan pemantun, dalam ingatannya sudah tua-tua. Ia betah melihat pertunjukan itu berjam-jam. Saat teman-temannya mengajak pulang, ia bergeming.
Pengalaman melihat pertunjukan Ronggeng Deli di pinggir Sungai Deli itu sangat membekas di hatinya. Sejak itu, hampir tiap sore ia jadi sering menonton pertunjukan ronggeng, sampai kelompok kesenian rakyat itu tergusur karena ruang pentas mereka digusur atas nama pembangunan kota.
“Sejak itu, saya jatuh cinta dengan Ronggeng Deli,” tuturnya saat dijumpai di kantin Kompleks Taman Budaya Sumatera Utara, Kamis (1/12) sore. Bau aspal jalan basah masih tercium menyengat, hujan baru berhenti mengguyur Medan. Ditemani segelas kopi hitam dan senda gurau sejumlah seniman yang duduk di bangku terpisah, Sukarnoto (52) alias Retno Ayumi itu lalu melanjutkan kisah perjumpaannya dengan kesenian rakyat Melayu yang ada sejak abad 17 – 18 itu.
Ronggeng Kampung
“Saat saya berusia 16 tahun, saya lalu belajar tari di Lembaga Studi Tari Patria Medan. Namun sejak itu saya sadar bahwa tari-tarian Melayu itu bersumber dari Ronggeng Deli,” ujar Retno Ayumi. Lalu saat berusia 18 tahun, ia bergabung dengan grup Ronggeng Deli yang mengadakan pentas dari kampung ke kampung seperti di Percut Sei Tuan, Sunggal, Deli Serdang dan Tanjung Balai.
Lebih 30 tahun ia menjadi peronggeng. Retno Ayumi dikenal sebagai salah satu penari dan pemantun, sejak 2015 aktif terlibat dalam Komunitas Ronggeng Deli.
“Kami bukan seperti ayam yang kehilangan lesung/Baru bertelur sebutir ributnya sekampung/Kami hanya menjalankan amanah orang-orang tua di kampung/Kalaulah nanti Pak Menteri mau berkunjung/Apalagi kalau ‘dah mau bergabung/Itu tandanya ada adat resam yang dijunjung/Oleh sebab itu kami lantunkanlah lagu Tanjung Katung/Dari Ronggeng Deli yang nyaris hanyut terapung."
Itulah pantun yang dilantunkan Retno Ayumi pada saat bersama Komunitas Ronggeng Deli manggung di depan Anies Baswedan pada Perayaan dan Penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia di Gedung Kesenian Jakarta, 20 Oktober 2015 lalu.
Pantun Kekuatan Ronggeng
Menurut Retno Ayumi, pantun adalah unsur sastra sekaligus kekuatan utama Ronggeng Deli, di samping seni tari dan seni musik. Yang khas, dalam pertunjukan Ronggeng Deli, pantun tidak hanya dilantunkan sesama peronggeng, tapi juga penonton. Itu artinya penonton terlibat aktif selama pertunjukkan.
“Ini berbeda dengan ronggeng di Jawa atau tempat lain, objek penonton bukan peronggeng tapi pantunnya,” tambahnya. Pantun menjadi medium seniman dan rakyat dalam mengungkap seluruh segi kehidupan rakyat Melayu. Semacam katarsis untuk menjaga daya hidup rakyat.
Isi pantunnya beragam, mulai dari curahan hati terhadap pacar, orangtua, situasi sosial, ekonomi maupun politik. Bisa juga harapan atau suasana suka ria.
Tentu saja bukan hal mudah membuat pantun secara spontan. Apalagi peronggeng juga harus menari mengikuti irama musik dan menyanyi. Itu sebabnya Rizaldi Siagian, etnomusikologi dari USU menyebut Ronggeng Deli sebagai kesenian cerdas.
“Selain itu, isi pantun juga harus kontekstual dengan ruang Ronggeng Deli itu bermain. Kalau bermain di tengah komunitas orang Yogyakarta, pantun yang dilantunkan juga harus kontekstual dengan masyarakat Yogya,” imbuh Retno Ayumi. Dalam khazanah tembang Ronggeng Deli, dikenal juga lagu ‘Mak Inang China’ yang sudah berumur ratusan tahun. Itu artinya ada juga pantun Melayu berlogat China.
Ronggeng Deli memang kesenian hibrid, kesenian multikultural. Tak hanya dalam pantun, tapi juga alat musik terjadi akulturasi, misalnya penggunaan biola dan akordion dari Portugis. Atau gendang yang masih menimbulkan silang pendapat, apakah dari Arab atau India.
Terlepas dari saling bepengaruh budaya yang merupakan sesuatu yang tak terelakkan dalam sejarah perjumpaan peradaban antarumat manusia, menurut Kepala Anjungan Sumut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Tatan Daniel, Ronggeng Deli adalah sebuah kesenian tradisional yang sesungguhnya menjadi identitas dan akar budaya masyarakat Melayu.
“Ronggeng Melayu, penting untuk dirawat agar mata air peradaban orang Melayu tidak kering. Akan sama halnya, etnis Batak, akan kehilangan kebatakannya jika bahasa, ulos, atau tortornya tidak lagi dipakai,” katanya.
Namun ziarah batin kurang lebih dua pekan yang dilakukan Rizaldi Siagian, Retno Ayumi, Tatan Daniel, dan Prof Mohamad Anis (dari Universitas Malaya), pada 2014 dari Pangkalan Brandan sampai Perbaungan dan Medan, justru menemukan “air mata” bukan “mata air” peradaban Melayu.
“Hampir tidak ada lagi yang memainkan seni Ronggeng Melayu. Para senimannya, satu-satu meninggal tanpa tercatat dan terwariskan pengetahuan dan keahlian mereka yang dapat disebut sebagai 'maestro' itu,” kata Tatan Daniel.
Pemerintah juga tak pernah peduli. Situasi itu berkelindan dengan revolusi perangkat musik dan teknologi, televisi, arus budaya luar, hegemoni rezim yang merontokkan tradisi dan keseniannya, serta pendidikan yang tidak membuka ruang bagi pengajaran seni tradisional.
Saat ruang berekspresi makin sempit, sejumlah seniman ronggeng bertahan dengan cara sendiri. Ada yang pasrah menungu pesanan. Ada yang mencari ruang-ruang baru ke pinggiran Kota Medan, bahkan ke luar Medan. Ada juga yang mengekspresikan di jalanan. Mengembara dari satu ruang ke ruang lain.
Jerembab Lumpur
Tak sadar, kisah lama pun terulang, ada kelompok ronggeng terkontaminasi hiburan kejelataan. Mereka lalu sempat menjadi bagian dari sebuah ruang hiburan yang sarat minuman keras dan praktik prostisusi. Itulah realitas yang ada dan harus diterima. Stigma pun berkembang liar. Ronggeng Deli diidentikkan dengan porno aksi dan minuman keras.
“Ronggeng Deli terjerambab di lumpur itu, tapi apakah harus kita angkat dengan lumpur-lumpurnya? Tidak, yang harus kita angkat itu rohnya, keseniannya yang cerdas. Siapa yang bisa menari mengikuti irama musik sambut pantun secara spontan? Hanya seniman yang lahir dari tradisi ronggeng yang bisa,” tutur Retno Ayumi.
Prihatin dengan nasib Ronggeng Deli, sejumlah seniman Tanah Deli seperti Retno Ayumi, Mak Yal, Zulkifli, Jamal, Aisyah dan para diaspora seperti Rizaldi Siagian, Tatan Daniel, Dede Rasyid, Herman Lunk dan Rosianna, pada 2015 menginisiasi revitalisasi Ronggeng Deli. Lahirlah Komunitas Ronggeng Deli. Kelompok ronggeng ini rutin tampil mengisi acara di Anjungan Sumut TMII Jakarta.
Selain itu mereka juga pernah tampil di rumah budaya Tembi Yogyakarta, Balai Pengkajian Melayu Yogyakarta, Kuningan, Jawa Barat dan berbagai ajang lain di Jakarta
Di Medan sendiri, Ronggeng Deli masih berpendar. Walaupun sifatnya masih pesanan. Misalnya karena ada acara pemerintahan, ada acara pesta pernikahan atau untuk kepentingan atraksi wisata. Retno Ayumi tidak antipati dengan kecenderungan itu.
Sebagai peronggeng, ia sadar bahwa ruang untuk berekspresi para ronggeng saat ini adalah ruang hasil dari sistem yang menghimpit mereka. Jadi sekalipun ruang itu terbatas, tetap dimanfaatkan oleh para seniman ronggeng. Ia hanya tak rela jika hikayat para pemantun di Tanah Deli kelak hanya tinggal nama. Jika keterampilan berpantun makin pudar dan tak lagi ada generasi muda yang meneruskan.
Karena itu, sekali lagi, ia tak khawatir-khawatir amat dengan seniman ronggeng yang sering tampil di acara-acara pemerintahan. “Tentu para seniman akan bernegosiasi dengan ekspresi masing-masing, tapi sampai hari ini saya percaya para seniman ronggeng tidak tunduk kepada kepentingan pihak pemesan,” katanya.
Duh, Ronggeng Deli….