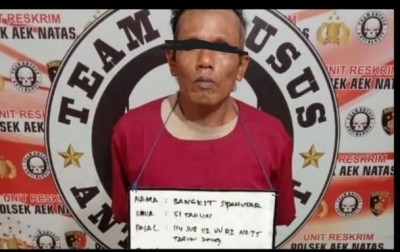Oleh: Wayudin, SE, MM.
Topik mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual,dan Transgender) menghangat di tengah masyarakat akhir-akhir ini. Mulai dari kasus pembunuhan di sebuah cafe yang tengah ramai dibicarakan dengan dugaan adanya motif asmara sejenis, bantuan UNDP untuk mendukung LGBT di sejumlah negara termasuk Indonesia, sampai pada heboh di masyarakat karena sebuah aplikasi pesan dari Korea Selatan yang jamak digunakan oleh masyarakat, menawarkan stiker yang ‘berbau’ homoseksual.
Kaum LGBT yang biasanya dilambangkan dengan pelangi sebenarnya bukanlah kaum baru di Indonesia, akan tetapi mungkin sepak terjang mereka di tengah masyarakat masih sangat terbatas karena adanya stigma negatif yang terlanjur melekat dalam benak masyarakat terhadap mereka. Meskipun banyak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, namun beberapa orang dari kaum ini mampu menginspirasi masyarakat karena sumbangsih dan prestasi yang berhasil mereka torehkan. Sebut saja Dorce Gamalama yang lebih dikenal dengan sebutan Bunda Dorce. Terlahir sebagai seorang laki-laki dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi, namun artis serba bisa ini akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi ganti kelamin di Surabaya karena ia merasa terperangkap dalam tubuh seorang laki-laki. Tindakan Bunda Dorce dianggap ‘sangat berani’ pada waktu itu tentu mendapatkan tentangan dari banyak pihak, namun banyak pula diberitakan di media massa sehingga Bunda Dorce semakin dikenal luas oleh masyarakat.
Akan tetapi tentu saja tidak semua kaum LGBT memiliki keberanian sebesar Bunda Dorce untuk mengekspose diri mereka di masyarakat karena mempertimbangkan resiko berat yang akan mereka hadapi. Sebut saja cemoohan dari masyarakat, dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat, bahkan tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat. Sanksi-sanksi sosial inilah yang menjadi pertimbangan dari kaum minoritas ini untuk memutuskan apakah akan ‘mendeklarasikan’ identitas mereka ke masyarakat atau memilih jalan lain yaitu gerakan bawah tanah.
Berbeda dengan transgender yang mungkin akan langsung terlihat perubahannya dalam masyarakat, dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, kaum lesbian dan gay, cenderung samar-samar dalam masyarakat, meskipun ada beberapa yang tidak malu untuk menunjukkan jati dirinya. Seringkali kita menjumpai adanya laki-laki yang ‘kemayu’ atau perempuan yang ‘tomboy’ luar biasa, hal-hal seperti itu bisa jadi merupakan cara mereka untuk menunjukkan identitas mereka yang tidak biasa, namun tentu saja hal tersebut tidak dapat digeneralisasikan karena saat ini banyak juga laki-laki yang berpenampilan gagah ternyata memiliki pasangan yang tak kalah tampan.
Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran tentu menentang adanya praktik-praktik LGBT di Indonesia. Akan tetapi, tanpa kita sadari kaum LGBT sebenarnya bisa saja berada di sekitar kita. Mungkin mereka adalah teman, saudara, atau kerabat kita yang berprofesi sebagai dokter, guru, penata rias, atau bahkan pelatih kebugaran. Ditinjau dari segi agama, tidak ada satu agamapun yang mengamini praktik LGBT karena semua agama meyakini bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak diantaranya, serta laki-laki merupakan pasangan yang sepadan bagi perempuan, bukan bagi sesamanya laki-laki.
Dari segi ilmu sosial, LGBT dipandang sebagai penyimpangan sosial karena praktik LGBT menyimpang dari norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. Akan tetapi dengan kondisi masyarakat yang dinamis, norma-norma yang berlaku tentu saja dapat mengalami pergeseran nilai dimana dulunya menentang menjadi mengizinkan praktik LGBT seperti yang terlihat dari disahkannya pernikahan sejenis di beberapa negara di dunia seperti Belanda.
Lain di Belanda, lain pula di Indonesia. UU Perkawinan di Indonesia sampai saat ini belum mengakomodasi pernikahan sesama jenis. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia seringkali menunjukkan reaksi yang berlebihan ketika dihadapkan pada isu-isu yang berkaitan dengan LGBT. Di satu sisi, kekhawatiran masyarakat bahwa LGBT akan merusak tatanan masyarakat dapat dimaklumi, tapi disisi yang lain, kekhawatiran masyarakat malah menjurus pada ketakutan yang berlebihan, alias homophobia. Ketakutan terhadap LGBT lebih dikarenakan informasi yang beredar dalam masyarakat simpang siur sehingga menimbulkan salah persepsi, misalnya saja berita di Harian Analisa pada hari Minggu (14/ 2) dengan judul LGBT Dapat Menular. Kesan yang muncul ketika membaca judul tersebut seolah-olah LGBT adalah sebuah penyakit mematikan yang dapat menular ( misalnya melalui sentuhan) pada orang-orang yang berada di dekat penderitanya sebagaimana penyakit berbahaya lainnya. Padahal maksud dari berita tersebut adalah perilaku LGBT dapat ‘dipelajari’ oleh manusia yang tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan kaum LGBT.
Kesalahan-kesalahan persepsi demikianlah yang mendorong opini-opini liar bergulir dalam masyarakat dan melahirkan stigma-stigma negatif terhadap kaum LGBT sehingga seolah-olah kaum LGBT harus dihindari karena mengidap kelainan yang menjijikkan dan menular. Dengan adanya stigma-stigma negatif yang melekat, kaum LGBT menjadi minoritas yang sering mengalami marginalisasi dalam masyarakat sehingga mengurangi hak-hak mereka sebagai warga negara dan sebagai manusia.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran kaum LGBT akan hak-hak mereka dalam hukum dan pengadilan, maka United Nations Developments Programme (UNDP) mengucurkan bantuan sebesar US$8 juta kepada Indonesia, Tiongkok, Filipina, dan Thailand yang kemudian disalahartikan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan propaganda UNDP untuk mempromosikan LGBT di Indonesia. Penekanan dari bantuan ini adalah kaum LGBT memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam hukum, bukan untuk melegalkan praktik LGBT di Indonesia.
Kesalahan lain yang sering terjadi adalah masyarakat sering ‘memaksa’ untuk menyembuhkan kaum LGBT karena LGBT dipandang sebagai sebuah penyakit. Saat ini memang tersedia terapi untuk mengembalikan kaum LGBT ke ‘jalan yang benar’, namun masalah kembali atau tidaknya sangat tergantung pada masing-masing individu. Misalnya saja dalam kasus Bunda Dorce yang merasa memiliki jiwa wanita namun secara fisik laki-laki, terapi psikologi mungkin hanya akan berdampak pada pergolakan jiwa yang berkepanjangan jika beliau tetap dipaksakan untuk menerima fisik alaminya yang berupa laki-laki. Demikian juga dengan terapi yang diberikan kepada kaum lesbian dan gay, tidak dapat menjamin mereka akan kembali menjadi heteroseksual, akan tetapi lebih ditujukan untuk mengubah kecenderungan orientasi seksual mereka, dari yang cenderung menyukai sesama, menjadi cenderung menyukai lawan jenisnya.
Masyarakat yang bereaksi keras terhadap kaum LGBT malah menjadikan mereka semakin tertutup dan semakin ekslusif sehingga menimbulkan bahaya yang lain, sebut saja penyebaran HIV/ AIDS yang meluas, bukan hanya di kalangan sesama LGBT tetapi juga di kalangan masyarakat luas karena tidak jarang kaum LGBT memiliki pasangan lawan jenis alias menikah untuk menutupi kedoknya. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa sebuah isu kontroversial justru menjadi semakin populer ketika hangat dibicarakan dalam masyarakat, misalnya saja ketika muncul berita pencekalan goyang ngebornya Inul Daratista yang malah semakin melejitkan nama pemiliknya karena masyarakat semakin penasaran bagaimana hebohnya goyangan tersebut sehingga pantas untuk dicekal, demikian juga dengan isu-isu menyangkut kaum LGBT. Bukan tidak mungkin semakin keras reaksi masyarakat malah membuat LGBT semakin eksis di masyarakat. Bagaimanapun juga, kaum LGBT adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak harus dihindari, melainkan harus dirangkul kembali sebagaimana saudara-saudara kita yang terjerumus dalam paham-paham radikal sehingga dapat bersama-sama membangun bangsa. ***
Penulis adalah Guru SMP Methodist-3, Dosen UNPRI, Medan.