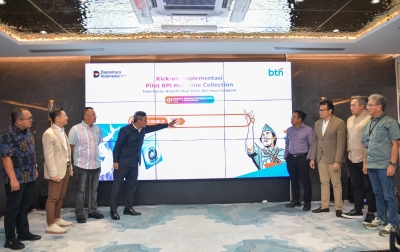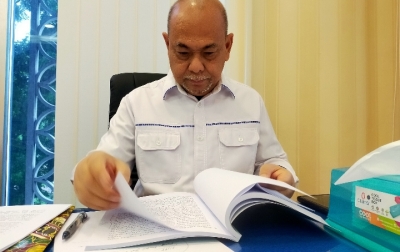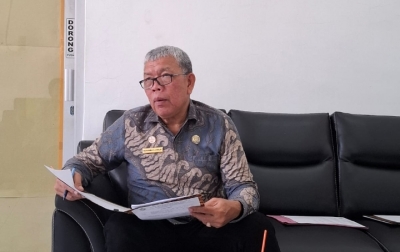Oleh: Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn
Di Indonesia saat ini, mungkin hanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA), yang masih eksis sebagai undang-undang pokok atau undang-undang induk atau hukum payung (umbrella act).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebenarnya tidak mengenal adanya undang-undang pokok, dalam arti undang-undang yang merupakan induk atau hukum payung (umbrella act) dari undang-undang yang lain, karena semua undang-undang di Negara Republik Indonesia mempunyai hirarki yang sama dan semua dibentuk oleh Presiden (eksekutif) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (legislatif). Oleh karenanya semua undang-undang kedudukannya sama, tidak lebih tinggi dari yang lain, dengan demikian satu sama lain tidak dapat saling memerintahkan untuk mengatur dengan undang-undang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga tidak mengenal adanya ketentuan mengenai hukum payung (umbrella act) atau undang-undang yang bersifat hukum payung (umbrella act) dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga tidak terlihat adanya pembedaan antara undang-undang sebagai hukum payung dan undang-undang yang bersifat organik.
Kondisi tersebut membawa konsekuensi hukum, yakni pembuatan undang-undang yang bersifat organik (Undang-Undang Sektoral Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam atau disingkat UU Sektoral PSDA.
Yang dimaksud dengan UU Sektoral PSDA antara lain ialah undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan mineral dan batubara, undang-undang minyak dan gas bumi, undang-undang sumber daya air, undang-undang perikanan, undang-undang penataan ruang, undang-undang lingkungan hidup, dan lain-lain), tidak lagi harus mengacu atau bertindak berdasarkan UUPA.
Padahal UUPA sejatinya dimaksudkan untuk menjadi hukum payung (umbrella act) yang mengandung amanat pembuatan beberapa undang-undang (UU Sektoral PSDA) sebagai pedoman pelaksanaan UUPA.
Di sisi lain, UUPA sebagai undang-undang pokok yang semula diharapkan menjadi hukum payung (umbrella act) bagi UU Sektoral PSDA ternyata mengalami kegagalan.
Salah satu penyebab utama kegagalan UUPA sebagai undang-undang pokok atau sebagai undang-undang payung adalah karena materi UUPA kurang lengkap, UUPA lebih lengkap mengatur masalah pertanahan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa UUPA lebih tepat disebut sebagai ‘Undang-Undang Pertanahan’ daripada undang-undang yang mengatur secara komprehensif dan proporsional tentang agraria.
Menurut UUPA pengertian agraria meliputi bumi (tanah adalah bagian permukaan bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).
Mestinya UUPA juga mengatur secara lengkap tentang kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, sumber daya air, perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, dan lain-lain, namun faktanya tidak demikian, UUPA lebih dominan mengatur sektor pertanahan, dari 67 pasal di dalam UUPA, terdapat 53 pasal yang mengatur sektor pertanahan, hanya ada 4 pasal yang mengatur hal-hal di luar sektor pertanahan.
Lahirlah berbagai undang-undang sektoral
Kekuranglengkapan UUPA itu tidak segera dibenahi akibatnya lahirlah berbagai undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 11: Tahun 1974 tentang Pengairan dan berbagai undang-undang lain yang terbit kemudian yang dalam kenyataannya tidak satupun undang-undang sektoral tersebut merujuk pada UUPA, melainkan masing-masing langsung merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Era bertumbuhkembangnya undang-undang sektoral, menandai didegradasinya UUPA yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi lex generalis bagi pengaturan sumber daya alam menjadi sederajat dengan undang-undang sektoral lainnya dan dengan demikian menjadikan UUPA sebagai lex specialis yang hanya mengatur bidang pertanahan.
Sejatinya UUPA dimaksudkan sebagai undang-undang yang akan menjadi landasan pengaturan berbagai undang-undang terkait dengan agraria (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Namun, dalam perjalanan waktu, terutama pada awal tahun 1970-an, ketika pembangunan ekonomi negara kita memerlukan modal yang cukup besar, terjadi perlombaan untuk menyusun undang-undang sektoral.
Diawali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan (direvisi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), tanpa mengacu kepada prinsip-prinsip yang digariskan oleh UUPA, semua undang-undang sektoral secara langsung merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukumnya.
Sejak terbitnya berbagai undang-undang sektoral itu, kedudukan UUPA sebagai induk regulasi pengelolaan sumber daya alam didegradasi menjadi undang-undang sektoral yang mengatur tentang pertanahan.***
Penulis adalah Notaris/PPAT dan Dosen Program Studi Magister Kenotariatan USU – Medan)