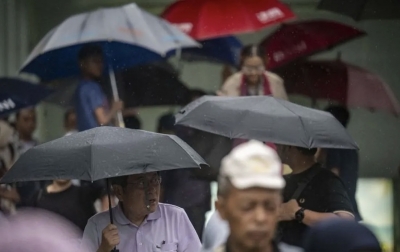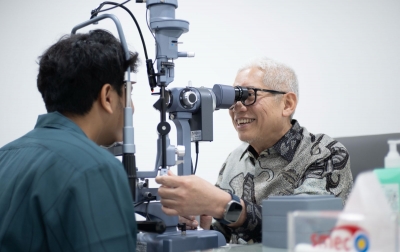Medan, (Analisa). Pencarian budaya dan identitas Kota Medan sebagai warisan Melayu sulit terbentuk. Beberapa faktornya, antara lain populasi orang Melayu yang minim dan enggannya melakukan konsolidasi budaya.
Kepala Pussis Unimed, Dr. phil. Ichwan Azhari, MS, menyampaikannya dalam Seminar Perubahan Sosial di Kota Medan dalam Perspektif Antropologi Kerja sama Antropologi Sosial Pascasarjana Unimed dan Prodi Antropologi FIS Unimed, di VIP Gedung Serbaguna Unimed belum lama ini.
"Dulunya, Kesultanan Deli memberi hak istimewa pada orang Melayu dan etnik non Melayu terserap dalam proses Melayunisasi secara setengah hati," ujarnya.
Namun, lanjutnya, institusi kesultanan tidak memperkuat budaya Melayu itu sendiri dan lebih menonjolkannya (budaya Melayu) sebagai aksesoris, sama seperti di Medan.
"Kreator budaya Melayu tidak muncul dari istana. Tidak ada kesenian, yang muncul, arsitek, karya sastra Melayu yang muncul di istana," ucapnya.
Padahal, lanjutnya, kesultanan ini merupakan satu dari empat (kesultanan) terkaya di Indonesia yang hanya ada di Sumatera Utara yakni Melayu Deli. "Melayu Deli mendapatkan kekayaan 'durian runtuh' dengan adanya penyewaan tanah dari kolonial. Namun, pada 1946, mendadak runtuh dalam tragedi sosial di Sumatera Timur. Institusi kesultanan musnah, elit Melayu banyak terbunuh, mengungsi, tersingkir, menarik diri, sejarah kultural menjadi lemah," paparnya.
Melayu hilang ketika istana musnah. "Itulah kelemahan orang Melayu. Meskipun, Melayu di pinggiran masih eksis dengan involusi budayanya. Di pinggiran juga masih bisa kita cari anyang, bubur pedas. Sementara, di sudut lain sudah tidak ada," katanya.
Konsolidasi budaya
Lalu, mulai muncul komunitas-komunitas Melayu di Medan. "Tapi dalam hal konsolidasi budaya, (orang Melayu) mengalami kesulitan. Sementara, Medan telah jadi kota migran yang dikuasai pedagang. Saat saya tanya, siapa Melayu, maka akan sedikit yang angkat tangan. Sedangkan, yang Batak, langsung banyak yang angkat tangan," tuturnya.
Karenanya, pencarian budaya dan identitas Kota Medan sebagai warisan Melayu saat ini sulit terbentuk. "Dalam politik modern, orang yang paling demokrasi, tidak nepotisme, adalah Melayu karena tidak ada keterpanggilan konsolidasi budaya itu. Belum lagi, Melayu sangat minoritas jumlahnya, berdasarkan statistik juga masih rendah. Sementara, pendatang masuk lewat 'pintu belakang'. Orang-orang pendatang yang datang malah mengesahkan diri sebagai orang 'Medan'. Dalam penelitian, skripsi, tesis dan lainnya, kondisi ini masih jarang ditelaah," jelasnya.
Dalam seminar ini, sejumlah guru besar turut menjadi pembicara, di antaranya Prof. Syafri Sairin, MA PhD (Guru Besar UGM), Prof. Usman Pelly MA PhD (Guru Besar Unimed), dan Prof. Dr. Robert Sibarani, M.Si (Guru Besar USU).
Prof Syafri Sairin, MA PhD, dalam paparannya menyebutkan bagaimana sulitnya mengelola secara administratif bangsa Indonesia. "Saya saat di Wakatobi mengetahui ada 75 bahasa lokal yang tidak dimengerti. Itu akhirnya menimbulkan konflik-konflik internal di politik," sebutnya.
Di Medan, lanjutnya, konflik ada dan selalu disebut-sebut tapi tidak terbuka. "Karena itu, konflik itu diselesaikan dalam antropologi, dengan konsep 'the way of table manner' atau, 'makan bersama'. Meja itu, kata Levistrauss, menunjukkan siapa teman kita," lanjutnya.
Antropologi banyak memberikan kontribusi. "Tapi orang-orang tidak mau paham terhadap simbol-simbol yang sebenarnya setiap orang sama," tambahnya. (st)