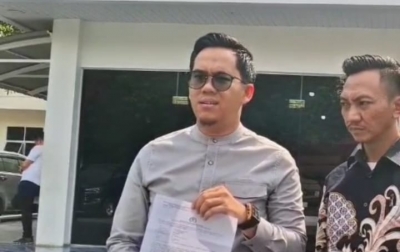Oleh: J Anto.
Bagi masyarakat Tionghoa Indonesia, Ceng Beng bukan sekadar ritual sembahyang biasa. Tapi juga wujud hao atau bakti anak terhadap orangtua. Dalam sistem nilai masyarakat Tionghoa, hao menempati posisi penting. Setiap anak akan menghindar agar tidak disebut puthao atau tidak berbakti. Ceng Beng juga menjadi media memulihkan harmoni keluarga. Itulah musabab kenapa masyarakat Tionghoa, di tengah kesibukan bisnis atau kerja, sekalipun tinggal terpisah jauh dari makam (bongpai) orangtua atau leluhur, tetap mengusahakan pulang kampung melakukan ceng beng.
Minggu malam (26/30), dengan mengajak isteri, menantu, cucu serta kerabat dekat lain berjumlah 12 orang, Iwan Hartono Alam ramai-ramai melakukan perjalanan dengan menumpang kereta api. Rombongan keluarga ini berangkat dari Sasiun KA Medan, yang terletak di sebelah Lapangan Merdeka Medan. Tujuan perjalanan Rantau Prapat, kampung halaman yang telah ditinggalkan 30 tahun lebih itu.
"Bagi saya melakukan ceng beng itu suatu kewajiban. Rasanya ada sesuatu yang hilang pada diri saya jika tidak melakukan sembahyang di bongpai sesuai ajaran Buddha Konghucu yang saya anut," ujar suami dari Herlina Tjoa (60) itu. Bagi Iwan Hartono Alam bakti terhadap orangtua tak hanya dilakukan terhadap mereka yang masih hidup, tapi juga terhadap mereka yang sudah meninggal. Senin dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, rombongan pun sampai di Rantau Prapat.
Setelah istirahat sehari, tanggal 28 Maret, Iwan Hartono Alam bersama isteri, anak dan cucunya, melakukan ziarah ke bongpai Liem So In alias Bina, mendiang ibunya yang meninggal tahun 2011 lalu.
Sebagai wujud penghormatan terhadap almarhum ibunya, beberapa jenis kue dan replika pakaian yang jadi kesukaan almarhum semasa hidup ia bawa. Usai bersih-bersih dan melakukan sembahyang di komplek bongpai yang dikelola Yayasan Perkuburan Tionghoa Pinang Lombang, Rantau Prapat, Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Amal Kemanusiaan (KOMPAK) itu langsung melakukan sembahyang. Jajan tradisional kesukaan mendiang adalah kue Cen Toe dan Ang Ku Kue warna merah. Selain itu ia juga membawa kue wajik dan bakpao. Tak ketinggalan jeruk dan nanas .
Bagi Iwan, yang telah dikaruniai 6 orang cucu itu, kue angku bukan sekadar kue biasa. Kue yang bentuk bagian atasnya mekar itu juga dipercaya sebagai simbol kemakmuran. Sedangkan buah nanas melambangkan kesuburan, dan jeruk simbol harmoni.
Rasa Hormat Bukan Menyembah
Relasi antar manusia dalam tradisi Tionghoa memang tidak akan hilang, meskipun kematian telah memisahkan orang dari kehidupan di dunia ini. Karena itu tidak heran kalau dalam setiap keluarga penghormatan kepada leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama.
“Orang yang tidak lagi menghormati leluhur yang telah meninggal dianggap sebagai anak durhaka atau put-hao, sebab mereka melupakan asal usul dan jasa dari para pendahulunya, bahkan melupakan akar kehidupannya sendiri,” ujar Berry CWT pengamat budaya Tionghoa, salah seorang pendiri Sahabat Center Medan.
Menurut Berry CWT penghormatan kepada leluhur bukan suatu sikap menyembah atau memperlakukan leluhur bak dewa. Persembahan hanya sarana untuk menyatakan hormat dan penghargaan kepada leluhur atau orang yang berjasa dalam hidup.
Berry menambahkan, masyarakat Tionghoa membagi dunia dalam dualisme yin-yang. Kehidupan di dunia disebut dunia yang, kehidupan sesudah dunia ini disebut yin. Jika orang meninggalkan dunia yang, dia berpindah ke dimensi lain dari kehidupan. Hubungan antara yang hidup dan yang mati, antara dunia sini dan dunia sana harus dijaga keseimbangannya. Bila keseimbangan itu terganggu, roh-roh akan marah.
“Keseimbangan dijaga bukan dengan persembahan, melainkan dengan perilaku hidup moral yang baik dan benar,” tambahnya.
Sejak Kaisar Beng Thay Couw
Mengutip Marcus A.s, sembahyang ceng beng dilakukan sejak Dinasti Ming. Dikisahkan seorang anak bernama Chu Guan Ciong (Zhu Yuan Zhang, pendiri Dinasti Ming) berasal dari keluarga miskin. Ketika terjadi bahaya kelaparan di negerinya, keluarga Chu Guan Ciong meninggal karena kelaparan. Maka Chu Guan Ciong hidup menggelandang sampai kemudian ia tinggal di sebuah kuil dan belajar Buddha. Chu Guan Ciong sejak kecil sudah terbiasa menderita dan tahan menahan rasa lapar, sehingga ketika dewasa ia memiliki jiwa besar.
Pada suatu saat ia mengumpulkan sejumlah pemuda dan melakukan pemberontakkan. Pemberontakan itu berhasil, bahkan ia naik tahta menjadi kaisar dengan gelar Beng Thay Couw, Kerajaannya disebut Thay Beng Couw atau Ta Ming (1368 – 1644 M).
Sesudah memeroleh kedudukan mulia sebagai kaisar, Kaisar Beng Thay Couw teringat kepada ayah ibunya yang sudah meninggal dan entah dimana keberadaan makam mereka. Memikirkan hal itu, kaisar menjadi sedih. Ia tak tahu harus bagaimana berbakti kepada ayah ibunya sebagai seorang kaisar. Tentara kerajaan sudah dikerahkan untuk menemukan kuburan kedua orangtuanya, tapi tak ketemu juga.
Seorang menterinya kemudian memberi saran agar seluruh rakyat saat pergi ke kuburan orangtua melakukan tee-coa atau melempar kertas ke atas nisan. Jika ada nisan yang tidak di tebari kertas, maka itu berarti makam orangtua kaisar. Kaisar Beng Thay Couw setuju ide menterinya, lalu ia membuat titah agar rakyat melakukan tee-coa saat berziarah ke kuburan. Beberapa hari kemudian ketika Kaisar Beng Thay Couw pulang ke kampung halamannya ditemukan dua buah kuburan yang tak ditebari tee-coa. Kuburan itu penuh rumput, lalu dibersihkan dan diakui sebagai kuburan kedua orangtua kaisar.
Sejak itu Kaisar Beng Thay Couw memerintahkan saat membersihkan makam harus juga dilakukan tee-coa.
Wisata Tanpa Promosi
Menurut Berry CWT ceng beng yang dilakukan setahun sekali ini juga merupakan sarana untuk mempererat rasa persaudaraan, bahkan mediasi bagi keluarga yang mengalami disharmoni.
“Kan tidak mungkin mereka yang tengah bertengkar juga membuat ribut saat lagi bersembahyang kepada leluhur,” ujarnya. Begitulah, sembahyang ceng beng memang erat berkait dengan konsepsi hao.
Konsep bakti terhadap orangtua ini juga yang membuat ceng beng tetap setia dilaksanakan masyarakat Tionghoa dari waktu ke waktu. dari generasi ke generasi. Tidak peduli apakah mereka kini tinggal jauh di rantau. Tak terkecuali para Tionghoa diaspora. Berry CWT memberi contoh Tionghoa Pematangsiantar yang merantau ke berbagai kota besar di Indonesia, bahkan mereka yang tinggal di Hong Kong, Malaysia, Tiongkok, atau Vietnam, saat ceng beng mereka ramai-ramai pulang ke Pematangsiantar.
Warga Tionghoa perantau Siantar menurut Berry CWT punya perkumpulan. Saat ceng beng mereka biasanya pulang ramai-ramai. Jumlah mereka ratusan orang. Tak jarang mereka sampai carter pesawat terbang. Mereka bukan saja anak-anak muda yang telah sukses di rantau. Menurut Berry CWT yang pernah lama tinggal di Siantar, yang merayakan ceng beng juga warga Tionghoa yang pernah jadi korban kebijakan PP 10 tahun 1959 dan repatriasi ke Tiongkok paska-peristiwa 1965.
Hadirkan Rasa Aman
Ceng beng mereka jadikan ajang kumpul-kumpul, mempererat persaudaraan dan juga sarana reakreasi. Banyak pihak kecipretan rezeki saat berlangsung sembahyang ceng beng. Hotel, restoran, objek wisata, pedagang UKM biasanya menikmati imbas dari wisatawan religi ini.
“Intinya Pendapatan Asli Daerah beberapa daerah tercipratlah. Karena itu selayaknya keamanan dan kenyamanan saat melakukan ceng beng di tiap bongpai dijamin aparat keamanan. Jangan biarkan premanisme mengganggu peziarah dan merusak wisata religi yang tak butuh anggaran promosi dinas parwisata itu,” ujar Berry CWT yang melakukan ziarah pada 26 April lalu di Pantai Cermin itu.
Berry CWT mengaku dirinya banyak mendapat masukan soal premanisme usai seseorang melakukan ziarah. Ia berharap aparat keamanan serius menangani hal tersebut.
“Jangan anggap sepele masalah ini. Perlakuan premanisme yang dialami para peziarah bisa menimbulkan dampak tak terduga,” kata Berry CWT. Ia misalnya menyebut kecenderungan beberapa orang Tionghoa mengkremasi dan membawa abu leluhur di kota tempat orang itu berdomisili.
Jika fenomena itu meluas, maka dampak ekonomi ceng beng pun sudah ada di depan mata. Mau?