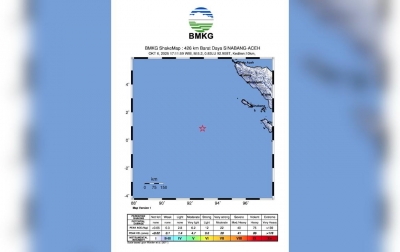Oleh: J Anto
WARGA Tionghoa Medan, terutama penganut agama Buddha Mahayana, Konghucu, dan Taoisme pada September ini akan melakukan sembahyang Cio ko atau Pho To (Hungry Ghost). Sebuah ritual religi yang mengajarkan pentingnya nilai bakti terhadap orang yang lebih tua dan menumbuhkan sikap empati terhadap arwah-arwah terlantar di alam gaib, serta mereka yang papa di alam nyata.
Sudah 42 tahun tragedi itu berlalu, namun Budiman Trisanto (68) alias Kampak, masih segar mengingatnya. Waktu itu ia berusia 26 tahun. Pekerjaannya sopir truk barang antarkota. Suatu hari sebuah peristiwa naas terjadi. Di Perbaungan, sebuah bus yang sarat penumpang menabrak truk yang dikendarainya. Sebanyak 13 penumpang bus meninggal seketika. Ia sendiri selamat dan hanya mengalami cedera di kaki kanannya.
Sekalipun kesalahan ada pada sopir bus, apalagi sopir bus juga masih dibawah umur, namun perasaan bersalah bersemayam di hatinya kala itu. Maklum hal itu berhubungan dengan nyawa orang. Ia sendiri merasa bersyukur lolos dari kecelakaan maut itu.
Kampak lalu berobat ke dokter. Saat belum ada perubahan berarti, keluarganya memutuskan membawa berobat ke seorang tabib di sebuah vihara di Pematangsiantar. Beberapa minggu dirawat, ia pun sembuh. Dari tabib itu, ia mendapat berkat lain: pencerahan akal budi.
"Tabib bilang, musibah yang menimpa saya mungkin terjadi karena punya ‘utang' di dunia sana," tuturnya saat dijumpai di Vihara Gunung Timur, Rabu (30/8). Mengenakan kaos hijau lumut dan celana jeans, penampilan bapak dua anak dan memiliki 4 cucu itu terlihat masih bugar. Kontras dengan usianya yang mendekati 70 tahun.
Sejak peristiwa itu, ia mengubah jalan hidupnya. Menjauhi dunia kekerasan yang membuatnya dipanggil ‘Kampak’ itu. Ia rajin sembahyang ke vihara, termasuk mengikuti sembahyang Cio Ko (Mandarin) atau Pho To ( Hokkien). Sekalipun sejak 1989 bersama keluarga ia menetap di Jakarta, namun tiap tahun ia selalu rutin sembahyang Pho To di Vihara Gunung Timur.
"Pak Budi ini juga relawan vihara, ia banyak ajak teman-temannya bersembahyang di sini," ujar Pengurus Harian Vihara Gunung Timur, Edy Taslim. Bagi Budiman, ritual Pho To memang telah mengubah hidupnya. Hari-harinya kini lebih banyak diisi dengan berdoa di vihara. Setelah kehidupan ekonomi mapan, ia punya punya prinsip "bangun tidur libur", artinya tak lagi mau ngoyo mencari materi, hidupnya kini lebih banyak dihabiskan untuk vihara dan liburan. Termasuk mengikuti sembahyang Pho To di Medan.
Penangguhan Penyiksaan
Pada bulan ketujuh (cit gwee) kalendar Lunar atau 5 September Masehi, menurut kepercayaaan Taoisme, roh-roh yang terlantar di akhirat diberikan "penangguhan" penyiksaan. Hal itu itu berlangsung sebulan. Sembahyang Pho To dilakukan untuk roh yang tidak disembahyangkan sanak keluarga di dunia. Mereka jadi kelaparan. Saat sembahyang Pho To, dipersembahkan berbagai makanan untuk hantu-hantu yang kelaparan itu. ( Nio Joe Lan: 1961: 2013).
Arwah leluhur yang tidak diperingati (tidak dirawat) kadang-kadang bisa menjadi gui, suatu istilah untuk arwah jahat dari neraka, yang menunjukkan bahwa mereka pun bisa menjadi jahat apabila tidak dirawat dengan semestinya. Sedangkan arwah-arwah yang pada dasarnya baik, termasuk arwah leluhur dan dewa-dewa dari agama Buddha, Tao dan Konghucu disebut shen dan pusa. (Gondomono:2013).
Karena mahluk adikodrati sangat berperan dalam kehidupan religius masyarakat Tionghoa, mereka selalu merayakan hari-hari raya setiap tahun dengan bersembahyang di rumah-rumah pemujaan atau altar keluarga. Dewa dan arwah leluhur dipuja dengan harapan para makhluk adikodrati tersebut membantu manusia agar bisa sejahtera, bahkan kaya dan sehat, dan terjamin dalam hidup selanjutnya.
Sekalipun umumnya gui harus dihindari, ada juga upaya untuk menyenangkan para gui yang dilakukan dalam perayaan-perayaan tertentu dengan memberikan bermacam persembahan sebagai semacam "suap" agar para gui membiarkan manusia hidup dengan tenang tanpa gangguan. (Gondomono: 2013, hlm. 287-288).
Penyebab arwah menjadi gui bisa karena mati mendadak atau mati karena pembunuhan dan kekerasan, sehingga belum bisa melepaskan dari ikatan dunia. Bisa juga karena mati di laut, udara sehinggga jasadnya tak bisa ditemukan dan diperistirahatkan di tempat layak (Frena Bloomfield: 1983).
Ragam replika
Gui inilah yang disembahyangi saat sembahyang Pho To. Di Vihara Gunung Timur misalnya, ritual religi ini akan dimulai 4 September dan puncaknya 5 September malam. Pihak vihara sudah menyiapkan 2.800 paket makanan sesuai jumlah umat yang mendaftar untuk mengikuti sembahyang tersebut. Paket sajian tak hanya berupa berbagai jenis makanan, tapi juga uang emas, perak, dolar, pakaian, celana, sepatu, pembantu rumah tangga, handphone, rumah, mobil bahkan kapal.
Tentu semua itu hanya berupa replika. Bahannya terbuat dari berbagai materi yang mudah dibakar saat acara sajian untuk para hantu. Ada kertas, kayu, tripleks, dan bambu. Bambu semisal digunakan untuk rangka rumah. Ukurannya cukup besar, yakni 4 x 6 meter. Tripleks dan kayu digunakan untuk rangka mobil dan perahu.
Untuk replika rumah jumlah yang disediakan vihara ada 86 buah sesuai yang dipesan umat. Butuh waktu tak kurang 2 bulan untuk mempersiapkan miniatur rumah berbahan bambu dan kertas warna warni penuh hiasan ornamen dewa-dewi dan oriental itu. Ada juga replika patung kertas Dewa Tai Shu atau Dewa Hantu yang memegang peranan penting dalam sembahyang ini.
Ragam sajian disediakan mengingat hantu-hantu terlantar di alam gaib punya berbagai kekurangan. Yang lapar butuh makanan, yang kedinginanan butuh baju atau celana, ada juga yang butuh uang, pembantu rumah tangga, dsb.
"Patung Dewa Hantu juga kita keluarkan di halaman vihara saat acara pemberian persembahan, tapi patung aslinya tidak ikut dibakar, kecuali repilkanya," tutur Edy Taslim. Keberadaan Patung Dewa Tai Shu dalam ritual itu untuk mengawasai agar roh-roh yang kelaparan itu tidak berbuat sesukanya memperebutkan makanan atau sajian lain.
Sudah puluhan tahun Edy mengikuti ritual Pho To. Saat uang kertas hendak disulut api dan dilempar ke udara, muncul hembusan angin di halaman vihara tempat ritual berlangsung. Bagi Edy, itu bukan sekadar angin biasa, tapi pertanda bahwa hantu yang lapar itu telah berkumpul dan siap mengambil sajian.
Ritual Pho To berlangsung secara bertahap, dari pukul 06.00 WIB sampai malam. Pemimpin ritual akan membacakan sejumlah kitab. Isinya doa-doa permohonan agar hantu-hantu terlantar itu tidak mengganggu umat manusia di bumi dan juga agar mendapat kedamain di alam gaib.
Selesai sembahyang, acara persembahan sajian dimulai. Berbagai paket sajian replika yang telah dikemas dalam dus, diarak dengan menggunakan truk dan kapal di sekitar lokasi ritual. Replika truk menggunakan roda mobil sebenarnya, demikian juga setir truknya. Hanya bodi truk terbuat dari tripleks dan kertas.
Setelah sajian dibakar dan makanan disantap para hantu, paket makanan boleh dibawa pulang, boleh juga tidak. Paket yang tidak dibawa pulang, dikumpulkan dan dibagikan ke sejumlah panti jompo. Jumlahnya ratusan. Ini adalah bentuk aksi sosial untuk mereka yang terlantar di dunia.
"Jadi ini memang sembahyang sosial, baik untuk para hantu terlantar maupun mereka yang terlantar di bumi ini," tuturnya.
Arwah Sahabat
Ritual Pho To juga dirayakan umat Konghucu dengan sedikit varian. Istilah hantu misalnya tak dikenal mereka. Umat Konghucu menyebutnya arwah para sahabat atau Hao Peng. Karena itu sembahyang bersama itu disebut Jing Hao Peng. Sembahyang ini dilakukan pada akhir bulan ketujuh atau 19 September. Tempatnya di rumah ibadah umat Konghucu, Kong Miao.
Tujuan sembahyang ini adalah umat terhindar dari malapetaka, nafsu iblis, dan tidak melakukan kolusi dengan arwah gentayangan guna mencapai sesuatu diluar kepercayaan terhadap Thian.
"Dalam sembahyang Jing Hao Peng, didoakan agar orang-orang yang dianggap sebagai pemuka atau tokoh yang berjasa dan mereka yang tidak disembahyangi keluarga," ujar Sekjen Majelis Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Sumut, JS Tevi Tandijono. Saat sembahyang disajikan sejumlah makanan yang diletakkan di atas sebuah meja.
"Usai sembahyang bersama dilanjutan bakti sosial dengan membagikan sembako ke sejumlah warga kurang mampu," tutur Ketua Perhimpunanan Wanita Konghucu Indonesia Sumut, JS Siet Nie.
Sebelum sembahyang Jin Hao Peng, pada awal bulan ketujuh, umat Konghucu melakukan sembahyang arwah untuk orangtua atau leluhur yang disebut Zhong Tuan Jie. Sembahyang leluhur ini kelanjutan dari Cengbeng. Bedanya Cengbeng dilakukan di bong pai, sementara Zhong Yuan Jie dilakukan di rumah. Menurut Tevi Tandijono, semua umat Konguhucu di rumah memiliki altar untuk sembahyang leluhur.
"Sembahyang ini juga wujud bakti anak kepada orangtua yang telah meninggal atau kepada leluhur yang lebih tua," ujar Ketua Pemuda Agama Konghucu Sumut, Suharto Tan. Nabi Konghucu menurutnya mengajar 8 ajaran yang wajib dijalankan umatnya, yakni bakti terhadap orangtua, rasa persaudaraan, kesetiaan, dapat dipercaya, jujur, suci hati, dan tahu malu (susila).
Bakti anak terhadap orangtua yang telah meninggal juga diwujudkan dengan memberikan makanan, minuman atau hal-hal yang disukai orangtua semasa masih hidup saat sembahyang Chit Gwee Phoa. Menurut Tevi Tandijono, hal itu karena arwah orangtua atau leluhur telah menjaga keturunan yang ada di rumah selama mereka hidup.
Pantangan
Banyak pantangan bagi umat Konghucu selama bulan ketujuh atau saat arwah-arwah sahabat itu dikeluarkan dari alam gaib. Semua aktivitas umat yang berhubungan atau menghadirkan warna merah biasanya tak bisa dilakukan. Misalnya pernikahan, kelahiran anak, peresmian toko, membangun rumah atau pindah rumah.
"Bulan ketujuh ditandai warna hitam, yin, sementara yang kita lakukan yang, jadi bisa tabrakan, tidak bagus nantinya," ujar Tevi Tandijono. Pada bulan ketujuh, tak sedikit umat yang bermimpi didatangi orangtua yang telah meninggal. Itu simbol yang mengingatkan agar keturunan yang masih hidup ingat terhadap leluhur mereka dan menyembahyangi mereka.
Percaya atau tidak, seminggu jelang perayaan sembahyang Chit Gwee Phoa, isteri Suharto Tan sudah dua kali mendapat mimpi didatangi almarhum ayahnya yang meninggal pada 2004. "Pa, aku kok asyik mimpi didatangi almarhum ayahku terus," tutur Suharto Tan.
Istrinya merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Masing-masing sudah berkeluarga dan tinggal di kota berbeda. Seorang di Pekanbaru, Batam, dan seorang lagi di Kamboja.
"Setiap anggota keluarga harus melakukan sembahyang leluhur saat Chit Gwee Phoa. Jika ada yang tidak melakukan, leluhur bisa mengingatkan lewat mimpi," ujar Tevi Tandiono. Nah, mau disebut puthao?

Replika Rumah

Suharto Tan, Siet Nie, dan Tevi Tandijono

Edy Taslim

Budiman Sunarto

Replika Dewa Hantu