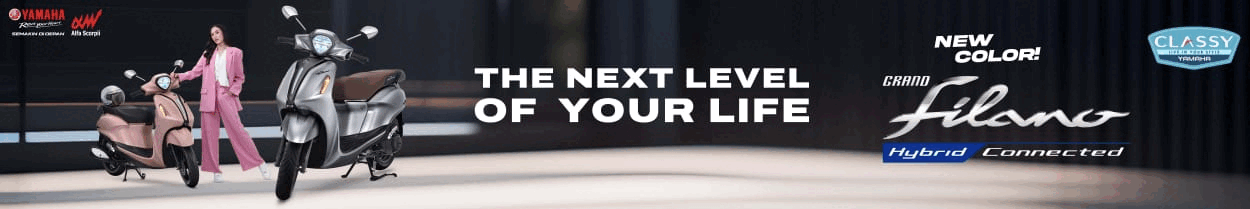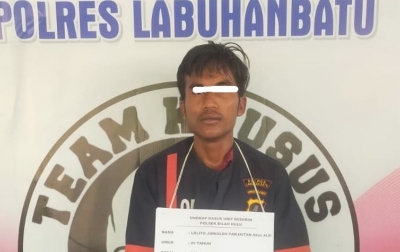Celakanya lagi, budaya instan tersebut bukan hanya menjangkiti para peserta didik, namun juga lembaga pendidikan dan perangkatnya. Simaklah ketika jelang Ujian Nasional (UN), berbagai sekolah sibuk menyelenggarakan les tambahan atau setidak-tidaknya menghimbau siswanya untuk memenuhi bimbel-bimbel. Simak pula ketika UN tiba, berbagai bentuk kebocoran kunci jawaban terjadi di sana-sini. Seperti jamur yang tumbuh di musim hujan.
Pendidikan serba instan yang dipraktekkan oleh berbagai lembaga pendidikan dan penghuninya secara sosiologis dapat dikategorikan sebagai fenomena McDonaldisasi. Sebagaimana dikemukakan George Ritzer dalam The McDonaldization of Society (2004), McDonaldisasi adalah proses-proses dimana prinsip-prinsip restoran cepat saji mendominasi masyarakat. Tak jauh beda dengan lembaga lainnya lembaga pendidikan tampaknya tidak mau ketinggalan meniru budaya ini.
Ada empat unsur Mcdonaldisasi yang kini sedang berlangsung dalam tubuh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Pertama, efisiensi. Prinsip efisiensi menuntut perseorang/lembaga/perusahaan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan penyederhanaan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Seiring dengan lembaga pendidikan yang telah berubah menjadi lebih kapitalis, prinsip efisiensi kini mulai mendarah-daging.
Hal ini berlangsung dalam proses belajar dan mengajar dalam berbagai sekolah di Indonesia. Sejatinya guru dituntut untuk mencerdaskan seluruh peserta didik di ruang kelas. Namun akibat adanya silabus, membuat guru harus menghabiskan seluruh tema mata pelajaran tiap minggunya, tanpa peduli apakah ada yang belum paham akan materi tersebut. Alhasil siswa yang punya daya serap ilmu yang rendah, akan tertinggal dari teman-temannya yang masuk kategori pintar. Dalam kasus ini sekolah seolah tidak mau ambil pusing untuk membantu siswa yang memiliki daya serap ilmu yang rendah. Karena dianggap repot, memakan waktu dan melelahkan. Sekolah baru akan bekerja optimal bila musim ujian tiba dengan menyelenggarakan les tambahan.
Efisiensi juga berlangsung dalam bentuk penekanan biaya operasional. Sebut saja dengan menumpuk puluhan murid dalam sebuah ruangan kelas ketika jumlah siswa menumpuk, tanpa peduli apakah over kapasitas atau tidak. Bagi sekolah yang terpenting mereka tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk membangun ruangan baru. Contoh lainnya dapat kita temukan di perguruan tinggi. Misalnya kebijakan menghapus jurusan yang dianggap tidak diminati oleh masyarakat dan tidak menguntungkan seperti jurusan filsafat, budaya, dan ilmu sosial lainnya. Sementara jurusan yang mendatangkan uang seperti jurusan ekonomi, kedokteran, teknik, dan hukum difasilitasi sedemikian rupa.
Tak sampai disitu kerapkali demi menekan pengeluaran, berbagai lembaga pendidikan membiarkan gedung belajar tampak kumuh, perpus tidak lengkap, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Kedua, kalkulabilitas. Ritzer (2011) menyatakan bahwa prinsip kalkulabilitas dalam McDonaldisasi lebih menekankan pencapaian kuantitas sehingga mengorbankan aspek kualitas. Dalam lembaga pendidikan prinsip ini juga kian menguat. Bagi sekolah-sekolah, khususnya sekolah negeri, akreditasi merupakan harga mati, sehingga apapun dilakukan demi bisa mencapai akreditas yang tinggi. Salah satunya berusaha agar setiap tahunnya sekolahnya meluluskan peserta didik sebanyak-banyaknya bahkan kalau bisa meluluskan seluruh siswanya.
Di samping itu kuantifikasi juga muncul dalam bentuk cara evaluasi dan produk hanya dilihat dari sisi kuantitas saja. Semakin banyak orang yang berminat masuk ke sekolah/universitas tertentu semakin populer namanya. Semakin banyak lulusan yang dihasilkan semakin lembaga pendidikan tersebut dianggap sukses menyelenggarakan pendidikan. Bahkan baik tidaknya kualitas seorang peserta didik hanya diukur dengan berbagai macam skala nilai. Tidak peduli apakah nilai tersebut berkorelasi positif dengan kemampuan sebenarnya dari si pemilik nilai.
Di samping itu, kalkulasi dana juga menjadi fokus lembaga pendidikan. Demi menambah uang kas. Sekolah/universitas membuka kelas eksekutif berbayar. Misalnya di perguruan tinggi negeri ada jalur masuk bernama UMBPTN. Selain harus membayar biaya pendaftaran yang mahal, setiap mahasiswa yang lulus juga harus membayar uang kuliah yang sudah dipatok oleh kampus yang jumlahnya lebih tinggi dari mahasiswa yang lulus dari jalur seleksi lainnya. Bahkan karena dianggap begitu menguntungkan, belakangan kuota pada jalur masuk ini semakin diperbesar.
Ketiga, prediktabilitas (keterprediksian). Prinsip keterprediksian di lembaga pendidikan terwujud dalam kurikulum dan standarisasi lulusan untuk pasaran kerja. Demi menciptakan lulusan yang berstandar dan siap pakai. Insitusi pendidikan mendesain kurikulum yang sedemikian rupa sesuai dengan permintaan pasar. Dengan kata lain pendidikan lebih diarahkan pada kemampuan menyongsong pasar kerja.
Selain dengan kurikulum, keterprediksian juga diwujudkan dalam penyesuaian jurusan. Hal tersebut kerap terjadi di perguruan tinggi. Dimana kampus membuka program-program baru sesuai dengan kebutuhan pasar semisal keperawatan, kedokteran, ekonomi, farmasi, pariwisata, Hubungan Internasional, maupun sastra.
Keempat, teknologisasi. Kebijakan pendidikan hari ini telah mendorong sekolah/universitas untuk menggunakan proses belajar berbasis teknologi. Pendidikan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi sehingga lulusannya melek teknologi. Meskipun di satu sisi penggunaan teknologi sangat bermanfaat. Namun di sisi lain kebijakan teknologisasi kerap menjadikan penyelenggara dan peserta didik menjadi budak teknologi. Meminjam istilah C. Wright Mills, peserta didik cenderung menjadi cheerful robots yang pintar secara teknis, namun kehilangan naluri kritis dan reflektif. Alhasil teknologisasi memunculkan dehumanisasi dimana para hasil didikan bertindak seperti robot.
Irrasionalitas
McDonaldisasi telah mengubah wajah pendidikan kita. McDonaldisasi yang bermula dari sesuatu yang rasional yakni otonomi pendidikan, kini berakhir dengan irrasionalitas seperti dehumanisasi, dan kemerosotan kualitas pendidikan. Lembaga pendidikan yang harusnya berfungsi untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, kini hanya berpikir bagaimana menambah kuota didikan dan lulusan. Berbagai penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta berlomba-lomba membuka cabang baru demi mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang ingin bersekolah.
Tidak sampai disitu, tingginya animo masyarakat atas pendidikan, dimanfaatkan oknum sekolah/kampus untuk menambah pundi-pundi kas dengan cara mematok biaya pendidikan yang begitu mahal. Celakanya, kelimpahruahan bangunan sekolah maupun universitas tidak dibarengi dengan upaya penyelenggara pendidikan untuk menciptakan lulusan yang berdaya saing. Tidak pula diikuti dengan upaya menyiapkan lowongan pekerjaan bagi lulusannya. Pada akhirnya lembaga pendidikan memiliki andil besar sebagai "pabrik penghasil pengangguran" di negeri ini.
Di samping itu pendidikan yang seyogyanya diselenggarakan untuk meningkatkan nilai jual dimana orang-orang yang berpendidikan tinggi dibayar lebih mahal dibandingkan yang tidak sekolah. Dalam banyak kasus para lulusan justru kebanyakan bekerja sebagai buruh industri yang diupah murah. Sialnya, akibat generalisasi skill yang dimiliki banyak lulusan sekolah/perguruan tinggi membuat para tenaga kerja tidak dapat menolak upah rendah tersebut. Karena kalau menolak, pemilik modal bisa dengan mudah menemukan orang lain yang punya kemampuan sama. Ironis.***
* Penulis adalah Pengamat Sosio-Politik dan Pegiat Literasi di Toba Writers Forum (TWF)