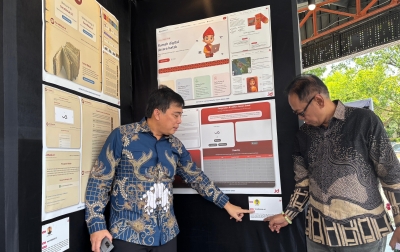Oleh: J Anto
SASTRA Melayu tradisi berfungsi membangun, mengukuhkan dan menyakralkan institusi kemelayuan. Namun para pujangga Melayu juga banyak menghasilkan karya sastra yang kritis terhadap perilaku sultan dalam mengelola kekuasaan. Karya sastra yang bisa menjadi kompas peradaban Melayu.
Ada yang membuat gelisah Wan Syaifuddin akhir-akhir ini. Profesor sastra Melayu tradisi yang telah menulis puluhan buku sastra Melayu tradisi ini menengarai kuatnya kecenderungan penelitian terhadap peninggalan budaya tangible (materi) suatu etnik, dan mengabaikan penelitian budaya intangible (nonmateri) saat merekonstruksi sejarah kemelayuan sebagai suatu etnik.
“Padahal Melayu sebagai bangsa dan etnik, tidak terlepas dari perkembangan sastra tradisi,” kata Guru Besar Sastra Melayu Tradisi saat dijumpai di sebuah kedai kopi tak jauh dari Universitas Sumatera Utara tempatnya mengajar, Rabu (12/6). Kesultanan dan istana Deli menurut Wan Syaifuddin, dibangun, dikukuhkan, dan disakralkan melalui sastra tradisi.
Ia memberi contoh mitos dan hikayat, cerita-cerita yang hidup dalam masyarakat Melayu. Sebagai bentuk sastra tradisi, ia adalah objek yang diamalkan raja-raja Melayu untuk memperkuat kekuasaan dengan nilai-nilai sakral. Hikayat misalnya merupakan genre sastra tradisional yang digunakan kaum bangsawan, orang-orang besar dan sultan-sultan Melayu untuk membangun sosio politik Melayu.
Hikayat adalah standardisasi mitos dan merupakan bahan bacaan bagi rakyat dan bangsawan. Dalam alam Melayu, hikayat adalah kisah kekuasaan politik magis raja yang merupakan media pengabdian rakyat. Baik mitos maupun hikayat ditulis para pujangga istana dan bersifat anonim. Pada fase ini lahir Hikayat Hang Tuah, Hikayat Deli, Hikayat Hamparan Perak, dsb.
Istana Maimun semisal mendapat legitimasi dari mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Melayu Deli. Sifat mitos dan fiksi dalam karya Sastra Melayu, seperti Hikayat Deli merupakan pesona estetik dalam kebudayaan Melayu. Namun bukan keindahan semata yang dicari dalam karya sastra tradisi, tapi juga nilai kebaikan dan kearifan baik yang berasal warisan Hindu, Buddha, Islam maupun yang datang dari barat yang mewarnai sastra Melayu tradisi.
Dalam Hikayat Deli, misalnya Gocah Pahlawan digambarkan sebagai orang sakti. Saat kapal mereka terombang-ambing dan pecah dihempas badai lautan, hanya dia dan beberapa pengawalnya yang selamat. Gocah Pahlawan dianggap memiliki tuah. Karena tuah itulah bisa berdiri Kesultanan Deli.
Peran Temenggung
Dalam tradisi Kesultanan Melayu di Sumatera Timur, pujangga menurut Wan Syaifuddin memang memiliki tempat khusus. Pada Kesultanan Melayu ada institusi Temenggung, yang menghimpun para pujangga untuk berkarya. Saat era masuknya Islam, peran pujangga ini dilakukan oleh ulama yang pujangga.
“Pada waktu tertentu, seperti setelah Ramadan, Sultan memberi kebebasan pujangga untuk berkarya sebebas-bebasnya,” tuturnya. Pujangga dianggap sebagai orang yang mampu berpikir jernih, jujur, dan adil. Pada akhir bulan, para pujangga ini harus menunjukkan karya-karya yang mereka hasilkan kepada sultan. Dari karya-karya itu, sultan mengambil kebijakan dalam menjalankan dan mengelola kekuasaan terhadap rakyatnya.
Dengan kata lain, karya-karya pujangga adalah kompas peradaban bagi kesultanan dan masyarakat Melayu. Satu di antara beberapa teks sastra tradisi yang menggambarkan keharmonisan hubungan penguasa, rakyat, dan cendikia dengan khazanah kesusastraan Melayu tradisi adalah kutipan berikut:
/...demikian bunyi titah yang mulia itu, bahawa ia merasakan rakyat minta agar bendahara perbuatkan hikayat serta sebarang karya seni kepada pujangga yang terlahir daripada masyarakat, bukan semata-mata peristiwa dan peraturan segala raja-raja, melainkan hendaklah segala peristiwa rakyat Melayu dengan istiadatnya sekali, supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita, diingatkannya oleh mereka itu, syahdan beroleh faedah-lah ia daripadanya/ (Wan Syaifuddin: 2009).
Pada fase ini terjadi perubahan bentuk dan motif dalam karya sastra tradisi. Bentuk sastra berubah dari hikayat ke syair dan menampilkan nama ulama pujangga. Menurut Wan Syaifuddin, puluhan bahkan ratusan karya syair dan hikayat lahir di wilayah-wilayah kekuasaan Raja Melayu. Namun di Sumatera Timur tak segemuruh yang muncul di kerajaan lain. Hanya lahir Hikayat Deli, Syair Tunggul Serdang, Syair Burung Punggok, dan Syair Ikan Terubuk.
Namun menurutnya, tak seluruh karya sastra boleh disebarluaskan ke masyarakat. Ada karya-karya yang disekat oleh sultan atau pembantu-pembantunya. “Kadang ada karya pujangga yang menulis perilaku sultan secara jujur,” tutur doktor sastra Melayu tradisi dari Universiti Sains Malaysia tahun 2005 itu. Saat Ramadan, sultan umumnya suka mengadakan perjalanan ke kampung-kampung.
Seperti apa kelakuan sultan saat bertemu masyarakat, apa tanggapan masyarakat, apa yang dilakukan sultan atau bagaimana sultan mengelola kekuasaannya? Semua ditulis secara jujur oleh pujangga.
“Karya sastra yang ditulis jujur, bukan penuh kepura-puraan inilah yang disekat sultan. Hanya boleh beredar di kalangan tertentu, bukan di kalangan masyarakat,” katanya. Dalam masyarakat Melayu Deli, hubungan antara sultan dengan masyarakat tertuang dalam sebuah ungkapan. “Pantang durhaka kepada raja, berbuat baik kepada raja harus berpada-pada”. Artinya kebijakan sultan tak selamanya harus diikuti, tapi harus diwaspadai. Jika tidak benar tidak perlu diikuti. Namun ketidaksetujuan harus diungkapkan dengan bahasa yang sopan.
Menurut Ketua Umum Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komda Sumatera Utara 2015 - 2020, dalam konsep budaya Melayu, bahasa lahir dari batin karena itu harus santun. Penyair senior Sumut Damiri Mahmud mengistilahkan sebagai santen balade, santan yang rasanya lemak manis bersebati rasa pedas.
Meski begitu, santun atau tak mendurhaka raja, menurut Syaifuddin tidak berarti mengabaikan kejujuran dan keadilan.
Di Sumatera Timur, menurut suami dari Romana Ayuni Loebis, ada karya pujangga Syair Burung Punggok dan Syair Ikan Terubuk yang merupakan syair protes terhadap kelakuan sultan yang suka melecehkan rakyat biasa. Oleh sultan karya itu “ditahan surat” alias tak boleh diterbitkan. Oleh pujangga, dengan arif syair itu lalu digubah dengan mengganti tokoh-tokohnya dengan tokoh-tokoh binatang, sehingga mengaburkan subjek yang dikritik.
Kebijakan seperti ini sebenarnya merupakan kerugian besar bagi keberadaan sastra Melayu tradisi dalam khasanah sastra nasional. Menurut Wan Syaifuddin karya-karya pujangga yang disponsori sultan, namun isinya mengritik sultan atau kesultanan dalam memerintah, harus terus-menerus digali. Terutama yang berbentuk prosa seperti syair atau hikayat.
Ia meyakini karya tersebut ada karena inspirasinya bersumber dari masyarakat Melayu. Selama ini baru karya sastra dalam bentuk ungkapan yang sudah dikenal masyarakat dan banyak dikaji, misalnya ungkapan, “raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah”.
Belum lama ini ia pernah menghadiri Festival Siak Bermadah. Lelaki kelahiran Tanjung Morawa, 9 September 1965 ini menyaksikan sebuah tarian yang digubah dari syair seorang pujangga yang mengisahkan tentang perjalanan seorang sultan berkaitan dengan libido sultan. Isi syair seperti ini dianggap memalukan, tabu. Meski syairnya ada. Maka secara kreatif oleh seniman hal itu digubah dalam bentuk tarian agar “pantang durhaka kepada raja”.
Bagi penulis buku Khasanah Kebudayaan Melayu Sumtera Utara itu, yang dilakukan seniman pertunjukkan Melayu, merupakan bentuk kreativitas dalam menjaga budaya dan tradisi Melayu sepanjang zaman melalui karya-karya tradisional yang ada.
Laga Bongak
Pada 2018, ia juga pernah diundang menjadi salah seorang juri pada Festival Laga Bongak, sebuah pentas seni pertunjukkan tradisi yang direvitalisasi Pemkab Labuhanbatu. Laga bongak adalah lomba debat belagak bongak (nokoh-nokoh atau bohong-bohongan) dengan menggunakan bahasa Bilah dan Panei.
Pada lomba itu tiap peserta yang mewakili kecamatan masing-masing, melontarkan sindiran kepada lurah, camat, bahkan bupati yang dianggap tidak dekat dengan warganya. Karena disampaikan dengan guyon, lurah, camat atau bupati tak bisa marah-marah.
“Apalagi peserta festival bilang, “Ini ‘kan hanya bongak-bongak,” tuturnya. Seni pertunjukan rakyat seperti ini, menurutnya merupakan bentuk kearifan lokal dalam mengelola interaksi antara rakyat dengan penguasa. Dalam konteks kekinian, laga bongak bisa jadi katarsis saat saluran politik mampet atau mengurangi aksi parlemen jalanan.
Namun kesenian rakyat Melayu seperti ini yang kurang mendapat perhatian dari seniman istana di Sumatera Timur. Menurutnya, itu terjadi pada fase saat pra kemerdekaan seiring masuknya nilai-nilai barat yang dibawa bangsa barat.
Pada fase itu muncul karya sastra roman yang bersumber dari perubahan sosial yang cepat. Namun menurut Wan Syaifuddin, tidak melahirkan karya-karya sastra dari kaum istana di Sumatera Timur. Institusi Istana Raja Tanah Deli Sumatera Timur, tidak memperhatikan alur perubahan sosial secara wajar sehingga tidak banyak menghasilkan karya-karya sastra yang agung. (Wan Syaifuddin: 2018 : 25 - 26).
Itu sebabnya dalam khazanah sastra modern, belum ada umbangan signifikan dari sastra Melayu. Bahkan kaum cerdik pandai atau sultan sebagai penguasa di istana menjauh dari perubahan-perubahan sosial budaya rakyatnya, yang seharusnya diabstraksikan dalam karya-karya besar sehingga tercermin sultan mempunyai daya serap atau kepedulian yang tinggi kepada rakyatnya (Wan: 26).
Pada seni pentas pertunjukkan Deli, kebanyakan dikembangkan seniman istana adalah monora, makyung, teater bangsawan, ronggeng (tonil) yang hanya populer di kalangan istana. Ronggeng sekalipun kemudian berkembang ke masyarakat, namun menurutnya, hanya seni tari atau seni gerak tubuh yang ditonjolkan.
“Kalau pun ada, seniman yang berpantun, mereka menjaga betul agar tidak menyimpang,” katanya. Artinya pantun yang dibawakan dalam ronggeng, tidak mungkin dilepas sebebas-bebasnya. Batasnya ada, yakni tidak melakukan kritik ke penguasa.
“Seni sastra Melayu masih banyak dikemas dengan kepura-puraan, belum banyak yang alamiah. Apalagi yang bersinggungan dengan kekuasaan,” tambahnya.
Puluhan tahun mengkaji dan menggeluti sastra Melayu tradisi, itu yang membuatnya merasa tidak puas. Meski begitu, ia terus takzim terjun ke masyarakat, menelisik karya-karya sastra Melayu tradisi untuk menemukan harta warisan budaya nonmateri yang merupakan kompas peradaban masyarakat Melayu itu.