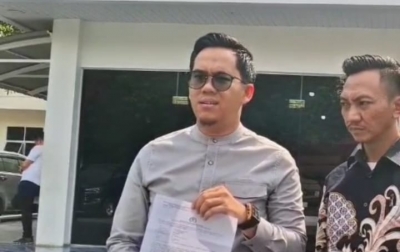Oleh: dr Robert Valentino Tarigan SPd SH.
Adakah jari telunjuk merupakan simbol dari kekuasaan? Atau kekuasaan adalah telunjuk? Pada masa monarki, kedua pertanyaan tersebut bisa dijawab ‘ya’. Ketika itu fatwa adalah telunjuk raja. Makanya orang-orang Jawa yang santun, kerap menggunakan ibu jari (jempolnya) untuk menunjuk sesuatu. Dengan menggunakan ibu jari, kesannya lebih egaliter, jauh dari sikp memerintah.
Perlahan zaman bergulir, dikenallah demokrasi yang merupakan kekuasaan rakyat. Dari, oleh dan untuk rakyat. Tapi, apakah demokrasi di Indonesia sudah sebagaimana yang kita harapkan?
Demokrasi bukanlah sesuatu yang instan, sebagaimana makanan instan yang begitu diseduh air panas langsung dapat dinikmati. Demokrasi adalah perjuangan dan terkadang memerlukan waktu sangat panjang, yang uniknya tiap zaman seolah memiliki bentuknya sendiri.
Rezim orde lama yang dilakoni Soekarno malah berusaha mengawetkan kekuasaannya lewat pernyataan majelis yang mengaku perwakilan rakyat sebagai “presiden seumur hidup”. Orba juga tak jauh beda. Meskipun Soeharto bukan presiden seumur hidup, pun melakoni apa yang disebut orang pintar sebagai oligarki eksekutif. Selama 32 tahun kekuasaan orba berhasil misubordinasi lembaga-lebaga yang ada.
Masuklah kita di era (orde) reformasi. Pun menurut penulis, era reformasi tetap juga mengakal-akali rakyat. Memang eksekutif tidak dapat lagi bertingkah macam-macam, tetapi peran legislatif yang begitu besar menciptakan apa yang disebut orang pintar sebagai oligarki parlemen.
Memasuki era transisi kepada kekuasaan rakyat yang ditandai dengan pemilihan langsung oleh rakyat, baik presiden maupun legislatif (DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota). Terpilihlah presiden dan wakilnya oleh rakyat, begitu juga para legislatif. Meski untuk pemilihan legislatif menimbulkan riak yang cukup berarti, tapi sudahlah, kita anggap saja hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari belum terbangunnya sistem.
Kini, tahun baru 2019 sudah kita masuki, kekuasaan sebagian kepala daerah pun mendekati masa akhir. Artinya, tahun 2019 merupakan hari-hari terakhir bagi sebagian besar kepala daerah. Pertanyaannya, akankah penguasa-penguasa daerah saat ini rela melepas ‘baju kekuasaan’-nya? Jawabnya, bisa ‘ya’, bisa juga ‘tidak’.
Berkuasa Itu Nikmat
Yang pasti, berkuasa itu nikmat. Mengapa tidak, ketika kekuasaan ada di tangan kita, ia (kekuasaan) umpama jari telunjuk terhadap tombol lampu listrik yang dapat menghidup atau mematikan cahaya bola lampu. Itulah yang diisyaratkan Putu Wijaya dalam naskah monolognya berjudul “Bos”.
Kekuasaan adalah jari telunjuk yang dapat diarahkan ke mana saja. Tapi, si Bos sesekali terhenyak juga bila jari telunjuk itu diarahkan kepadanya. Makanya, agar jari telunjuk tidak mengarah kepada si Bos, dicarilah cara-cara mengawetkan kekuasaan (immortal).
Pilkada yang seharusnya dilakukan secara langsung oleh rakyat pun diupayakan sedemikian rupa agar yang diplih rakyat kelak adalah mereka-mereka juga. Betapa tidak, kedaulatan untuk memilih kepala daerah yang diatur oleh undang-undang.
Justru itu, kini tak sedikit kepala daerah yang berebut menjadi ketua partai. Kenapa? Sebagai ketua partai, tentu ia berhak menentukan kandidat kepala daerah. Karena itu pula, perebutan kursi ketua partai merupakan pertarungan yang terkadang menggunakan segala cara.
Sebagaimana petuah orang-orangtua, ada tiga ta yang sangat nikmat di dunia ini dan terkadang dapat menghilangkan kemanusiaan manusia. Ta pertama, adalah tahta (kekuasaan), kemudian harta, selanjutnya khusus untuk pria-wanita. Ketiga ta inilah yang terkadang memperbudak manusia sehingga memberhalakan kekuasaan, harta dan seks.
Meski menurut Betrand Russel (1872-1970) dorongan atau motivasi bagi seorang manusia berbuat sesuatu bukanlah dorongan seks seperti yang dikatakan Sigmund Freud (Bapak Psikoanalisa), akan tetapi pada titik tertentu sebagaimana dikemukakan Freud seks dapat mendominasi seseorang, sehingga berbuat sesuai dorongan syahwatnya semata.
Kata Russel, dorongan pada kekuasaan itu berbentuk eksplisit pada pemimpin yang ingin berkuasa dan bersifat implisit pada manusia yang bersedia mengikuti sang pemimpin. Maka dalam bentuk negatif, dorongan implisit tadi digadaikan dalam bentuk uang atau bagi-bagi kekuasaan (proyek).
Berhasil Berkuasa
Jadi, seorang pemimpin berhasil berkuasa, bukan hanya karena dorongan hendak berkuasa yang ada dalam dirinya sendiri. Ada pula dorongan hendak berkuasa dalam diri orang lain, tetapi cukup dengan mendukung atau mengikut sang penguasa. Dengan berbuat begitu, para pendukung dan pengikut orang yang berkuasa, merasa diri mereka juga telah ikut berkuasa, dan dorongan kekuasaan dalam diri mereka telah terpenuhi.
Dorongan untuk berkuasa ini pada banyak orang seakan tak kenal batas. Kenyataan serupa inilah yang melahirkan pemimpin-pemimpin dari zaman dahulu hingga ke zaman modern untuk mencoba mengabadikan bahkan meluaskan kekuasaan mereka selama dan seluas mungkin. Kaisar-kaisar Roma meluaskan kekuasaannya hendak menaklukkan Mesir pula, timbulnya seorang Hitler sebelum perang dunia kedua merupakan beberapa contoh sejarah.
Bersebab rasa nikmat itu ingin terus abadi sampai akhir hayat, bahkan kalau perlu sampai ke tujuh turunan sekalian, maka kekuasaan diawetkan. Pemilihan rakyat yang seharusnya menjadi keniscayaan sejarah, dibuat tata caranya sedemikian rupa. Sehingga rakyat jadi sekadar domba-domba putih yang dengan tata cara seolah menjalankan demokrasi digiring ke satu titik: memilih mereka yang ‘gila’ kekuasaan ini.
Kenapa demikian? Bagi orang-orang yang mengidap post-power syndrome, kekuasaan adalah segalanya. Tanpa adanya kekuasaan bagi mereka itu adalah kiamat. Ya, telunjuk harus tetap dapat diarahkan sesuka hati. Sekarang tinggal terpulang kepada rakyat, akankan rela digiring sedemikian rupa, atau mau mencoba power people agar calon independen dapat ikut dalam bursa pemilihan kepala daerah sebagaimana berlaku untuk beberapa daerah istimewa?
Dengan dapatnya calon independen pilihan rakyat mengikuti bursa pemilihan kepala daerah, maka telunjuk rakyatlah yang berkuasa. Pada titik ini, telunjuk kekuasaan adalah koridor hukum yang dibangun bersama prinsip egaliterian. Akankah? ***
Penulis Pimpinan BT/BS Bima Medan.