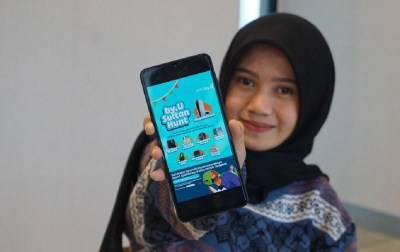Oleh: Deddy Kristian Aritonang.
Razia buku oleh TNI, Kejaksaan dan Polri kembali terjadi. Pertama di dua toko buku berlokasi di Ki Ageng, Kediri, Desember 2018 silam. Saat itu TNI menyita buku-buku yang dianggap berhaluan kiri, yaitu (1) Empat Karya Filsafat, (2) Menempuh Jalan Rakyat (karya DN. Aidit), (3) Manifesto Partai Komunis (karya Karl Marx dan Fredrich Angels), (4) Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan (karya Soe Hok Gie), (5) Benturan NU PKI 1948-1965, (6) Gerakan 30 September 1965 Kesaksian Letkol PNB. Heru Atmojo, (7) Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, (8) Oposisi Rakyat, (9) Gerakan 30 September 1965, (10) Catatan Perjuangan 1946-1948, (11) Kontradiksi MAO-Tse-Tsung, (12) Negara Madiun, (13) Islam Sontoloyo (karya Soekarno), (14) Sukarno, Orang Kiri, Revolusi, & G30S1965 (karya Ong Hok Ham) dan (15) Komunisme ala Aidit.
Selang sebulan kemudian, di Padang, sebuah toko buku mengalami nasib serupa karena menjual buku-buku berjudul Kronik 65, Jas Merah dan Mengincar Bung Besar. Lalu akhir Juli 2019 lalu, dua orang pegiat literasi terpaksa berurusan dengan polisi karena membawa empat buku, yakni (1) Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara, (2) Sukarno, Marxisme dan Leninisme: Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia, (3) Menempuh Jalan Rakyat, dan (4) D.N Aidit Sebuah Biografi Ringkas. Disusul kemudian pada 04 Agustus 2019, razia buku di toko buku Gramedia Trans Mall Makassar dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia. Uniknya, selain bukan dilakukan oleh aparat, salah satu buku berjudul Pemikiran Karl Max: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme karya Franz Magnis-Suseno yang dirazia sekelompok orang itu justru merupakan kritik terhadap Marxisme. Dengan kata lain, mereka merazia buku-buku itu secara sembrono karena tidak memahami isinya sama sekali.
Tindakan penyitaan maupun razia buku-buku beraliran kiri dan dianggap berseberangan dengan ideologi Pancasila merupakan sebuah kemunduran. Bisa kemunduran berpikir. Bisa juga kemunduran menyikapi peradaban yang sudah jauh lebih maju. Boleh jadi niatnya memang baik: agar masyarakat tidak terpapar ideologi komunis. Tapi, di tengah-tengah gencarnya kampanye literasi yang dikumandangkan berbagai lembaga pendidikan kita, tindakan razia apalagi sampai menyita dan melarang akses terhadap buku-buku itu jelas merupakan cara yang salah kaprah.
Indeks Minat Baca
Sangat aneh apabila buku-buku yang dianggap berhaluan kiri membuat masyarakat resah. Seharusnya yang menjadi keresahan kita adalah pencapaian literasi bangsa ini yang begitu buruk berdasarkan kajian-kajian lembaga internasional. Sebut saja UNESCO pada tahun 2012. Badan PBB itu memperlihatkan indeks minat baca bangsa kita yang cuma 0,001%. Ini berarti dari 1000 penduduk Indonesia, hanya satu orang yang suka membaca.
Kemudian pada tahun 2015, penelitan PISA (Programme for International Student Assessment), rilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), melaporkan peringkat literasi Indonesia yang cuma duduk di urutan ke-62 dari 70 negara. Lalu setahun kemudian, Central Connecticut State University (CCSU) dalam laporan yang berjudul “The World’s Most Literate Nation” menempatkan peringkat literasi kita di posisi ke-60 dari total 61 negara, atau satu tingkat lebih baik dari Botswana, negara di Afrika bagian selatan.
Merazia buku sama saja dengan mengkebiri hak-hak manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara luas. Ya, pada konteks ini paham komunisme harus dipandang sebagai ilmu pengetahuan terlepas dari eksistensinya yang tidak sesuai dengan ideologi kita, Pancasila. Sebab, untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif atas alasan mengapa komunisme bertentangan dengan Pancasila, harus dengan cara memahami secara utuh apa dan bagaimana paham komunisme itu sesungguhnya melalui membaca. Bukan dengan modal diceritakan secara turun temurun seperti dongeng pengantar tidur.
Melarang akses bacaan terhadap buku-buku berhaluan kiri hanya akan memberikan kesan kuat bahwa komunisme dan sejarah kelamnya di negeri ini seperti mitos dan kisah fiktif belaka. Generasi muda yang lahir jauh sesudah peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965 tidak pernah menyaksikan itu semua. Maka mereka harus dibekali dengan pengetahuan sejarah yang komplit. Dan caranya tentu dengan memberikan kajian terhadap literatur yang relevan dengan itu. Tujuannya adalah agar mereka tahu betul bagaimana upaya-upaya keji yang pernah dilakukan para pemberontak itu untuk merongrong Pancasila.
Membaca buku-buku berhaluan kiri tidak dapat dijustifikasi secara sepihak bahwa pembacanya akan secara otomatis mengusung ideologi itu. Pada konteks yang berbeda, kita bisa melihat kehidupan sehari-hari. Kita disuguhkan rambu dan peraturan lalu lintas. Kita membaca aturan-aturan itu setiap hari. Tapi ternyata setelah membacanya kita tidak serta merta menjadi individu yang benar-benar taat akan aturan lalu lintas. Sebagai manusia yang beragama, kita juga relatif rajin membaca kitab suci agama yang kita anut. Tapi ternyata setelah membacanya kita juga tidak secara otomatis menjadi penganut agama yang taat.
Vonis Sepihak
Dengan memberikan akses bacaan, sekalipun itu tentang ideologi-ideologi kiri, sesungguhnya kita sedang membuka ruang bagi ketajaman berpikir dan kemampuan untuk mengolah informasi dengan nalar yang kritis. Larangan membaca buku-buku itu malah secara tidak langsung memvonis intelektualitas generasi muda kita. Artinya, secara sepihak, para generasi muda telah ditempatkan pada posisi yang rentan terpapar komunisme. Mereka sedang diberi label sebagai generasi yang tidak memiliki kecakapan bernalar. Menyakitkan bukan?
Kita harus membangun optimisme bahwa Pancasila adalah ideologi final. Dan komunisme, terutama di Indonesia, hanya sebatas sejarah. Pemberian kesempatan melahap buku-buku aliran komunis, apalagi lewat diskusi akademis dan forum-forum ilmiah akan mengekspos sisi-sisi lemah ideologi itu sehingga akan semakin menguatkan kesadaran masyarakat bahwa Pancasila tidak perlu diutak-atik lagi. Dengan demikian buku-buku yang dilarang itu seharusnya dianggap sebagai referensi varian saja atau untuk tujuan memperkaya literasi semata. Tidak lebih dari itu.
Lagipula, sejak 13 Oktober 2010, UU No. 4/PNPS/1963 yang melarang buku-buku tertentu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau pun aparat, atau ormas tertentu keberatan dan ingin memberangus buku-buku yang dianggap ‘membahayakan’ atau ‘meresahkan’, caranya adalah lewat mekanisme pembuktian di pengadilan. Merazia, melarang atau menyita buku tanpa proses peradilan sudah dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang. Lebih dari itu, cara-cara tersebut sangat identik dengan warisan Orde Baru.
Masih ingatkah kita dengan penulis hebat, almarhum Pramoedya Ananta Toer? Novel Tetralogi Buru miliknya yang tersohor itu sempat membuatnya menjadi pesakitan. Dia dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan selama belasan tahun terutama pada masa Orde Baru karena dianggap mengusung ideologi komunis. Tak hanya itu, orang-orang yang ketahuan memiliki dan membaca novel-novel itu juga akan mengalami takdir serupa. Padahal hingga saat ini, belum ada bukti-bukti konkrit yang menyatakan Pram sebagai komunis. Ironisnya, novel itu pernah mengantarkan beliau menjadi nominator peraih Nobel Prize.
Kalau pun buku-buku itu dilarang beredar hanya karena alasan mencegah kebangkitan komunis, masayarakat tetap bisa dengan mudah mencari informasi lewat akses internet. Di era digital sekarang ini, buku-buku dalam format e-book banyak tersedia dan bisa diperoleh dengan sangat mudah.
Pada akhirnya, kita tidak boleh gegabah dan terlalu phobia begitu melihat buku-buku bernuansa komunis. Apalagi negara-negara dengan ideologi itu justru sekarang tidak lagi sefanatik dulu. Tiongkok misalnya. Negeri itu dikenal sebagai penganut komunis tulen dari dulu hingga sekarang. Tapi belakangan arah dan kebijakan ekonomi mereka justru berkiblat pada sistem liberal dan kapitalistik. Kini mereka menjadi salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia. Jangan sampai kita terperangkap dalam kerangka berpikir sempit yang membuat kita sulit bergerak menuju kemajuan. ***
Penulis adalah kolumnis lepas, guru SMP/SMA Sutomo 2 Medan dan dosen PTS.