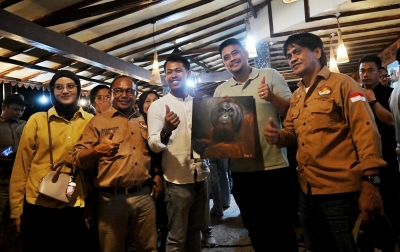Oleh: Mihar Harahap
Negeri di atas kabut. Sulit memadamkan jiwa terlecut luka-setia melupa rupa. Cinta terbang melabuhkan birahi di teluk sunyi. Angin miris mengoyak kalbu di senyap pekat
Kalau jiwa sudah terlecut, tercambuk, terbakar, maka sulit dilucut, dibujuk, dipadamkan. Tidak karena cinta, sebab birahinya sepi di teluk sunyi. Tidak juga karena angin, sebab mirisnya sekat di senyap pekat. Kecuali karena Tuhan: “negeri di atas/kabut. Aku zikirkan rindu di pucuk daun/agar sempurna catatan menuju tuhan/ah!”.
Jadi, negeri di atas kabut itu adalah kekalutan atas kehidupan individu, sosial, politik, ekonomi, budaya, agama yang muaranya pada kekuasaan Tuhan.
Sulaiman Juned, lahir 12 Mei 1965 di desa Usi Dayah, Mutiara, Pidie, Aceh. Menulis sejak 80- an berupa puisi, cerpen, esai, drama dan artikel budaya. Dimuat di surat kabar, majalah, jurnal, buku. Terbitan Aceh, Medan, Padang, Riau, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Jateng, Malaysia dan Brunei.
Pernah menjuarai lomba buku sastra. Antologi lainnya, Podium (1990), Joglo (2006), Ziarah Gempa (2010). Aktif berteater, pelakon dan sutradara. Kini, sebagai dosen ISI Padanganjang Sumbar.
Selalu kita dengar “Negeri di Atas Angin”. Merupakan nama yang beragam peruntukan. Ada nama buku sastra, nama daerah pariwisata, nama asal pewayangan, nama negara dalam hadis nabi dan lainnya. Negeri di Atas Kabut, mungkin belum pernah kita dengar. Walau ‘angin’ dan ‘kabut’, letaknya sama-sama di atas udara. Dia adalah nama buku kumpulan puisi Sulaiman Juned terbitan Disbudpar Aceh (2015). Penyair Aceh yang bermukim di Padangpanjang Sumbar.
Tidak ada kata pengantar penyair, yang mestinya menjelaskan maksud nama itu. Kita pun bebas menafsirkannya. Kalau angin bersifat terbuka, memberi kesegaran dan kedamaian. Kabut, bersifat tertutup, kesenjangan dan penuh kemisterian. Artinya, puisi-puisi dalam kumpulan ini, selain terungkap bagai kabut (sesuai nama buku), juga seperti angin (tak sesuai nama buku). Bertumpang tindih simbol kenisbian, kemisterian,kelugasan dan aroma kesegaran.
Kehadiran puisi pun sempat mengecoh pembaca. Memang tidak ada puisi sesuai nama buku dan hal itu sah-sah saja. Begitu, ada puisi “Kabut” (seperti petikan di atas) yang isinya tentang negeri di atas angin. Kemudian, ada kata-kata kabut di beberapa larik puisi.
Kebanyakan puisi bermakna kabut, tertutup, sehingga sulit untuk dikuakkan. Karena itu, diperlukan konsistensi penyair terhadap judul puisi dengan nama antologi agar tidak mengganggu kenikmatan pembaca.
Adriyandi, S.Sn, mendesain sampul buku melukiskan awan, bukan angin atau kabut. Layaknya sinetron Kera Sakti dari Cina yang mengenderai awan. Di atas awan itu, ada tiang dan seseorang yang memainkan vilon cello (musik gesek keluarga biola).
Mungkin tiang di udara/awan dapat dimaknakan negeri di atas awan (bukan kabut). Apakah seseorang yang memainkan viloncello itu sudah mewakili puisi secara tepat? Masih umum, abstrak. Belumlah menukik ke dalam puisi.
Ada 157 judul puisi. Diciptakan tahun 2009 (59 puisi), 2010 (41 puisi) dan 2011 (40 puisi). Tahun 2008 (16 puisi) dan khusus tahun 1989 bahkan letaknya di awal (1 puisi). Judulnya “Usi Dayah”.
Bukan lantaran puisi ini terbaik, melainkan Usi Dayah itu kampung penyair. Dia berpesan, siapapun melewati gunung Seulawah, titip rindu karena kampungnya di kaki gunung itu. Tanyanya: ”masihkah bilik para datu/mengalirkan air kasih-Nya”. Maksudnya, kampung yang sangat relegius.
Menariknya antologi ini, pertama, ada 115 judul diciptakan di Sumbar (Padang Panjang, Bukit Tinggi, Padang, Batusangkar). Cuma 18 judul diciptakan di Aceh (Banda, Takengon, Kutacane, Pidie). Artinya, bak pepatah Minang, di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung. Penyair Aceh mencipta di Padang. Kedua, 24 judul lagi diciptakan di dalam dan luar negeri. Dari Sumatera, Jawa, Papua, hingga ke Malaysia. Brunei, Japang, German. Pertanda, wilayah pengarang menembus negara.
Jumlah puisi pendek dan puisi panjang hampir sama. Puisi pendek 71 judul di mana 59 judul (5 baris) dan 12 judul (6 baris). Puisi panjang ada 86 judul (7 baris dan seterusnya).
Perbedaan umum kalau puisi panjang larik lebih bermakna denotatif, sedang puisi pendek bermakna konotatif. Lebih baik membaca puisi panjang (penyair sering membacakannya) ketimbang puisi pendek. Leon Agusta menyebut puisi auditorium, puisi konkrit, jelas, lugas dan mudah dipahami pendengar.
Puisi pendek, misal, satu judul “Padangpanjang” tetapi 37 puisi. Di antaranya: ”aku/sedang memungut kabut”(Satu). “Aku/mengintip bulan/sunyi di pikiran/ah!” (Sepuluh). “Hujan dinginkan jiwa. Aku/berdiang di api yang telah/padam/ah! ”Duapuluh Dua). ”Aku/memanggang daun/di atas tungku/jadi/bara/ah!” (Tigapuluh Tujuh). Puisi tentang aku, aku-puisi versus aku-peyair. Di sini, kita melihat aku-puisi, bukan aku-penyair, di mana terjadi kontradiksi di antara keduanya.
Di Jakarta, puisinya: ”di koyak/sepi. Menghitung ombak/dimata-rindu menyusup membelai pucuk rambut/ (aku sunyi dalam keramaian” (Koyak). Di Kuala Lumpur, puisinya: ”mata/bulan. Nanar/menyaksikan luka/bersimaharaja di hati” (Bulan mata). Di Brunei, puisinya: ”anginkah/yang lukiskan pekat. Laut jilati/bulan di atas meja perjamuan” (Lidah Bulan). Terasa aku puisi itu, sangat sensitif, pesimistis, tidak sebagaimana yang dikatakan Musafa Ismail dalam pengantarnya.
Puisi panjang beragam tema, subtema atau sekedar lompatan pikiran-perasaan. Tentang kehidupan yang melelahkan (Lelah). Cinta keluarga, anak-istri (Emak II). Kealaman, gempa, tsunami, tanah longsor yang memakan korban (Ziarah Gempa). Tentang ketuhanan yang melingkupi segala aspek kehidupan (Rindu). Tidak harus puisi ketuhanan, melainkan hal-hal dalam kehidupan lainnya, pun selalu muncul nilai-nilai keimanan dan ketuhanan (Jika Air Berumah di Pasie Laweh).
Mengeritik kekuasaan: ”Pemimpin sering menakut-nakuti/rakyat dengan kekuasaan dan jabatan” (Takut). Di era reformasi, demokrasi dan globalisasi dewasa ini, masih juga terjadi pemimpin mengintimidasi rakyatnya. Termasuk soal korupsi: ”di negeri para/koruptor/kita dipaksa jadi rumput oleh pengembala sapi” (Cemas). Begitu mencemaskan, bila rakyat adalah makanan (rumputnya) para koruptor (pengembala sapi). Karena itu, sangat perlu komisi pemberantasan korupsi.
Mengeritik media: ”...televisi mengantarkan permusuhan ke rumah-rumah/ mengaburkan arti persahabatan sejati.../terkontaminasi pemahaman kebebasan... (kita diperbudak hidup dalam menghidupi hidup)” (Tersingkir). Televisi mengingkari fungsi sebagai media pendidikan bahkan seakan mengancam tradisi dan peradaban. Pemahaman pemirsa kepada Pancasila, kebudayaan dan agama terkontaminasi dengan pemahaman kebebasan yang melanggar nilai-nilai luhur tersebut.
Sulaiman Juned, menutup antologi puisi dengan judul “Bersebelas”. Petikannya: ”berbebelas/kita-menghitung tasbih pada bibir angkuh/menyekap jejak di tubuh zikir-pikir meluruh/menaburkan mawar basuh muka bersihkan khilaf (api meluluhkan isi kepala)”. Sebagai penyair yang santun lagi dramatis, dia mohon maaf atas kekhilafan. Mari menghitung tasbih, berzikir-pikir atau membasuh muka agar makna puisi yang merupakan nasehat ini dapat diterima pembaca dengan baik.
Mencermati antologi ini, kita mencatat lima hal. Pertama, pengungkapan puisi, pernyataan dahulu, baru keterangan. Contoh pernyataan: ”anginkah”, maka keterangannya: ”yang lukiskan pekat /di hati. Laut jilati/bulan di atas meja perjamuan” (Lidah Bulan).
Atas pernyataan: ”angin”, maka urai keterangan: ”miris-mengoyak cinta/tergadai kabut (satu) dan dua: ”miris-melupa rupa/di teluk sunyi/ ah!” (Miris). Cara seperti ini sesungguhnya teknis menulis prosa, misalnya bentuk prosa liris.
Kedua, mengakhiri puisi, selalu menggunakan kata “ah”. Atau kalimat dalam kurung. Makna beragam, tergantung bait/baris lariknya. Bukan kebetulan melainkan kesengajaan. Perlu kajian lebih dalam.
Ketiga, selalu mengulang idiom, frasa, kalimat, pada puis-puisi. Misalnya ”kita belum mampu memaknai petuah-Nya” atau “kita tak mampu membaca isyarat alam”. Keempat, menggunakan garis tengah untuk memisahan di antara dua puisi dalam satu halaman, terasa agak mengganggu.
Kelima, menggunakan ejembemen (pemenggalan suku kata atau kata) dalam bait atau baris puisi. Memang kita paham licensia poetica, hak seorang pengarang untuk melanggar tatabahasa, termasuk soal ejembemen ini.
Pelanggaran itu dilakukan tidaklah semena-mena. Harus ada alasan yang menguatkan sehingga demi alasan itu, maka dilakukan pelanggaran. Misalnya demi mencapai efek bunyi, pengertian dan lainnya. Jika tak ada, maka seyogianya tidak perlu.
Penulis; kritikus sastra, budaya, mpr-oos, ketua fosad, pengawas dan dosen uisu.