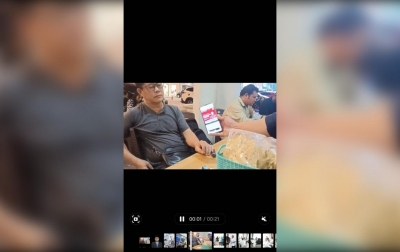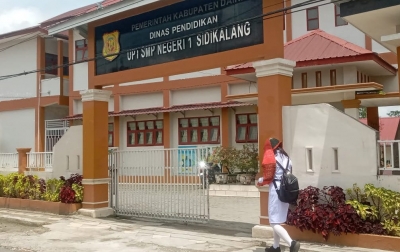Oleh: Saripuddin Lubis
PANTUN sebagai karya sasra lama, menyimpan beberapa kelebihan dibandingkan dengan karya sastra lama lainnya, seperti syair dan gurindam. Syair dirasakan terlalu panjang, sebaliknya gurindam terlalu singkat ketika digunakan. Permainan persajakan dalam pantun pun, terasa lebih variatif dibandingkan kedua karya sastra lama yang lainnya.
Di sisi lain, masyarakat ternyata masih memerlukan karya sastra untuk dijadilan alat kontrol terhadap persoalan sosial budaya di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu karya sastra yang saat ini masih timbuh subur adalah pantun. Setidaknya masih digunakan saat membuka dan menutup sebuah acara seremonial. Seorang pejabat pun ketika memberi sambutan juga masih memanfatkan pantun.
Mencermati persoalan kehidupan yang semakin rumit dewasa ini agaknya membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Bahasa-bahasa lugas memang cenderung ditanggapi lebih cepat dan reaktif.
Ada rasa takut ketika harus menyampaikannya. Keadaan itu melahirkan sikap apatis terhadap sikap kritis, terutama terhadap ketimpangan sosial budaya di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat pun banyak yang melakukan aksi diam di tengan segala ketimpangan sosial-budaya yang ada di sekitarnya tadi. Ini merupakan gejala psikologis yang tidak sehat dalam hegemoni kebermasyarakatan yang terus berkembang secara dinamis.
Pantun sendiri merupakan karya sastra puisi lama Indonesia. Dalam KBBI pantun didefinisikan sebagai bentuk puisi Indonesia (Melayu). Tiap bait (kuplet) biasanya terdiri atas empat baris yang bersajak (a-b-a-b), tiap larik biasanya terdiri empat kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan (sampiran) saja dan baris ketiga dan keempat merupakan isi.
Dalam bahasa Jawa Barat kita mengenal istilah paparikan. Di Tapanuli kita mengenal pula istilah umpasa. Tentu daerah lain di Indonesia juga memiliki karya sastra serupa pantun.
Selama ini di Sumatera Utara kita mengenal pantun hanya digunakan untuk kepentingan acara-acara seremonial semata. Seorang pejabat atau siapa saja ketika membuka dan menutup sebuah sambutan dilakukan dengan membaca pantun. Pantun seperti ini yang lazim kita dengar misalnya;
Kalau ada sumur di lading
Boleh kita menumpang mandi
Kalau ada umur yang panjang
Boleh kita berjumpa lagi
Atau ada juga pantun permohonan maaf
Kalau ada jarum yang patah
Jangan disimpan di dalam peti
Kalau ada kata yang salah
Jangan disimpan di dalam hati
Masih ada pantun yang juga lazim kita dengar seperti:
Berdebur ombak berdebur
Berdebur hingga ke pantai
Bersyukur kita bersyukur
Sebab acara sudah selesai
Semua pantun tersebut berisi pemanis sebuah sambutan. Padahal kita juga mengenal jenis pantun yang lain seperti pantun anak-anak, pantun orang muda/remaja dan pantun orang tua.
Pantun sebagai karya puisi lama umumya berisi nasihat dengan kata-kata arkais (bahasa lama). Ada juga pantun yang berlebihan menggunakan kata-kata, bahkan cenderung menyalahi pakem-pakem yang ada dalam pantun. Hal serupa ini dapat kita saksikan pada acara-acara hiburan di televisi. Para pengisi dapat dikatakan membuat pantun yang kurang bernilai, misalnya ada pantun seperti ini:
Ada nenek-nenak bawa becak
Kepala lu petak
Ini sangat tidak logis dan tidak etis. Beberapa kalangan menganggap ini sesuatu lucu, padahal uangkapan tersebut sungguh tidak bernilai.
Pantun sebagai karya sastra sebenarnya dapat juga dijadikan sebagai salah satu alat kontrol penyimpangan sosial dan budaya. Dengan menggunakan pantun, sindiran atau kritik menjadi lebih lunak dan mudah diterima, apalagi penyampaian dilakukan dengan santun. Kritik yang awalnya terasa pedas, ketika dibuat jadi pantun menjadi lebih lebut, ramah tapi mengena.
Mari kita cermati pantun Nirwana Sinaga, seorang guru SMK dari Tobasa berikut.
Kota Parsoburan penghasil andaliman
Rasa andaliman pedas getir di lidah
Pilu rasanya melihat anak tak sopan
Didikan anak berawal dari rumah.
Kita baca pula pantunnya berikutnya.
Kota Jakarta kota metropolitan
Surga impian para perantau
Kusapa “Horas apa kabar kawan”
Hampa hatiku dibalas “fine, thank you”
Kedua pantun di atas berisi kritik terhadap persoalan sosial dan budaya. Pantun pertama mengkritik pendidikan yang dilakukan oleh orang tua tethadap anaknya. Nirwana menjelaskan bahwa kesalahan anak yang tidak mengenal sopan santun adalah kesalahan orang tua.
Pada pantun kedua si penulis pantun mengkritik perilaku berbahasa masyarakat yang cenderung tidak lagi mencintai bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Masyarakat begitu bangga menggunalan bahasa asing dalam tindak tutur mereka.
Pantun senada dapat kita lihat seperti tulisan Risdine Liline, seorang guru SMK di Kota Binjai.
Ayah ibu sepasang pengajar
Gaya mereka buat terkesima
Sopan santun harus diajar
Keluargalah sekolah pertama
Pondasi pertama pendidikan menurut Risdine adalah keluarga di rumah. Kita lihat sebuah pantun kritik dari Dhani, seorang guru dari Labuhan Batu. Katanya begini;
Labuhan Bilik Sungai Berombang
Dayung sampan hingga tepian
Sungguh banyak jalan berlubang
Cemanalah perasaan puan-tuan?
Sebuah pertanyaan bagi warga Sumatera Utara mengenai jalan berlubang yang menyebar di semua penjuru negeri. Pada akhir pantun sebuah pertanyaan retoris disampaikan Dhany. Lihat pantun kedua dari Dhany berikut yang lebih pedas sekaligus menggelikan;
Ke Batubara melihat kapal
Anak-anak mencari kepah
Jalan sudah sulam-tambal
Macam celana Pak Ongah.
Masih tentang jalan yang rusak, kita baca pula pantun Karnadi seorang guru di Simalungun berikut ini;
Minum teh di sore hari
Tehnya asli dari Sidamanik
Jalan rusak di pelosok negeri
Membuat masyarakat jadi panik
Pantun-pantun yang berisi kritik sosial. Kalaulah pantun tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri para pemangku kepentingan, tentu akan menjadi masukan yang berarti. Tanggapannya, dibandingkan dengan penyampaian secara lugas (langsung), akan lebih positif dan ditanggapi dengan nuansa berbeda.
Pantun sepertinya memang tetap diminati, sayangnya hanya untuk hal-hal yang terbatas seperti acara-acara seremonial semata. Kehadiran pantun masih sebagai pemanis pidato dan kata sambutan.
Untuk kalangan muda, kehadiran pantun saat ini hanya sebatas ajang lomba berbalas pantun. Ajang yang jangankan secara kualitas, secara kuantitas pun masih sungguh langkanya. Dilematis, saat para pejabat selalu menggunakan pantun sebagai pelengkap pidato/sambutan, namun perhatian terhadap perkembangan pantun amatlah sedihnya.
Pantun semestinya terus dikembangkan seperti asal muasalnya, seperti pantun anak-anak, pantun remaja, dan pantun orang tua. Harus dirancang sebuah konsep agar pantun diminati anak-anak, remaja dan orang tua. Dengan mengembalikan pantun seperti konsep asalnya, maka diharapkan pantun akan dapat kembali tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.
Lebih penting saat ini, pantun seharusnya dikembangkan pula sebagai salah satu alat kontrol penyimpangan sosial dan budaya.
Penulis; Pengasuh Sanggar Rumah Cerita dan Ketua DPW AGBSI Sumatera Utara.