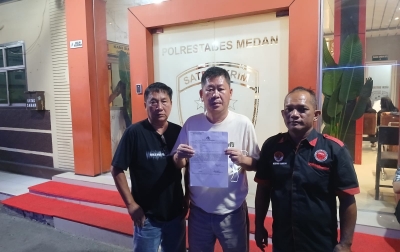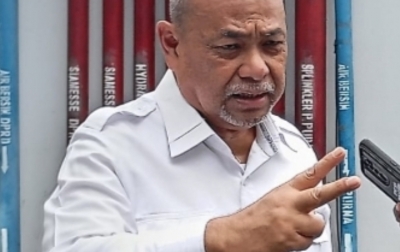Sebelum muncul roman Medan, pembaca karya fiksi di Medan umumnya membaca karya roman yang disebut Sastra Melayu Tionghoa. Ciri khasnya, roman-roman itu menggunakan bahasa Melayu rendah. Di sisi lain ada juga karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu tinggi, yang sering disebut Sastra Balai Pustaka.
Lalu ada pengarang seperti Mas Marco dan Semaoen yang menulis roman yang disebut literatur sosialis. Pada ketiga fase inilah, muncul roman Medan – majalah namun berbentuk buku saku. Di antaranya Loekisan Poedjangga, Doenia Pengalaman, Suasana Baru, Poestaka Islam, Bintang Roman, dll.
“Roman Medan hadir saat kebudayaan Indonesia masih kosong,” ujar Koko Hendri Lubis. Roman Medan mengandung sebuah identitas kultural khas Medan yang ikut menyumbang dan memerkaya kebudayaan nasional.
“Karena itu roman Medan penting untuk penelitian sejarah sastra kita. Lewat roman Medan, kita bisa mengetahui selera masyarakat Medan saat itu atau gaya hidup yang berkembang,” ujarnya. Pada awalnya roman Medan terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar, seperti karya Matumona, Dja Umenek Jadi-jadian di surat kabar Pewarta Deli, 1933.
Dimuat secara bersambung, tentu butuh kesabaran pembaca untuk tahu akhir cerita. Keadaan itu membuat banyak pembaca penasaran. Itu sebabnya roman Medan lalu muncul dalam versi majalah yang dicetak dalam bentuk buku. Inilah awal kelahiran roman Medan.
Koko mencatat, itu terjadi Agustus – September 1938 lewat roman Topeng Hitam, karya A Damhuri yang dicetak Percetakan Poestaka Islam dan roman Roeh Bertjerita, karya Joesoef Souyb. Koko memang pernah mendapat informasi bahwa pada 1933, Matumona pernah menerbitkan roman Harta Karoen, tapi sampai sekarang ia belum pernah melihat secara fisiknya.
Pada 1942, saat Jepang menjajah, roman Medan sempat vakum. Waktu itu Jepang membuat kebijakan, semua kegiatan kebudayaan harus dilakukan lewat lembaga kebudayaan baru yang mereka bentuk, mamanya Bunkaka. Mereka menerbitkan majalah Minami.
Tak semua pengarang roman Medan mau bergabung menulis di Minami. Beberapa pengarang seperti Amir Hamzah dan Hamka menulis di Minami. Jadi antara 1942 – 1945, roman Medan praktis tak diproduksi lagi. Baru menjelang 1948, kembali muncul sampai berakhir pada 1965.
September 2017, saat mengikuti program residensi penulis selama 2 bulan di Asian Library, Leiden, Belanda. Koko berhasil memindai ratusan roman Medan dalam bentuk digital. Koko juga banyak mendapat informasi berharga tentang roman Medan.
“Roman Medan ada yang sekali dicetak 5.000 eksemplar, bahkan karya Joesoef Souyb sampai 15 ribu eksemplar. Itu bisa disebut sebagai zaman keemasan industri kreatif di Medan saat itu,” ujarnya.
Jika akhirnya roman Medan tidak diperhitungkan dalam pembentukan identitas kultural bangsa Indonesia pasca-PD II, itu karena pusat pemikiran budaya saat itu dominan ada di Jakarta. Para pengarang di Jakarta membangun jejaring dengan penulis luar negeri, sedang seniman di Medan berjejaring ke Singapura dan Malaysia, dan kurang peduli dengan perkembangan sastra yang terjadi di Jakarta.
Di mata pejabat Balai Pustaka, roman Medan dinilai telah keluar dari pakem roman zamannya. Aspek antikolonialisme yang ada dalam roman Medan membuat para pejabat Balai Pustaka tak suka.
“Matumona dan Surapati pernah ditangkap Belanda dalam kapasitas sebagai aktivis politik, bukan karena roman yang mereka tulis,” katanya.
Singkatnya, roman Medan dalam pandangan Koko dipandang melawan kanonisasi sastra versi Balai Pustaka. Karya sastra menurut Balai Pustaka harus netral. Tapi itulah yang diabaikan para pengarang roman Medan. Sebagai ganjarannya, roman Medan akhirnya tak tercatat dalam sejarah sastra resmi.
Para pengarangnya umumnya juga bekerja sebagai wartawan. Beberapa di antaranya, Matumona, Martha, Joesoef Sou’yb, Roma Nita, M Kasim, Aziz Thaib, Rohana, Z St Alamsjah, Tamar Djaja, Bachtiar Joenoes, D Chairat (Rahman - Decha), Hamka, A Damhoeri, S Djarens, Surapati, Dali Moetiara, Matu Mona, Z Jusuff, DE Manoe Turie, Abu Zul, Yusdja, Taher Samad, I Made Otar, dan MN Sulan.
Kepada merekalah kita sejatinya memiliki sebuah utang sejarah. Utang yang harus segera dilunasi, yakni dengan tebusan mengakui karya-karya mereka sebagai bagian narasi sejarah sastra Indonesia modern. (J Anto)