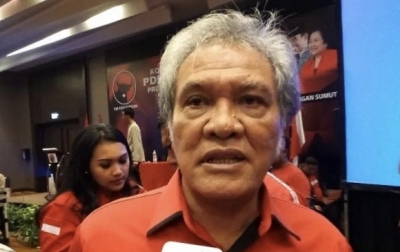Oleh: Radja Sinaga
DI era industri 4.0 orang-orang menginginkan sesuatu dengan cepat, praktis, dan tentunya menguntungkan. Dalam sekali tindakan menghasilkan lusinan benda. Di suatu waktu yang biasa, di mana daun-daun berwarna kuning belum ranggas dari tangkainya. Api menolak menjadi diksi dalam puisi yang mengumpamakan rindu berkobar, atau hujan yang sebenarnya hanya proses geografis. Para pemikir mengelu-elukan manusia sepatutnya menjadi monitoring saja! Akhirnya terciptalah robot-robot dan mesin-mesin.
Ini langkah awal menyentuh peradaban. Bayangkan bila manusia hanya mampu membuat beberapa benda dalam sehari. Revolusi industri ini mesin-mesin yang kami ciptakan bisa melipatgandakan hasilnya. Begitulah kira-kira kalimat pembuka yang kau baca di koran ibu kota saat negara ini mulai sibuk dengan industri 4.0. Sebelum bacaan itu selesai kau telah melenggang jauh meninggalkan rumah. kau biarkan koran itu tidur di lantai teras kosmu.
Bukan kau tak ingin membaca berita itu. Sepagi ini kau harus menuju ke tempat konsumen. Kau pekerja yang profesional, terlebih saat ini sangat sulit menjumpai orang yang ingin menggunakan jasamu. Ketimbang membaca berita yang makin menyayat hati, lebih baik kau pergi berkerja.
“Toh dengan membaca kelaparanku tetap menganga,” begitu kau memotivasi diri sendiri sambil melampiaskan kekesalan kepada industri 4.0.
* * *
Tanganmu tak lagi mampu menyaingi mesin-mesin jahit. Jari-jarimu yang hanya sepuluh terlalu kecil dihadapan satu jari yang mengetuk layar mesin jahit. Lambat laun orang-orang yang sering memesan kepadamu untuk dibuatkan pakaian atau mereparasi pakaian kini menghilang serupa pejuang-pejuang reformasi.
Kini mesin jahit yang kau punya berdebu. Tempat duduk yang biasa membuat bokongmu nyeri tak lagi pernah kau duduki, kecuali dalam waktu iseng kau duduki beberapa saat sekadar mengingat kenangan. Kenangan yang tak lekang di bilik ingatanmu. Di mana waktu yang membeku itu pernah membuat hidupmu lebih bermakna di dunia.
Saat kau duduki bangku mesin jahit itu. Kepalamu berubah menjadi kereta api yang melintasi stasiun-stasiun waktu. Suara klakson kereta api seperti bunyi mesin jahit. Gemertak roda kereta api bak lehermu yang linu.
Di bawah meja mesin jahit, di samping pintu kosmu, lamat-lamat kau tatap benang dan jarum yang tersusun rapi dalam kardus. Sempat tanganmu hendak meraih benang dan jarum itu, tetapi kauurungkan seketika. Bukan karena kau tak tahu lagi bagaimana caranya menjahit. Bukan! Jika saja ada orang datang untuk memintamu menjahit baju atau menambal pakaianya, kau masih sanggup. Jahitanmu tak berubah, rapi seperti kenanganmu saat ibumu tanggal. Hanya mesin jahit itu yang masih tersisa untuk sekadar mengenang.
Kau bawa mesin jahit itu dari kampung setelah ibumu dimakamkan. Konon kata ibumu, mesin jahit itu sudah ada saat nenekmu masih kanak-kanak. Setelah kembali lagi ke kota, kau belajar bagaimana mengoperasikan mesin jahit itu. Berulang kali jarimu tertusuk jarum. Tak ratanya jahitanmu. Sesekali pun tanganmu menolak berhenti.
Pernah suatu malam selepas aku pulang kuliah dan mampir ke kos temanku. Bergema suara mesin jahit.
“Dari mana datangnya?” kataku saat kami asyik membicarakan wanita depan kos temanku yang selalu berpakaian terbuka.
“Mungkin habis menjajakan tubuh.”
“Maksudmu?”
“Wanita di depan ‘kan?”
“Suara itu, suara mesin jahit!”
“Ah, kalau itu dari sebelah.”
“Sudah lama?”
“Agaknya.”
* * *
Malam-malam selanjutnya, kira-kira seumur cabai setelah aku tahu kau pandai menjahit, semakin giat aku datang ke kos temanku. Tatkala aku rela sendirian di kosnya bila dia pergi. Bahkan tak jarang aku menginap sebab di dadaku menderu ingin mendegar kau memainkan mesin jahitmu. Telingaku seolah tercipta untuk mendengarkan bunyian mesin jahit yang mengalun dari jari-jarimu.
Beberapa kali kutahan bila kantuk menyerang mata. Mulut tak berhenti menyesap kopi dan asap rokok membubung di udara. Aku suka kesunyian begini. Hanya dentang jam dan helaan nafas di kos ini terdengar. Ternyata kesunyian tak begitu membosankan, jika tanganmu tetap memainkan mesin jahitmu.
Malam menggantung. Udara mengeras. Angka-angka di jam berjatuhan. Waktu seperti berlari dan bulan bak dikejar matahari. Jari-jarimu tetap mengalunkan suara mesin jahit. Tepat pukul tiga, tak terdengar lagi apa pun. Kesunyian menjelma penjara. Lantas aku menjadi lelaki yang menjilat ludahnya sendiri dan serba skeptis.
Pernah suatu waktu, di sela daun pintu yang masih terbuka, kau berjibaku dengan kain-kain yang jumlahnya seperti revisian skripsiku. Di jam menunjukkan pukul yang berat. Kau masih laten di sana. Kau seperti kesurupan.
“Sesekali berhentilah menggila, mengasihani diri sendiri itu perlu,” sapaku di luar kosmu seraya menghembuskan asap rokok ke segala arah.
Kau hanya tersenyum. Setelahnya wajahmu kau buang kembali ke tumpukkan kain. Kepalaku berusaha mencari kata-kata yang tepat. Kata-kata yang mampu memancing mulutmu berucap.
Setiap kali aku ke kos temanku. Bila pintumu terbuka dan kau masih sibuk dengan kain-kain, kududuk lamat-lamat menatapmu. Tak lupa sesekali aku berkata-kata, meski hanya senyummu dan setelahnya kau palingkan ke kain-kain.
“Barangkali kau perlu menggunakan jasanya,” kata temanku sesaat kutanya bagaimana caranya aku bisa berbicara dengannya. Sebab dari dia, kau memang tak banyak berbicara terlebih ke pria, jika pun kau berbicara dengan prai itu hanya pada orang-orang tertentu.
“Aku tak punya pakaian yang perlu diperbaiki atau menginginkan pakaian baru.”
“Tempa saja dulu, nanti setelah jadi bisa untukku.”
Di malam selanjutnya, sebelum gagang pintu kosmu hangat karena genggamanmu, kutunggu kau di sana. Angin membeku di udara namun tak derak-derak daun berjatuhan - sebab mempunyai kos di tengah kota dan kota selalu mengajarkan mengasingkan pohon-pohon. Mereka seperti hama bagi manusia, terlebih bagi orang-orang yang berada di dinas kebersihan.
Cukuplah sampah-sampah dari ciptaan manusia yang merepotkan petugas-petugas itu, daun-daun berwarna kekuningan dan hijau tak perlu! Dan jika pun pohon-pohon tumbuh di sini, dia tak akan lebih sekadar menjadi wadah wajah orang-orang yang mengemis suara-suara kita di hari yang konon mereka sebut hari demokrasi!
Bulan makin meninggi. Malam mendapatkan dirinya serupa di musim kemarau: tak ada hujan dan tanda-tanda akan gerimis. Tentunya aku senang, sebab tak perlu kutuliskan narasi seperti cerita-cerita pendek lainnya yang selalu saja datang hujan bila seseorang menunggu di luar.
Kelopak mataku mulai menarik-narik. Di kejauhan deru kendaraan mendekat, berhenti di depan pagar kos. Mataku yang sayup, rekah kembali. Beberapa saat setelah kau bercakap-cakap dengan orang yang mengantarmu, kau membuka gerbang. Bulan dengan cahaya pendar memancarkan bayangamu. Kau tersenyum dan aku hanya menggangguk kecil diselingi senyuman tipis.
“Bisakah kau menempa bajuku?” tanyaku sebelum tanganmu tuntas memutarkan kunci kos. “Aku ingin sebuah kemeja berlengan panjang,” lanjutku. Lama kau menatap, lalu membalas singkat, “Tunggu ya.”
Tak lama kau keluar dengan alat pengukur baju. “Tak perlu diukur, ukurannya segini saja,” kataku sembari memberikan kemaja temanku.
“Kira-kira berapa lama siapnya?”
“Ingin cepat?”
“Tidak juga.”
“Dua minggu, bagaimana?”
Aku hanya mengangguk. “Mari masuk ke dalam dulu,” katamu ketika keheningan hampir menderai di tengah perbincangan kita.
“Tak perlu,” balasku dan bukannya aku tak ingin tapi bila aku masuk kuyakin seluruh ruang tengah telah dipadati kain-kain. Kau masuk dan keluar kembali dengan kursi dudukmu yang sering menemanimu menjahit.
“Jadi kau dari tadi menungguku untuk menempa baju?”
“Ehm, begitulah.”
“Maaf membuatmu menunggu.”
“Hahaha, itu bukan soal. Kudengar kau seorang guru? Guru bahasa Indonesia?”
“Tepatnya calon guru.”
“Kenapa kau tak ambil jurusan tata busana, desainer atau apalah itu?”
“Setiap orang mestinya mencari jalan aman.”
“Ehm, tapi sesekali tampaknya kau perlu mengajariku memainkan mesin jahitmu.”
“Maksudnya?”
“Yah, mengajariku menjahit.”
“Untuk apa?”
“Barangkali, kelak, suatu waktu, aku akan menjahit baju pernikahanmu.”
Lalu untuk pertama kalinya kulihat kau berkelakar. Senyummu mengembang....
* * *
Aku sudah lama tak lagi ke sana, melihatmu berjibaku dengan kain-kain. Semenjak dua minggu setelah kau selesai menjahit bajuku tak lagi kulihat wajahmu. Aku bayangkan lagi senyummu, dan jika waktu itu bisa kucuri senyummu seperti seseorang di cerita lain mencuri senja. Bila takdir, tak harus membuatku bekerja paruh waktu. Hanya untuk memenuhi uang rokok yang melambung tinggi serta tugas negara; menyematkan gelar sebelum angka delapan terinjak.
Kudengar dari temanku kau telah jarang pulang ke kos sebab gagalnya pernikahanmu. Pernikahan? Begitu? Mungkinkah dengan orang yang mengantarmu waktu itu? Di suatu waktu yang biasa, di mana daun-daun berwarna kuning belum ranggas dari tangkainya. Api menolak menjadi diksi dalam puisi yang mengumpamakan rindu yang berkobar atau hujan yang sebenarnya hanya proses geografis. Kupastikan apakah semuanya benar. Temanku tak mengizinkan diriku menginap sebab malam ini dia membawa pacarnya.
“Kali ini saja.”
“Ada yang harus kutuntaskan malam ini dengannya.”
“Aku bakalan menganggap semua itu tak ada.”
“Tetap tak bisa. Lebih baik kau telepon dia. Lalu ajak berjumpa.”
“Telah kucoba, tapi tetap tak ada.”
Sebelum temanku membalas perkataanku. Dari jauh pacarnya berlari kecil menuju kami.
“Ok, begini, kita suruh saja pacarku yang menghubunginya. Dan berdoalah juga dia sudi menganggkat.”
Maka beberapa kali kau kami hubungi. Hingga di depan mata mengatakan menyerah adalah jalan yang mulia. Aku ingin, kuambil telepon genggam pacar temanku, berulangkali. Sampai aku hendak menyerah. Dan dengan iseng temanku menelepon sekali lagi.
* * *
Sepagi ini kau telah pergi, selang dua hari lalu ada sebuah kesepakatan. Kau diminta untuk menjahit sebuah baju. Kau harus menjahitnya di tempat yang telah dikatakan. Di pagi ini, saat kau rela membiarkan koran terbujur di lantai teras kosmu. Hanya untuk menjahit baju dengan orang yang tak kau kenal.
Dahimu mengkerut saat kau telah sampai di tempat yang telah ditentukan. Di depanmu seseorang membuatmu tercenung lama, kau berusaha mengingatnya, tapi ingatanmu hanya mengenal hari-hari ketika kau gagal menikah.
Orang yang di depanmu mengeluarkan bakal baju bewarna putih dari dalam tas yang dibopongnya. Hendak mematikan keheningan.
”Sesekali tampaknya kau perlu mengajariku memainkan mesin jahitmu!”
Kau makin dalam tercenung...