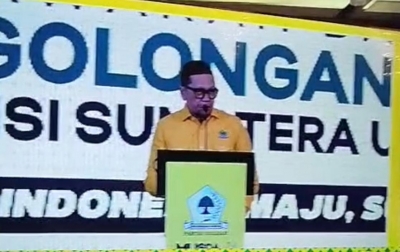Oleh: Deddy Kristian Aritonang.
Akhir-akhir ini entah mengapa kita semakin lama semakin alergi terhadap yang namanya kemajemukan. Dikotomi mayoritas dan minoritas semakin mengikis keharmonisan beragama. Toleransi antar pemeluk agama yang berbeda mulai dianggap hanya sebatas fatsun semata. Pemeluk agama lain yang menjalankan ibadah sering dicap meresahkan dan mengganggu.
Menjadi mayoritas sekarang ini seperti mendapat legitimasi tidak tertulis untuk menindas minoritas. Sebut saja pembubaran Tradisi Sedekah Laut di Bantul, pemotongan nisan berbentuk salib di Yogyakarta, dan yang baru-baru ini terjadi di kawasan Martubung, Medan. Sekolompok masyarakat membubarkan kebaktian jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Filadelfia Griya Martubung pada hari Minggu, 13 Januari 2019. Semua peristiwa intoleran ini terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Maka sudah sepantasnya kita bertanya: bagaimana nasib wajah toleransi di negeri ini pada masa-masa mendatang? Masih bisakah kita hidup damai dan berdampingan walau berbeda keyakinan?
Dalam kasus pembubaran aktifitas ibadah GBI Filadelfia Griya Martubung, dari video amatir yang beredar di media sosial, tampak bagaimana perlakuan kasar secara verbal oleh oknum-oknum yang ditengarai melarang berlangsungnya ibadah kepada para jemaat. Massa berteriak ‘tutup-tutup’ berulang kali dan berusaha masuk.
Informasi terakhir menyebutkan bahwa aktifitas peribadahan GBI Filadelfia yang beralamat di Jalan Permai 4 Blok 8, Griya Martubung itu pada akhirnya dihentikan untuk sementara. Hal ini terjadi setelah adanya ‘kesepakatan’ antara warga Blok 8 Komplek Griya Martubung, Lingkungan 20, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan dengan pihak jemaat GBI Filadelfia yang difasilitasi Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis, di Mapolres Pelabuhan Belawan pada Selasa 15 Januari. Pemko Medan, yang diwakili pihak kecamatan, akan mencari tempat baru bagi jemaat untuk beribadah. (sumber: Medanbisnisdaily.com).
Kata kesepakatan di atas sengaja saya berikan tanda petik. Karena seperti yang sudah-sudah, pihak minoritas akan cenderung mengalah dan menuruti permintaan massa (baca : mayoritas). Mereka harus mau menerima keputusan semisal menghentikan peribadahan di lokasi yang diprotes hingga kerelaan untuk pindah tempat beribadah sesuai tuntutan warga.
Memang harus diakui, tidak ada asap kalau tidak ada api. Pun demikian dengan kasus ini. Dilansir dari Tribunnews.com (Senin, 14/01/2019), pembubaran jemaat yang sedang beribadah disinyalir karena selama dua bulan terakhir, bangunan rumah beralih fungsi menjadi gereja. Izin pendirian gereja juga dilaporkan masih belum ada. Satu sisi memang peribadahan tanpa izin pastinya tidak sesuai regulasi yang berlaku. Tapi di sisi lain, yang menjadi pertanyaan : apakah warga berhak melakukan pelarangan apalagi pembubaran terhadap aktifitas ibadah terlepas dari izin yang belum dilengkapi? Bukankah izin mendirikan rumah ibadah adalah wewenang pemerintah?
Ini yang bagi saya cukup mengkhawatirkan. Sekiranya pihak jemaat GBI Filadelfia memang belum mendapatkan izin pendirian rumah ibadah pun, bukan berarti aktifitas keagamaan mereka bisa dibubarkan. Apalagi dengan gestur-gestur yang provokatif seperti yang terlihat dalam video amatir tadi. Toh, yang para jemaat lakukan hanya sekedar menjalankan ibadah. Kecuali dalam pelaksanaan ritual ibadah itu, para jemaat mengancam kehidupan orang lain atau menyebarkan paham radikalisme yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi NKRI, maka sewajarnya memang harus dibubarkan. Itu pun harus melalui aparat keamanan yang berwenang. Bukan masyarakat sipil! Intimidasi seperti yang dilakukan massa adalah bentuk main hakim sendiri yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.
Seharusnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan komunikasi lintas agama yang manusiawi dan bermartabat. Bukan dengan tindakan, yang menurut saya, rentan memicu terjadinya tindakan anarkis. Lagi pula kebebasan beragama dan menganut kepercayaan merupakan hak semua warganegara seperti yang termakhtub dalam Pancasila dan UUD 1945.
Setiap kali terjadi kasus pelarangan dan pembubaran kegiatan keagamaan, yang selalu menjadi perhatian kita bersama tentunya adalah aturan-aturan yang digariskan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 atau yang dikenal dengan SKB 2 Menteri No 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.
Pada artikel opini saya yang berjudul ‘Hak Minoritas Dikebiri (Lagi)’ di Harian Analisa, Jumat 5 Oktober 2018 silam, saya sudah menuliskan kalau rumusan-rumusan tentang pendirian rumah ibadah dalam aturan ini sangat mempersulit kaum minoritas. Maka tak heran jika SKB 2 Menteri ini sering dianggap pasal karet dan kerap dituntut agar segera dihapuskan. Mengapa dianggap sebagai pasal karet? Karena kenyataannya pasal ini sangat rentan dijadikan tameng oleh pihak-pihak tertentu yang anti pada keberanekaragaman agama untuk melarang pembangunan rumah Ibadah pemeluk agama lain.
Kita mesti menerima realita yang tidak mengenakkan bahwa kebanyakan masyarakat kita masih belum mampu menerima perbedaan dengan berjiwa besar terutama yang menyangkut soal agama. Lihat saja kolom-kolom komentar portal berita online yang memberitakan kasus ini. Komentar-komentar warganet yang kurang lebih menyatakan bahwa minoritas harus tunduk pada mayoritas cukup banyak ditemukan. Ini benar-benar membahayakan sekaligus membuktikan bahwa ‘mabuk agama’ telah merampas nalar bertoleransi yang selama ini kita banggakan sejak dulu.
Ya, dulu kita begitu menghargai perbedaan. Saya teringat pada masa kecil. Ketika di rumah teman saya yang beragama Islam diadakan Wirid, selepas acara, orangtua teman saya suka membagi-bagikan kue-kue pada kami, tanpa memandang perbedaan agama. Demikian pula ketika di rumah saya digelar acara Kebaktian Doa (Partangiangan), maka giliran keluarga saya yang mengantar kue-kue ke rumah tetangga saya yang Muslim. Ini berlaku juga saat Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Bahkan, berbalas kunjungan silaturahmi seperti menjadi agenda rutin yang tidak boleh dilewatkan. Semua saling bersalaman dan saling memaafkan. Kerukunan benar-benar terjaga. Belakangan pandangan intoleran mulai dianut oleh banyak masyarakat kita. Ada saja oknum-oknum yang sering ‘gerah’ melihat eksistensi agama lain di daerah tempat mereka tinggal.
Keberadaan SKB 2 Menteri, suka atau tidak, telah sering mengakomodir sikap intoleran oknum-oknum yang suka menghakimi penganut agama yang berbeda. Mereka merasa punya power yang lebih untuk mengatur kehidupan beragama kaum minoritas di balik aturan ini. Jika pencabutan SKB 2 Menteri tidak segera dilakukan, saya khawatir masalah yang sama akan terjadi di tempat-tempat lain dan ujung-ujungnya akan merenggut sikap toleransi beragama di negara kita.
Dengan kejadian ini, kita harus semakin mewaspadai peristiwa intoleran yang mulai merasuki Kota Medan. Medan selalu dikenal sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi perbedaan agama. Selama ini kebebasan menjalankan ibadah di kalangan umat beragama begitu dihormati. Itulah sebabnya kota ini sering diberi label sebagai miniatur Indonesia. Karena di sini penduduknya benar-benar beranekaragam, baik agama maupun etnis dan saling menghargai satu sama lain. Jika kemudian perilaku intoleran mulai muncul, sudah sepantasnya kita mengambil sikap tegas. Intinya hanya satu : Medan harus tetap toleran! ***
Penulis adalah pemerhati masalah sosial kemasyarakatan.