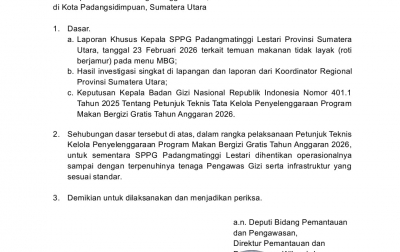Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Pasca lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto 23 tahun lalu, hingga saat ini belum ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia.
Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98, Sahat Simatupang, mengatakan bahwa hari ini, tepat 23 tahun lalu, ribuan mahasiswa dan rakyat turun ke jalan mendesak reformasi politik, ekonomi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Soeharto dan Orde Baru (Orba) dianggap gagal.
"Hingga kemudian pada 21 Mei 1998, Soeharto lengser dari kekuasaannya. Desakan reformasi sistim politik dan ekonomi menggema dimana-mana," kata Sahat, Kamis (20/5).
Namun, sambungnya, melihat perkembangan pasca 23 tahun Soeharto lengser atau yang dikenal sebagai era reformasi, Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 berkesimpulan bahwa lonceng kematian reformasi sudah terdengar.
"Kematian kawan juang kami Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie, Mahasiswa Trisakti serta korban kekerasan dan penembakan saat unjuk rasa Mei 98 di Medan, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Makassar dan kota lainnya seakan sia-sia," ucapnya.
Sahat menuturkan, sampai saat ini Presiden Jokowi, mantan Presiden SBY serta mantan Presiden Megawati Soekarno Putri tidak memperlihatkan keseriusan dalam menuntaskan secara hukum kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan mahasiswa lainnya.
"Padahal Presiden Jokowi dan kedua mantan presiden tersebut memiliki kemampuan politik mendorong peradilan kepada pelaku penembakan mahasiswa," tuturnya.
Oleh sebab itu, Sahat menegaskan bahwa Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 menyatakan sikap agar Presiden Jokowi menepati janji politiknya dalam menuntaskan penembakan mahasiswa Trisakti dan mahasiswa lainnya secara hukum.
"Reformasi ekonomi dengan kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Ekonomi Indonesia belum kunjung membaik. Penyebabnya karena ekonomi Indonesia dikelola dengan cara neoliberal-kapitalisme dan neofeodalisme yang sangat bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yakni demokrasi ekonomi yang berpegang pada prinsip produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan untuk tujuan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran seseorang saja," tegasnya.
Sementara pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini persis seperti masa Orba, yakni dikuasai oleh konglomerat bersama oligarki dalam bentuk kolusi dan nepotisme melahirkan sedikit orang kaya namun banyak orang miskin.
"Jumlah orang miskin Indonesia saat ini 27,55 juta jiwa (10,19 persen dari total penduduk). Dampak terparah dari pengelolaan ekonomi neoliberal-kapitalisme dan neofeodalisme yang terlanjur mendarah daging adalah ketidakpercayaan kepada kekuatan modal sendiri atau berdiri diatas kaki sendiri (berdikari). Neoliberalis menggantungkan ekonomi suatu negara kepada modal (investasi) asing serta tidak mampu membatasi produk asing (impor)," terang Sahat.
Selain itu, ketergantungan dan perburuan rente pada impor dan rendahnya penemuan riset dan inovasi teknologi dalam negeri membuat fundamental ekonomi Indonesia terus melemah. Puncak ekonomi neoliberal kapitalisme dan neofeodalisme yang rapuh itu bisa terlihat nyata pada pertumbuhan ekonomi kuartal I Tahun 2020 yang hanya sebesar 2.97 persen.
"Sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal II hingga kuartal IV tahun 2020 berturut-turut minus 4,19 persen minus 3,49 persen dan minus 2,19 persen," kata Sahat.
Adapun di kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74 persen. Seandainya fundamental ekonomi Indonesia kuat, maka dampak pandemi Covid-19 tidak akan menyebabkan Indonesia terpuruk terlalu lama.
"Bandingkan dengan Vietnam yang kini angka pertumbuhan ekonominya positif 4,48 persen meski sama-sama menghadapi pandemi Covid-19," ujar Sahat.
Selain itu, Sahat menjelaskan bahwa penegakan hukum yang adil. Sampai saat ini hukum merupakan hal yang menakutkan bagi orang miskin. Hukum dijadikan alat pemukul kepada yang lemah dan menjadi alat memenangkan kepentingan kelompok yang berkuasa. Hukum bukan lagi proses mencari keadilan, namun membela kepentingan perorangan atau kelompok.
Hal itu menurutnya persis seperti masa Orba berkuasa. Ancaman Neo Urba semakin nyata dengan pelemahan lembaga hukum seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi.
"Kami mendukung setiap upaya melahiran pegawai KPK yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan. Namun saat yang sama kami bertanya kepada pemerintah dan Presiden Jokowi kenapa tes wawasan kebangsaan tidak dilakukan juga kepada pegawai BUMN, para dosen perguruan tinggi negeri bahkan kepada TNI/Polri," jelasnya.
Sahat juga menceritakan bahwa Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiyarto melakukan perlawanan kepada kelompok pegawai PT Pelni yang terlibat radikalisme.
Selain di PT Pelni, kegiatan radikalisasi pegawai BUMN masih terus berlangsung di PTPN III (Holding), PT Pelindo I, PT Semen Padang, BTN dan sejumlah Bank BUMN. Namun Menteri BUMN, Erick Thohir, tidak melakukan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai BUMN seperti kepada pegawai KPK.
"Padahal Erick Thohir mengaku telah menerima data pegawai BUMN yang terpapar radikalisme dari Menkopolhukam Mahfud MD," jelasnya.
"Selain pegawai BUMN, kampus yang didalamnya terdapat interaksi dosen dan mahasiswa yang seharusnya menjadi tempat ilmu pengetahuan dan menghormati keberagaman, ternyata menjadi tempat bibit radikalisme dan intoleransi. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir pernah menyebut sebanyak 10 perguruan tinggi terpapar radikalisme yakni Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Mataram. Adapun di Pulau Sumatera kami melihat gejala radikalisme dan intoleransi menguat di Kampus Universitas Sumatera Utara, Universitas Riau dan Universitas Andalas," sambung Sahat.
Sahat juga menambahkan, pernyataan Menteri Pertahahan Ryamizard Ryacudu di Mabes TNI pada Rabu 19 Juni 2019, dari sekitar 975.750 anggota TNI, ada 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Penyebabnya karena wawasan kebangsaan dan pemahaman terhadap Pancasila yang bermasalah.
"Menghentikan dan melawan politik transaksional yang melahirkan oligarki. Parpol sebagai lembaga politik formal yang berkompetisi merebut suara rakyat dalam setiap Pemilu untuk tujuan berkuasa, sejatinya melahirkan pemimpin reformis. Namun faktanya pemimpin parpol tingkat pusat hingga daerah menjadi oligarki dan 'gank politik' atau berkoalisi taktis demi kekuasaan sehingga mengubur sikap pembaharuan atau reformis. Kondisi ini mengancam keutuhan NKRI. Apalagi sejak era multi partai Pemilu 1999 hingga 2019, tidak ada satu partai pun yang menang mutlak atau single majority. Watak pragmatisme pimpinan parpol menyebabkan masyarakat terbelah," tambahnya.
Selain itu, Majelis Perhimpunan Pergerakan 98 juga mendukung sikap untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan melawan setiap upaya pelemahan pemberantasan korupsi.
"Dan mendukung pembatasan masa jabatan presiden dua periode sesuai semangat reformasi," tegas Sahat.
(JW/EAL)