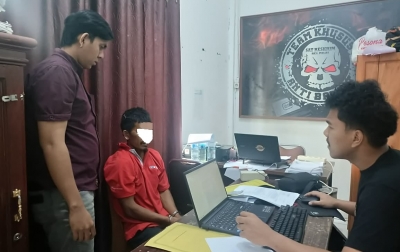Masyarakat harus memahami bahwa Danau Toba bukan hanya danau biasa ia adalah tempat yang sangat spesial, warisan geologi dunia yang tak ternilai,” tegas Jose Brilha, asesor UNESCO Global Geopark, saat evaluasi Kaldera Toba pada Juli 2025.
Ungkapan ini bukan sekadar apresiasi atas keindahan alam, tetapi juga peringatan bahwa Kaldera Toba adalah simpul kehidupan yang menyatukan alam, manusia, dan budaya. Ia bukan hanya lanskap megah hasil letusan purba, tetapi juga pusat ekosistem dan budaya Sumatera Utara dikelilingi hutan sebagai paru-paru alam, sungai yang menyuburkan pertanian, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari air, pangan, dan pariwisata. Toba juga menjadi ruang spiritual dan identitas kolektif masyarakat Batak yang diwariskan lintas generasi.
Namun di balik pesonanya, Danau Toba kini menghadapi krisis lingkungan yang serius dan kompleks. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kualitas air di kawasan ini terus menurun, ditandai oleh pencemaran ringan hingga sedang akibat limbah rumah tangga, sisa pakan ikan, serta limbah industri yang tidak terolah.
Kadar nitrat, amonia, dan fosfat meningkat tajam, mempercepat proses eutrofikasi dan menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Ledakan alga pun tak terhindarkan, menurunkan kejernihan air dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Fenomena ini telah berdampak nyata, seperti kematian lebih dari 100 ton ikan di Samosir pada Oktober 2020, yang kembali terulang di Pangururan pada Juli 2025.
Kondisi ini diperparah oleh budidaya ikan secara intensif melalui keramba jaring apung (KJA), praktik pertanian padi konvensional yang bergantung pada input kimia, serta penggundulan hutan di wilayah tangkapan air yang mempercepat sedimentasi dan menurunkan daya resap tanah.
Di wilayah Pangururan, kadar nitrit, nitrat, dan amonia telah melampaui baku mutu nasional, sementara nilai BOD dan COD yang tinggi mencerminkan stres ekologis akibat beban pencemaran yang terus meningkat. Pemerintah bahkan telah membatasi penggunaan KJA karena dampaknya terhadap danau, namun konsekuensinya terhadap ketersediaan pangan lokal terasa nyata dengan berkurangnya pasokan ikan sebagai sumber protein memengaruhi ketahanan gizi keluarga..
Krisis ini tidak berhenti pada lingkungan ia merambah ke kesehatan masyarakat. Peningkatan kasus penyakit kulit, diare, ISPA, serta potensi zoonosis dan keracunan logam berat seperti merkuri dan timbal menjadi ancaman yang semakin nyata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar danau dan bergantung langsung pada air dan hasil perikanan.
Ini adalah gambaran jelas bagaimana kerusakan lingkungan di Danau Toba bukan sekadar persoalan ekosistem, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup dan kesehatan manusia secara langsung.
Srategi untuk mengatasinya masih dilakukan secara sektoral, masing-masing instansi berjalan sendiri tanpa koordinasi yang utuh. Masalah pencemaran air ditangani oleh sektor lingkungan, meningkatnya penyakit kulit, diare, ISPA dan Stunting ditangani oleh sektor kesehatan, sementara tekanan terhadap keanekaragaman hayati diserahkan kepada sektor pertanian dan peternakan.
Padahal, ketiga aspek ini saling terkait erat dan membentuk satu kesatuan sistem kehidupan. Minimnya pendekatan lintas sektor dan transdisipliner inilah yang membuat krisis di Danau Toba terus berulang dan tak kunjung tuntas. Setiap intervensi menjadi reaktif, jangka pendek, dan tidak menyentuh akar persoalan. Pendekatan One Health menawarkan kerangka kolaboratif yang menyatukan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu sistem analisis dan solusi.
Tanpa sinergi lintas sektor dan keilmuan, upaya penyelamatan Danau Toba hanya akan menjadi tambal sulam tanpa arah yang berkelanjutan. Jika Kaldera Toba sakit, maka Sumatera bernapas dalam kesakitan. Inilah saatnya kita beralih dari pendekatan sektoral menuju kolaborasi lintas bidang.
Pendekatan One Health menawarkan cara pandang yang holistik dan terintegrasi, yang memandang manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan sistem kehidupan. Hanya dengan pendekatan inilah, Kaldera Toba dapat benar-benar terselamatkan.
Konsep One Health semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan kesehatan global yang bersifat lintas sektor dan kompleks, terutama dalam menghadapi penyakit infeksi baru maupun yang kembali muncul.
Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu sistem yang terpadu dan saling bergantung. Pemahaman mendalam mengenai pendekatan ini penulis peroleh saat mengikuti Simposium Internasional 2025 tentang Riset dan Praktik One Health, yang diselenggarakan di Shenzhen, China, pada 28–30 Juni 2025.
Mengusung tema “Dari Visi Menuju Kolaborasi dan Aksi”, simposium ini mempertemukan para pakar, pemangku kepentingan, dan praktisi dari berbagai disiplin untuk mendiskusikan solusi terintegrasi dalam menghadapi krisis kesehatan yang makin kompleks.
Salah satu pendekatan inovatif yang menarik perhatian dalam forum tersebut adalah Lawa Model Concept, yang dikembangkan oleh Tangkawattana dan Sripa di Thailand. Model ini menjadi contoh nyata penerapan prinsip One Health dan EcoHealth dalam pengendalian penyakit menular berbasis lingkungan, khususnya infeksi Opisthorchis viverrini (cacing hati).
Penyakit ini memiliki keterkaitan erat dengan perilaku masyarakat, kondisi sanitasi, dan ekologi perairan, sehingga memerlukan intervensi yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Lawa Model membuktikan bahwa dengan pendekatan holistik, partisipatif, dan berbasis komunitas, solusi kesehatan dapat dirancang lebih efektif dan berkelanjutan.
Adapun komponen inti dari Lawa Model meliputi enam elemen yang saling memperkuat. Pertama, System Thinking, yaitu cara berpikir sistemis yang memetakan keterkaitan antara manusia, hewan, dan lingkungan.
Kedua, Knowledge to Action, yang menekankan pentingnya menerjemahkan hasil riset ke dalam kebijakan dan aksi nyata. Ketiga, Gender and Social Equity, yang menjamin keadilan dan inklusi seluruh kelompok sosial.
Keempat, Sustainability, memastikan intervensi bersifat jangka panjang dan tertanam dalam struktur komunitas. Kelima, Participation, yakni pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses. Dan keenam, Transdisciplinary Research, yang mendorong kolaborasi lintas ilmu untuk menjawab tantangan lokal secara langsung.
Kaldera Danau Toba menghadapi tantangan lingkungan dan kesehatan yang saling berkaitan, mulai dari pencemaran air akibat limbah rumah tangga dan keramba jaring apung (KJA), degradasi kawasan hutan, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sumber pangan bergizi.
Dalam konteks ini, pendekatan Lawa Model sangat relevan untuk diadaptasi guna merespons persoalan secara holistik, partisipatif, dan berbasis komunitas.Beberapa masalah kesehatan dan ekologi yang dapat dikelola melalui adaptasi Lawa Model di kawasan Toba antara lain: meningkatnya kasus diare endemik, ISPA, dan penyakit kulit akibat kualitas air yang menurun; risiko zoonosis seperti leptospirosis dari kontak antara manusia dan hewan dalam lingkungan tercemar; serta ancaman keracunan logam berat seperti merkuri dan timbal dari akumulasi limbah.
Selain itu, pembatasan keramba untuk alasan lingkungan telah berdampak pada ketersediaan ikan sebagai sumber protein utama, yang berpotensi memperburuk ketahanan gizi keluarga.
Strategi implementasi Lawa Model di Toba dapat disesuaikan melalui enam komponen utama. Pertama, System Thinking dilakukan dengan memetakan keterkaitan antara limbah KJA, degradasi air, munculnya penyakit, dan ekonomi lokal.
Kedua, Knowledge to Action, yaitu mendorong hasil riset tentang kualitas air dan dampak kesehatannya menjadi dasar kebijakan publik. Ketiga, Participation, dengan melibatkan masyarakat adat Batak, kader posyandu, guru, petani, nelayan, dan tokoh agama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
Keempat, Transdisciplinary Research, melalui kolaborasi lintas institusi seperti USU, UHN, UGM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan sektor pariwisata. Kelima, Gender & Equity, dengan memberdayakan perempuan sebagai pengelola sumber daya air dan pangan komunitas.
Terakhir, Sustainability, yakni memastikan program berjalan jangka panjang melalui dukungan anggaran lintas sektor dan penguatan kapasitas lokal seperti kader desa dan program sekolah.
Untuk mewujudkan strategi ini, sejumlah kegiatan lapangan dapat dijalankan, antara lain: survei kualitas air dan sanitasi rumah tangga, pelatihan kader lingkungan dan kesehatan berbasis desa, serta program sekolah sehat yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal.
Modul pembelajaran tentang air, kesehatan, dan budaya Batak juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Selain itu, pemulihan ekosistem melalui reboisasi daerah tangkapan air dan pengolahan limbah terdesentralisasi akan memperkuat daya dukung lingkungan.
Forum dialog rutin antara petani, nelayan, pelaku wisata, dan pemerintah desa juga penting untuk membangun kesepahaman mengenai batas daya dukung danau, agar pembangunan tetap selaras dengan kelestarian lingkungan.
Melihat kompleksitas persoalan lingkungan dan kesehatan di Kaldera Danau Toba, sudah saatnya semua pihak pemerintah daerah dan pusat, akademisi, sektor swasta, hingga komunitas local bergerak bersama dalam kerangka kolaboratif.
Pembentukan Tim Kolaborasi One Health Kaldera Toba menjadi langkah strategis yang mendesak. Tim ini harus lintas sektor dan disiplin, melibatkan unsur kesehatan, lingkungan, peternakan, pendidikan, tokoh adat, dan masyarakat sipil.
Tugas utamanya adalah menyusun peta risiko kesehatan berbasis ekosistem secara terpadu, agar intervensi ke depan tidak lagi reaktif dan sektoral, melainkan berbasis data, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Penulis pernah memimpin langsung program kolaboratif LPPM USU dan PT INALUM melalui CSR di Desa Meat Balige yang fokus pada mitigasi risiko lingkungan dan pemberdayaan masyarakat Danau Toba.
Kegiatan tersebut meliputi pelatihan kader lokal, edukasi berbasis budaya, penguatan kelembagaan desa, hingga pengelolaan air dan sanitasi. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah sistem mina padi, yaitu budidaya ikan di sawah sebagai solusi peningkatan ketahanan pangan tanpa membebani danau.
Sayangnya, kerja sama ini terhenti dan perlu dirancang ulang sebagai program berkelanjutan dalam bingkai One Health. Pengalaman ini menunjukkan bahwa sinergi antara akademisi, BUMN, dan masyarakat sangat mungkin dilakukan asal didukung kebijakan dan investasi lintas sektor. Untuk memastikan keberhasilan, diperlukan regulasi yang mendorong pengelolaan kesehatan secara terintegrasi melalui kebijakan lokal maupun nasional.
Sektor pariwisata pun harus dilibatkan, karena keberlanjutan Toba menyangkut ekosistem sekaligus ekonomi ribuan warga yang menggantungkan hidup dari wisata alam dan budaya. Menyelamatkan Toba berarti menjaga napas Sumatera agar tetap hidup.
Sebagai penutup, penting untuk menegaskan kembali bahwa Kaldera Toba bukan sekadar lanskap alamia tetapi adalah nafas kehidupan bagi Sumatera. Segala bentuk kerusakan ekologis di kawasan ini membawa konsekuensi luas, mulai dari kematian massal ikan, meningkatnya penyakit, hingga menurunnya ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Strategi penanganan yang selama ini terfragmentasi dan sektoral terbukti belum mampu menyelesaikan akar persoalan.
Oleh karena itu, pendekatan One Health hadir sebagai solusi yang menjembatani keterkaitan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dengan menerapkan kolaborasi lintas sektor dan transdisipliner, serta mendorong aksi nyata dari pemerintah, akademisi, BUMN, dan masyarakat local seperti yang telah penulis inisiasi dalam program CSR bersama PT INALUM dan integrasi sistem mina padi maka upaya penyelamatan Toba bisa diarahkan menuju keberlanjutan sejati.
Lindungi Kaldera Toba bukan hanya demi ekosistemnya, tapi demi kehidupan Sumatera kini dan nanti, Insya Allah.